
Bhutan memasuki fajar perlahan. Sementara sinar matahari pertama masih menyinari puncak-puncak gunung, Lembah Paro di bawahnya tertutup lapisan kabut tipis bagai selendang sutra. Rerumputan dan pepohonan masih tertutup embun beku, dan aliran kabut tipis melayang di depan ujung sepatu.
Pada pukul 7:00 pagi, rombongan kami meninggalkan hotel di tengah terik matahari keemasan yang menyinari lereng gunung, memulai perjalanan untuk menaklukkan Biara Tiger's Nest-Taktsang Palphug, biara paling suci di Bhutan, yang dianggap sebagai simbol seluruh negara Bhutan.

Masyarakat Bhutan menceritakan sebuah legenda: Guru Rinpoche menunggangi seekor harimau betina (inkarnasi dari permaisurinya, Yeshe Tsogyal). Dari Tibet, beliau terbang ke tebing Paro untuk menaklukkan sesosok iblis. Beliau bermeditasi di sebuah gua selama 3 bulan, membuka era baru bagi agama Buddha di sana.
Dari kisah legendaris itu, Tebing Taktsang dijuluki dengan nama yang mendunia : Sarang Harimau. Berdiri di kaki gunung, memandangi kuil yang menggantung di langit, saya tak kuasa menahan diri untuk bertanya-tanya: Berapa banyak kepercayaan, berapa banyak keajaiban yang telah berkumpul di sini untuk membangun legenda yang tak lekang oleh waktu?

Menurut catatan sejarah, sekitar tahun 1692, Guru Tenzin Rabgye—seorang perwakilan dari silsilah Drukpa Kagyu—membangun sebuah biara di sekitar gua meditasi Guru Rinpoche. Di ketinggian 3.120 m, 900 m di atas dasar lembah Paro, bangunan ini menantang hati manusia sekaligus melawan gravitasi.
Lantai kayu, balkon putih, dan atap cokelat tua bertengger tak menentu di tebing terjal. Orang Bhutan menganggap ini sebagai mahakarya arsitektur mereka, perpaduan antara keyakinan, keterampilan tradisional, dan tekad yang luar biasa.

Tiger's Nest telah berkali-kali diuji oleh api. Pada tahun 1951, kebakaran besar menghanguskan banyak kuil. Pada tahun 1998, kebakaran semakin parah, menghancurkan mural dan patung-patung kuno. Namun, biara tersebut tetap dipugar, mempertahankan gaya arsitektur kunonya oleh para perajin Bhutan. Setiap lapisan kayu yang diganti, setiap dinding yang dipugar membawa serta aspirasi untuk melestarikan jiwa negara.
Bus membawa kami ke tempat parkir di lereng gunung pukul 7.30. Udara dingin menembus jaket, topi, dan sarung tangan kami. Di bawah naungan hutan pinus tua, kuda-kuda pengangkut barang berdiri dalam barisan panjang menunggu penumpang.

Di Bhutan, kuda hanya boleh membawa wisatawan hingga setengah jalan mendaki gunung, sisanya harus dijalani dengan berjalan kaki. Pemerintah negara ini mengatur dengan ketat, tidak ada pedagang kaki lima, tidak ada penduduk di hutan, semuanya dijaga keutuhannya sebagaimana alam menciptakannya.
Jalan setapak itu terbentang di atas tanah merah, lerengnya hampir vertikal. Udara tipis membuatnya sulit bernapas. Baru beberapa langkah, jantungnya berdebar kencang, dan angin dingin membakar pipinya.

Kami mendongak, Sarang Harimau masih jauh, sekecil titik putih yang menempel di tebing. Namun, langit musim gugur cerah, hutan pinus berganti warna kuning, merah, hijau bagai lapisan warna yang tak berujung. Dari atas, angin membawa aroma segar dan manis getah pinus, dan lungta (bendera doa) berkibar, menciptakan suara gemerincing seperti nyanyian dari kejauhan.
Saat itulah semua orang menyadari bahwa perjalanan ini bagaikan ritual memasuki negeri yang sunyi. Baru pukul 10 rombongan tiba di Tiger's Nest Café—satu-satunya tempat peristirahatan di rute tersebut. Terletak di tengah gunung, kafe itu kecil namun hangat. Cangkir-cangkir teh panas mengepul, aroma mentega yak tercium di udara. Angin membawa bunyi lonceng angin yang lembut menyentuh atap.

Dari sini, jika memandang ke atas, Sarang Harimau mulai tampak jelas, bagaikan mimpi yang menggantung di awan. Di bawah, Lembah Paro tampak luas di bawah lapisan kabut tipis, jalan-jalan dan atap-atap desa hanyalah titik-titik kecil.
Setelah istirahat 30 menit, rombongan melanjutkan pendakian. Bagian kedua jalur pendakian terbuka dengan anak tangga batu vertikal, setiap anak tangga terasa seperti mengangkat batu besar di pundak. Semakin tinggi mereka mendaki, semakin sedikit suara yang terdengar, hanya suara angin yang bertiup di antara pepohonan pinus, suara langkah kaki di bebatuan, dan detak jantung mereka sendiri.

Ketika gerbang kayu terbuka, kesan pertama semua orang adalah... keheningan. Biara itu terdiri dari dua blok arsitektur utama yang menempel erat di tebing. Balkon kayu hitam, dinding putih, dan atap segitiga cokelat tua berpadu dengan kabut gunung, menciptakan keindahan yang sakral sekaligus surealis.
Semua ponsel, kamera, dan tas harus ditinggalkan di luar. Pengunjung masuk dengan pikiran kosong, tanpa ada apa pun di antara mereka dan ruang suci ini.

Di 11 ruang vihara yang telah dibuka, patung-patung Guru Rinpoche hadir dalam berbagai postur: penenang, inkarnasi, dan penaklukan iblis. Mural-mural kuno yang dipugar setelah kebakaran tahun 1998 masih tampak hidup, menggambarkan alam kosmologi Vajrayana.
Lebih dalam lagi, terdapat ruang-ruang meditasi yang begitu kecil sehingga hanya bisa diduduki satu orang. Seorang biksu muda berkata: "Orang Bhutan datang ke sini bukan hanya untuk melihat pemandangan. Ini adalah tempat untuk menemukan jati diri." Kata-kata sederhana itu, di ruang yang dipenuhi aroma dupa, semua orang merasa seolah-olah menyentuh bagian terdalam pikiran mereka.

Sebelum meninggalkan kuil, rombongan diantar ke sebuah jurang sempit, di samping air terjun yang mengalir deras dari atas. Di puncak lereng, sebuah kuil kecil berdiri sendiri di antara bebatuan. Di sinilah Yeshe Tsogyal, permaisuri Guru Rinpoche, yang telah menjelma menjadi seekor harimau betina, bermeditasi.
Di atas batu di tepi tebing, masih terawetkan jejak kaki harimau. Meskipun sains dapat menjelaskannya sebagai erosi alami, berdiri di depannya, aku tak ingin akal sehatku bersuara. Ada hal-hal yang paling indah ketika dijaga dengan iman.

Meninggalkan biara pukul 14.00, rombongan mulai menuruni gunung. Semua orang mengira turun akan lebih cepat, tetapi ternyata sama sulitnya. Lereng yang curam membutuhkan konsentrasi lebih tinggi daripada mendaki. Debu menutupi sepatu mereka, dan lutut mereka mulai gemetar karena kelelahan.
Pukul 16.00, rombongan tiba di Tiger's Nest Café. Semua orang kelaparan, dan makan siang yang terlambat terasa sangat menenangkan: nasi putih, sayuran rebus, kentang, dan teh hangat. Anehnya, setelah perjalanan yang begitu sulit, hidangan paling sederhana pun terasa luar biasa lezat.

Setelah istirahat satu jam, rombongan melanjutkan perjalanan menyusuri bentangan terakhir. Hari mulai gelap dan angin dingin bertiup semakin kencang. Senter dinyalakan, menerangi jalan tanah yang berkelok-kelok menembus hutan pinus—pemandangan yang mengingatkan saya pada kisah-kisah perjalanan di negeri dongeng.
Kami tiba di tempat parkir pukul 18.00. Malam telah tiba, dan Lembah Paro separuh gelap gulita, separuh lagi remang-remang cahaya kuning. Menengok ke belakang ke pegunungan di belakang kami, tempat Sarang Harimau kini hanya setitik cahaya redup, saya mengerti mengapa begitu banyak orang menganggap perjalanan ini sebagai tonggak sejarah yang tak terlupakan dalam hidup mereka.

Tiger's Nest merupakan keajaiban arsitektur, legenda religius, tetapi juga tempat seseorang belajar mendengarkan napasnya, belajar bertahan, belajar menyentuh kerendahan hati.
Sumber: https://nhandan.vn/chinh-phuc-tigers-nest-khong-gian-linh-thieng-nhat-cua-bhutan-post924415.html


![[Foto] Kunjungi Hung Yen untuk mengagumi pagoda "karya kayu" di jantung Delta Utara](/_next/image?url=https%3A%2F%2Fvphoto.vietnam.vn%2Fthumb%2F1200x675%2Fvietnam%2Fresource%2FIMAGE%2F2025%2F11%2F21%2F1763716446000_a1-bnd-8471-1769-jpg.webp&w=3840&q=75)
![[Foto] Sekretaris Jenderal To Lam menerima Presiden Senat Republik Ceko Milos Vystrcil](/_next/image?url=https%3A%2F%2Fvphoto.vietnam.vn%2Fthumb%2F1200x675%2Fvietnam%2Fresource%2FIMAGE%2F2025%2F11%2F21%2F1763723946294_ndo_br_1-8401-jpg.webp&w=3840&q=75)

![[Foto] Presiden Luong Cuong menerima Ketua Majelis Nasional Korea Woo Won Shik](/_next/image?url=https%3A%2F%2Fvphoto.vietnam.vn%2Fthumb%2F1200x675%2Fvietnam%2Fresource%2FIMAGE%2F2025%2F11%2F21%2F1763720046458_ndo_br_1-jpg.webp&w=3840&q=75)

![[Foto] Ketua Majelis Nasional Tran Thanh Man mengadakan pembicaraan dengan Presiden Senat Republik Ceko Milos Vystrcil](/_next/image?url=https%3A%2F%2Fvphoto.vietnam.vn%2Fthumb%2F1200x675%2Fvietnam%2Fresource%2FIMAGE%2F2025%2F11%2F21%2F1763715853195_ndo_br_bnd-6440-jpg.webp&w=3840&q=75)


































































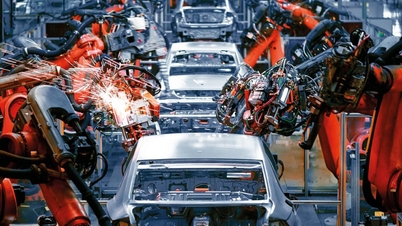






























Komentar (0)