Kehidupan di sekitarku masih mengalir dengan stabil, hari demi hari, dalam siklus pekerjaan, keluarga, dan teman yang berulang. Terkadang, ritme yang familiar itu tak lagi menghadirkan kegembiraan yang sama seperti di awal. Aku mengerti, itu wajar. Jadi, setiap kali aku punya waktu untuk diri sendiri, aku ingin keluar dari siklus itu. Dan ketika hasrat itu cukup kuat, aku kembali ke pegunungan dan hutan.
Di era transformasi digital, mempersiapkan perjalanan tak lagi sulit. Hanya dalam satu sore, saya bisa menyelesaikan semua urusan: menelepon pemandu yang familiar, memesan tiket bus, menyepakati harga, dan tinggal menunggu keberangkatan. Perjalanan ini membawa saya kembali ke alam liar, mengikuti seruan musim bunga chi pau ungu di lereng Gunung Ta Chi Nhu.

Puncak Ta Chi Nhu terletak di antara Desa Xa Ho, Tram Tau, Lao Cai ( Yen Bai lama) dan Desa Nam Nghep, Kecamatan Ngoc Chien, Provinsi Son La. Sebelumnya, orang-orang memilih jalur dari Tram Tau, tetapi jalannya curam dan penuh bukit berbatu yang gundul. Sejak jalan beton yang menghubungkan Nam Nghep dengan Kecamatan Ngoc Chien selesai dibangun pada awal tahun 2025, desa terpencil di tengah hutan ini tiba-tiba menjadi tempat berkumpul bagi para penggemar trekking.
Bus malam membawa saya ke Nga Ba Kim, Pung Luong, Mu Cang Chai, sebelum fajar. Hujan gerimis dan angin dingin menerpa begitu saya turun dari bus, membawa serta hawa dataran tinggi, yang sangat berbeda dengan cuaca panas dan lembap di kampung halaman saya. Porter sudah ada di sana sejak sore sebelumnya untuk menyiapkan barang-barang saya dan menjemput saya di motel terdekat. Setelah kelima anggota rombongan berkumpul, kami sarapan bersama, berkenalan, dan menunggu taksi yang akan mengantar kami ke Desa Nam Nghep.
Kami beruntung tiba di Nam Nghep di musim hawthorn yang sedang masak. Gugusan buahnya menggantung di dahan-dahan, kemerahan seperti pipi seorang gadis muda, bergoyang tertiup angin. Apel-apelnya menggantung berat di dahan, rendah, dan mudah dipetik hanya dengan sekali uluran tangan. Saya memetik sebuah buah beri, mengusapkannya ke baju, lalu menggigitnya dalam-dalam. Rasa manis bercampur sedikit sepat menyebar ke seluruh mulut, menyegarkan saya. Menariknya, ini pertama kalinya saya memetik dan memakan buah yang selama ini hanya saya kenal dari toples-toples anggur.

Kami tersesat di hutan hawthorn, tetapi pendakian gunung baru saja dimulai dan masih jauh. Kami saling mengingatkan untuk berjalan lebih cepat agar bisa mengejar ketertinggalan. Dari kaki gunung setinggi 1.200 m hingga puncaknya, rute pendakian sekitar 18 km pulang pergi, berlangsung dua hari satu malam, membutuhkan kekuatan dan keterampilan fisik dasar. Target hari pertama adalah mencapai pondok peristirahatan di ketinggian 2.750 m, yang diperkirakan akan tiba sore hari.
Gerimis. Pepohonan tinggi menaungi jalan setapak, lumut menutupi akarnya. Hutan yang lebat dan misterius membuat langkahku lebih riang. Hujan mendinginkan keringatku. Angin bertiup kencang, hujan semakin deras, memaksaku mengenakan jas hujan. Melewati hutan, kami melintasi perbukitan liar, kedua sisinya penuh semak belukar, pakis, dan tunggul-tunggul pohon hitam yang bengkok. Di tengah hujan, seluruh rombongan berjalan dalam diam. Langkah kaki kami perlahan-lahan menjadi akrab, napasku bercampur dengan suara hujan yang turun, membuatku tiba-tiba merasa kecil, melebur ke dalam pegunungan dan bukit-bukit yang luas.
Kemudian, sekali lagi, kami dipeluk dalam rindangnya pepohonan hijau hutan purba. Pemandangan yang memukau seakan menjawab pertanyaan mengapa rute Nam Nghep begitu menarik bagi para pencinta hutan. Sesampainya di dataran, kayu-kayu gergajian dijadikan tempat istirahat. Makan siang sederhana berupa nasi ketan putih, beberapa potong babi gulung garam dan cabai, disantap di tengah hujan di bawah naungan dedaunan, bersama teman-teman, menjadi kebahagiaan yang tak terlupakan. Setelah makan, kami memunguti sampah yang kami bawa, hanya meninggalkan jejak kaki di jalan setapak, lalu melanjutkan perjalanan.

Dari sini ke rumah peristirahatan sekitar tiga jam. Jalan setapak menembus hutan, harus menyeberangi tiga atau empat aliran sungai, lereng demi lereng menempel di lereng gunung, baru setelah mencapai aliran sungai turun, lalu mendongak untuk melihat lereng curam yang menantang kemauan. Namun di lereng-lereng itulah pemandangan terbuka dengan indah, bagiku, itulah momen terindah. Suara aliran sungai bergema dari jauh seolah menuntun jalan. Melewati tebing, kami turun ke dasar sungai. Duduk di atas batu, aku mencelupkan tanganku ke dalam air yang jernih dan dingin, lalu mengangkatnya ke wajahku. Di atas, air dari gunung yang tinggi mengalir deras, menciptakan buih putih. Di bawah, aliran sungai mengalir melalui celah-celah bebatuan, mengalir tanpa henti.
Berdiri di hadapan pemandangan itu, aku merasa kecil, hatiku dipenuhi cinta pada pegunungan dan hutan. Ibu Pertiwi seakan menyejukkan dan menyirami jiwa-jiwa yang kering karena hiruk pikuk mencari nafkah. Di tengah sore yang hujan di hutan, di tepi sungai yang sejuk, jiwaku seakan dibasuh, dilembutkan kembali bagai pita sutra, bagai sungai yang mengalir tanpa lelah. Dalam diriku muncul cinta akan kehidupan, rasa syukur, dan ketenangan.
Dari sini, hanya ada satu lereng lagi, tetapi di lereng-lereng terjal itu terdapat gubuk peristirahatan di tengah hutan, tujuan yang kami tuju. Dengan setiap langkah berat, napas berat, dan keringat, semua orang bertanya kepada porter: Apakah kita hampir sampai? Ia sudah terbiasa dengan pertanyaan ini, ia hanya tersenyum lembut, sepatu botnya yang berlumpur masih bergerak cepat: Hanya ada dua sungai lagi! Tepat ketika kami pikir kami sudah kelelahan, kami menangis tersedu-sedu ketika melihat gubuk peristirahatan itu muncul di kabut putih di kejauhan. Kami sampai! Seluruh kelompok berteriak.
Tempat perlindungan itu luasnya sekitar 80 meter persegi, cukup untuk menampung lebih dari 30 orang, dibangun di atas tebing yang cukup datar. Di bawahnya, aliran sungai mengalir deras; di sekitarnya hanya pepohonan, awan, dan angin. Di ketinggian ini, kabut dan dingin merembes melalui setiap celah di dinding. Untungnya, kami punya "penyelamat", api yang dinyalakan oleh kuli angkut. Kayunya basah, butuh waktu lama untuk menyala. Asap tajam mengepul di sekitar tungku, tetapi semua orang mengobrol dan berkerumun, berbagi kehangatan dari api merah. Teman-teman pendaki yang baru bertemu pagi itu, setelah perjalanan yang sulit, duduk berdekatan, dan percakapan menjadi lebih alami dan hangat.

Porter itu kini menjelma menjadi juru masak yang terampil. Ia dengan cepat memotong ayam, mencuci sayuran, menyiapkan kaldu, dan merendam daging. Malam pun tiba dengan cepat. Di sekelilingnya gelap gulita, angin bersiul di sela-sela dedaunan dalam kabut, entah nyata atau ilusi. Dalam dingin, di bawah cahaya senter yang berkelap-kelip, di sekitar api yang menyala-nyala, kisah-kisah perjalanan dan kehidupan diceritakan.
Anggur kental pun dituang. Porter mengangkat gelasnya, mengucapkan beberapa patah kata sambutan, semua orang bersorak dan minum, membuka makan malam secara resmi setelah seharian mendaki yang melelahkan. Hari pertama memang selalu yang tersulit, jadi hidangan ini adalah yang terbaik. Kami makan dan minum sepuasnya, lalu semua orang mencari tempat untuk beristirahat lebih awal agar bisa bangun tepat waktu untuk perjalanan berikutnya besok pagi.
Malam itu dingin. Pintu gubuk tertutup rapat, tetapi angin dan embun masih merayap masuk. Untungnya, selimut itu beraroma manusia, menghangatkannya setelah menggigil. Satu per satu, semua orang tertidur, meskipun hujan gerimis di luar, berirama di atap seng, berirama di kanvas. Larut malam, hanya suara hujan, angin, dan napas teratur yang terdengar di gubuk itu.
Keesokan paginya, selagi kami masih tertidur lelap, porter sudah bangun, menyalakan kompor, merebus air, menyiapkan kopi, teh, dan sarapan. Saya menyesap kopi hangat di tengah kabut pagi, ketika pegunungan dan hutan masih samar dan tak seorang pun bisa melihat dengan jelas, dan langsung merasakan tubuh saya terbangun dan semangat saya berkobar. Dingin hari ini terasa tidak sekeras kemarin sore.


Perjalanan hari kedua terasa lebih mudah karena kami meninggalkan ransel di pondok. Jalan setapak menuju puncak dimulai dengan jalan setapak berlumpur yang berkelok-kelok menembus lereng gunung yang masih gelap. Akar-akar pohon melilit tanah, menambah suasana mencekam. Kami mendaki dalam diam, hanya terdengar desiran sepatu kami di tanah basah dan napas berat. Semakin tinggi kami mendaki, langit semakin cerah, angin semakin kencang, dan hamparan bunga chi pau berwarna ungu cerah membentang di lereng gunung.
Bunga chi pau menjadi alasan mengapa musim ini, sekelompok anak muda berbondong-bondong ke Ta Chi Nhu. Bunga ini hanya mekar selama sekitar dua minggu, indah dan berwarna ungu. Nama "chi pau" juga menarik, berasal dari jawaban "tsi pau", yang berarti "tidak tahu", dari seorang Mong ketika ditanya tentang bunga ini. Namun, melalui media sosial, nama yang lucu ini menjadi akrab. Sebenarnya, itu adalah rumput madu naga, yang termasuk dalam famili gentian, tanaman obat tradisional.
Semakin dekat kami ke puncak, semakin banyak bunga chi pau yang tumbuh, dan semakin gelap warna ungunya. Dua gadis di rombongan itu asyik berfoto di lautan bunga. Dan di sana, di balik bunga-bunga ungu itu, puncak Ta Chi Nhu muncul. Puncak baja tahan karat yang dingin dan berkilau, terukir dengan ketinggian 2.979 m, dikelilingi oleh lebih dari selusin orang yang telah tiba sebelumnya. Angin bertiup kencang, dan awan beterbangan di mana-mana. Sayangnya, cuaca pagi ini tidak sesuai dengan keinginan kami: lautan awan dan matahari terbit keemasan harus menunggu hingga waktu berikutnya. Tapi tak masalah. Menjejakkan kaki di "atap Yen Bai" sudah menjadi kebanggaan tersendiri.
Dinginnya membuat lensa ponsel berembun. Saya mengeringkan lensa kamera, mengeluarkan bendera merah bergambar bintang kuning yang saya bawa, dan meminta teman saya untuk mengambil foto kenang-kenangan. Foto itu, meskipun tidak secerah yang saya harapkan, tetap menjadi momen terindah: Hari ketika saya menaklukkan Ta Chi Nhu, di tengah angin, awan, langit, dan warna ungu tua bunga chi pau. Sebuah momen sederhana namun membahagiakan.
Sumber: https://baosonla.vn/van-hoa-van-nghe-the-thao/ta-chi-nhu-hoi-tho-nui-rung-va-sac-hoa-chi-pau-AgqIafqNR.html




![[Foto] Sekretaris Jenderal To Lam menghadiri Kongres ke-8 Komite Partai Keamanan Publik Pusat](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/1200x675/vietnam/resource/IMAGE/2025/10/4/79fadf490f674dc483794f2d955f6045)


![[Infografis] Angka-angka penting setelah 3 bulan "menata ulang negara"](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/1200x675/vietnam/resource/IMAGE/2025/10/4/ce8bb72c722348e09e942d04f0dd9729)




















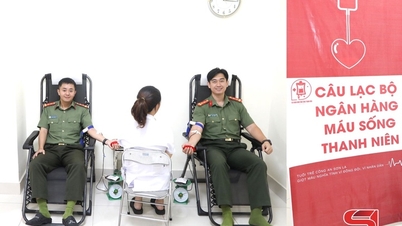
![[Foto] Perdana Menteri Pham Minh Chinh memimpin rapat untuk mengerahkan penanggulangan dampak badai No. 10](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/1200x675/vietnam/resource/IMAGE/2025/10/3/544f420dcc844463898fcbef46247d16)
![[Foto] Siswa Sekolah Dasar Binh Minh menikmati festival bulan purnama, merasakan kembali kegembiraan masa kecil](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/1200x675/vietnam/resource/IMAGE/2025/10/3/8cf8abef22fe4471be400a818912cb85)







































































Komentar (0)