Thao membungkuk untuk mengenakan kembali ranselnya, menarik topinya lebih dekat ke dahi. Di depannya terdapat jalan setapak kecil yang tersembunyi di balik semak-semak, melintasi lereng bukit, tempat yang pernah disebutkan kakeknya dengan suara yang sangat khidmat:
Itu lereng La Tham. Seluruh pasukan mundur ke sana. Tanpa jalan itu, saya tidak akan ada di sini untuk menceritakan kisah ini.
Sudah sepuluh tahun sejak kepergiannya. Thao hanya memiliki secarik catatan tulisan tangan dengan beberapa baris tinta yang buram dan narasi yang terpotong-potong dari ibunya. Namun kini, ia kembali ke sini sendirian, bukan untuk mengerjakan PR-nya, bukan pula untuk menemukan lereng itu lagi.
Sore hari turun dengan cepat di lereng gunung. Sinar matahari hanya sebatas garis tipis di hutan adas manis, membuat bayangan di jalan tanah memanjang seolah mencoba meraih sesuatu yang telah hilang. Thao berjalan perlahan, punggungnya basah oleh keringat, tetapi matanya tak meninggalkan lekukan samar di tanah. Semakin jauh ia berjalan, semakin tenang hatinya, seolah memasuki tempat yang pernah dikunjungi sebelumnya, dan kini hanya suara desahan angin yang tersisa. Thao menyusuri jalan tanah miring yang mengarah ke ujung desa, di mana terdapat sebuah rumah panggung tua dengan lumut menutupi salah satu sisi anak tangganya. Itulah alamat yang ditulis ibunya dalam pesan terakhirnya: Saat kau tiba di desa, tanyakan Tuan Khuyen. Ia masih ingat banyak hal tetapi tak banyak bicara.
Rumah Pak Khuyen terletak di ujung Desa Na Lam, bersandar di lereng bukit, atapnya ditutupi lembaran semen yang sudah pudar, lumut tumbuh di seluruh beranda. Di bawah tangga batu, beberapa pot daun obat mengering, miring tertiup angin sore. Suara alu menumbuk dedak padi bergema pelan dari rumah sebelah, di tempat yang sangat sunyi, sedemikian rupa sehingga Thao bisa mendengar kicauan burung yang mengepakkan sayapnya di antara pohon-pohon prem di samping pagar.
Thao berjingkat menaiki tangga kayu, telapak tangannya masih berkeringat karena perjalanan panjang. Ia mengetuk pelan tiang kayu. Tak seorang pun langsung menjawab. Hanya terdengar derak api di dapur dan suara pelan pisau memotong kayu di dalam rumah panggung. Sebelum Thao sempat berteriak untuk kedua kalinya, suara laki-laki yang dalam, agak serak namun jelas terdengar dari balik layar:
- Kau yang mencari lereng lama, kan?
Dia terkejut.
Ya! Nama saya Thao, saya dari Hanoi , keponakan Pak Loc yang dulu anggota tim gerilya...
Suaranya menghilang, tenggelam oleh suara angin yang berembus menembus dinding. Sebelum ia sempat berkata apa-apa lagi, suara pria itu berlanjut dari dalam ruangan yang gelap:
Keponakan Loc, pemain seruling di tengah gunung? Kamu mahasiswa sejarah, kan?
Thao berdiri diam, tertegun. Ia tak menyangka pria itu tahu, apalagi menyangka seseorang akan mengingat julukan lama itu, nama yang hanya digunakan oleh rekan-rekan kakeknya. Pria berjanggut beruban, berpunggung bungkuk, dan bertongkat itu melangkah keluar. Thao melepas ranselnya dan berdiri diam. Pak Khuyen memberi isyarat dengan tangannya:
Masuklah. Kalau kamu mau tanya soal kemiringannya, kamu harus ikut aku. Tapi tidak hari ini.
Thao mengangguk, masih memegang erat tali ranselnya.
Ya! Saya ingin menggambar ulang peta lereng La Tham. Kalau kamu masih ingat rute retret tahun itu, saya mau ikut.
Pak Khuyen menatapnya, matanya menyipit di bawah sinar matahari sore. Lalu ia tersenyum, senyum ompong:
Aku ingat, tapi garis itu sudah tidak ada di bawah kakiku lagi. Garis itu ada di punggungku, di bekas luka di betisku, pada malam aku berjalan mundur untuk menarik orang yang terluka itu. Untuk menariknya, kau harus menggunakan bukan hanya tanganmu, tapi juga telinga dan lututmu.
Thao mengangguk pelan. Ia tidak sepenuhnya memahami kata-kata itu, tetapi ada sesuatu di hatinya yang baru saja terbangun, sebuah keyakinan atau janji diam-diam bahwa lereng lama itu belum lenyap, jika ada yang berani kembali dengan sepenuh hati.
Keesokan paginya, cuaca terasa dingin. Angin dari hutan adas manis berembus melewati lembah, membawa aroma embun basah dan dedaunan muda. Kokok ayam jantan yang bersahutan bergema dari pintu masuk desa. Thao bangun pagi-pagi sekali. Ia melipat selimut, mengikat buku catatannya, dan memasukkan alat perekam ke dalam sakunya. Di dapur, Tuan Khuyen telah membuat teh lebih awal, sandal karetnya tertata rapi di anak tangga paling bawah, tongkat bambunya disandarkan di samping topi palemnya yang usang. Saat ia melangkah keluar dari pagar bunga aster, Thao mendengarnya berkata:
- Umurku tujuh belas tahun saat mendaki bukit ini. Sekarang umurku sembilan puluh. Tapi jalannya tak banyak berubah. Mungkin mataku yang berubah.
Jalan setapak itu berkelok-kelok di sepanjang lereng gunung. Thao mengikutinya dari belakang, berusaha menghindari menginjak bebatuan berlumut, meskipun Pak Khuyen tidak pernah menyuruhnya melakukannya.
- Dulu, tak ada yang mematahkan daun di hutan, mereka hanya menyapunya dengan lengan baju. Bukan karena takut tersesat, tapi karena takut menimbulkan suara.
Setelah berjalan sekitar satu jam, mereka tiba di sebuah lempengan batu datar yang menghalangi jalan setapak. Permukaannya tertutup lumut, tetapi tepinya cekung seolah-olah seseorang telah duduk di sana untuk waktu yang lama. Pak Khuyen berdiri diam, kepalanya sedikit miring, matanya menyipit.
Di sini, tahun itu, ada yang terluka. Kami tak bisa membawa mereka. Ibu saya meninggalkan terompet di kaki batu ini. Ia menyuruh saya menancapkannya di tanah dan menelepon. Jika ada yang selamat, mereka akan tahu cara kembali.
Thao melihat sekeliling. Angin di sudut gunung ini tidak kencang. Daun-daun hutan menutupi tanah. Di antara dedaunan kering, sebuah lempengan batu bertepi bundar memiliki retakan diagonal seperti garis tulang belakang manusia. Ia berlutut, dengan lembut menyingkirkan setiap lapisan daun, dan menyentuh batu yang dingin dan lembap itu. Tangannya menyentuh lekukan yang pas di telapak tangannya, seolah-olah seseorang telah meletakkan tangannya persis seperti ini. Ia mendongak dan melihat Tuan Khuyen telah melepas jilbabnya, menyeka keringat dari dahinya, dan berkata dengan lembut:
- Kalau ada sesuatu di bawah sana, itu karena ia belum mau pergi. Kalau tidak ada apa-apa, jangan bersedih. Soalnya kalau ada yang kembali, tempat ini akan penuh.
Mata Thao perih, meskipun angin bertiup menerpanya. Ia menarik napas perlahan, meraih ke belakang, dan mengeluarkan pisau kecil itu. Kemudian terdengar suara ujung pisau mengenai sesuatu yang keras. Suaranya kering dan tajam, bukan batu, bukan pula kayu. Ia gemetar dan menggalinya. Sepotong logam kusam muncul, melengkung di bagian atas, berlubang dan retak di sepanjang badannya. Itu adalah terompet kuningan yang rusak, berkarat tetapi masih mempertahankan bentuknya. Di sampingnya ada selembar kain merah kusut, tak lagi utuh, ujung-ujungnya lapuk. Thao menangis tersedu-sedu:
Kakek sayalah yang membawa pria yang terluka itu keluar dari hutan setelahnya dan juga yang mengubur terompet di samping batu. Dia selalu menyebut Lereng Daun Gelap.
Thao membungkus seruling itu dengan kain dan memasukkannya kembali ke saku. Rasa sesak menyesakkan dadanya, seolah ia telah menangkap panggilan, tetapi tidak tahu cara meniupnya dengan benar. Matahari baru saja miring di balik bahu hutan, memancarkan sinarnya ke lempengan batu. Seruling itu, meskipun berkarat, masih memancarkan sedikit warna merah dan emas seperti mata seseorang yang telah kembali untuk mengikuti jejak orang di belakangnya.
Sore pun tiba dengan cepat ketika mereka berdua kembali ke desa. Sungai di hulu desa surut, memperlihatkan bebatuan hijau seperti punggung ikan yang mengapung di baskom sinar matahari sore. Cahaya matahari terbenam mengalir di atap rumah panggung, meluncur di atas tikar bambu anyaman yang biasa digunakan untuk menjemur padi. Angin berhembus membawa aroma asap dapur dan kulit jagung yang terbakar. Thao mencuci tangannya di ujung atap pelana rumah, lalu membawa terompet yang dibungkus handuk ke rumah Pak Khuyen. Penduduk desa mulai berbondong-bondong mendatanginya. Ada yang penasaran, ada pula yang mengikuti rumor tersebut. Seorang pria paruh baya bertanya:
- Itu yang dipakai waktu pemberontakan? Yakin?
Thao mengangguk sedikit:
Saya belum bisa memastikannya, tapi posisinya sudah benar seperti yang dijelaskan. Kalau restorasinya bagus, saya bisa minta dibawa kembali ke sekolah sebagai model relik hidup.
Terdengar gumaman. Seorang perempuan tua berjilbab nila berbicara dengan lembut namun tegas:
- Kalau masih di dalam tanah, berarti itu milik tanah. Orang-orang menguburnya di sini karena mereka tidak bisa mengambilnya. Kenapa kita harus mengambilnya sekarang?
Thao terkejut. Ia meremas pelan tepi kain yang menutupi terompet itu.
Tapi kalau dibiarkan di sini, tak seorang pun akan tahu, ia akan tetap sunyi selamanya. Kalau kita mengembalikannya untuk direstorasi, mungkin lebih banyak orang akan mengingatnya, kurasa.
Wajah Pak Khuyen tanpa ekspresi. Baru ketika ia semakin dekat dengan terompet itu, ia memandang ke luar pintu, ke pegunungan di kejauhan, dan berkata dengan suara tenang:
Orang-orang yang tinggal di hutan tidak butuh siapa pun untuk mengenang mereka, tidak perlu muncul di museum. Mereka butuh seseorang untuk mengunjungi tempat-tempat yang sama yang pernah mereka kunjungi dan memahami mengapa mereka melakukan apa yang mereka lakukan.
Semua orang terdiam. Thao menundukkan kepala. Ia bingung antara tanggung jawabnya sebagai mahasiswa sejarah dan panggilan samar tanah dan hutan. Perempuan tua itu berbicara lagi:
- Kamu boleh mengambilnya. Tapi bagaimana kalau suatu hari nanti ada yang kembali ke sini mencari terompet itu?
Angin bertiup kencang, kain merah yang menutupi terompet berkibar pelan. Thao menunduk dan melihat retakan pada badan perunggu dan noda lumpur kering yang belum sepenuhnya dibersihkan. Ia dengan hati-hati membungkus terompet itu, tetapi tidak memasukkannya ke dalam ransel, melainkan meletakkannya di tangan Tuan Khuyen dan berkata dengan lembut:
Saya ingin mengambil foto untuk mengabadikan kenangan bersama keluarga. Silakan bawa foto-foto ini ke museum setempat untuk diserahkan kepada pihak pengelola!
Thao menunda perjalanan pulangnya. Ia mengajukan perpanjangan penelitian di Desa Na Lam, sebuah keputusan yang mengejutkan pembimbingnya dan membuat ibunya menelepon tiga kali untuk bertanya lagi:
- Apa rencanamu di sana? Bagaimana kalau penelitiannya tidak membuahkan hasil?
Dia hanya membalas:
- Sejarah tidak ada dalam laporan, Bu.
Keesokan paginya, ia dan Pak Khuyen memasang papan kayu di lantai rumah panggung yang sedang dikeringkan, menempelkan foto-foto yang ia cetak dari dokumen: foto lereng La Tham, foto bendera. Terompet terbunyi dengan khidmat di atas selendang nila yang baru. Anak-anak berdatangan, beberapa membawa sangkar burung, beberapa menggendong adik-adik mereka. Thao menggelar tikar, tidak menyebut tempat ini sebagai ruang kelas, hanya berkata dengan sangat lembut:
- Tahukah kamu, jalan yang kamu lalui untuk memetik blackberry kemarin dulunya adalah tempat peristirahatan militer?
Mereka menggelengkan kepala, mata mereka terpaku pada foto-foto dan terompet aneh itu. Suara Thao masih selembut kabut:
- Jadi hari ini, saya akan menceritakan kisah itu. Tapi Anda harus duduk diam dan mendengarkan dengan kedua telinga dan kaki Anda.
Anak-anak penasaran dan perlahan-lahan menjadi tenang. Thao menggunakan arang untuk menggambar diagram di papan kayu.
- Di sinilah seorang tentara terluka. Di sinilah seorang ibu meninggalkan terompetnya.
Siapa pun yang lewat di sana harus menundukkan kepalanya.
Tuan Khuyen duduk di sampingnya, tidak menyela, hanya sesekali mengingatkan:
- Dulu belum ada peta. Kita hanya melihat bintang-bintang dan mendengarkan kicauan ikan kayu.
Sore harinya, Thao mengajak anak-anak kembali mendaki lereng, masing-masing membawa batu untuk menandai jalan. Salah satu dari mereka bertanya:
- Saudari, apakah orang mati melihatku berjalan lewat?
Thao berhenti sejenak, menatap ke atas ke puncak pohon yang tak berangin:
- Jika kamu menyebut nama mereka di tempat mereka berbaring, mereka pasti akan mendengar.
Pada malam harinya, gadis kecil itu membawa sebatang adas bintang muda dan memberikannya kepada Thao:
- Saudari, aku mematahkannya di tempat terompet itu dikubur. Aku menanamnya di tanah. Kalau ada yang tersesat nanti, pohon ini akan menunjukkan jalan yang benar untuk kembali ke desa.
Thao memegang ranting bunga lawang, tangannya gemetar. Malam itu, ia mengeluarkan buku catatannya, tidak menulis "riset sejarah", melainkan menulis baris lain: Lereng tidak hidup dari kata-kata tercetak, melainkan dari langkah-langkah kecil yang tahu bagaimana caranya diam ketika melewati tempat orang-orang pernah berbaring.
Seminggu setelah terompet tua itu ditemukan, Desa Na Lam mengadakan upacara tanpa pengeras suara dan tak seorang pun bersuara. Pagi-pagi sekali, belasan orang di desa itu, para lansia, beberapa pemuda, anak-anak, dan Thao mendaki lereng La Tham. Mereka membawa sebuah batu pipih yang diambil dari tepi sungai. Permukaan batu itu agak miring, cukup untuk menampung tetesan embun setiap pagi. Sebuah selendang nila menutupinya untuk sementara. Terompet itu diletakkan di atas lempengan batu besar. Thao membawa sebuah pisau ukir kecil. Setelah selendang itu dilepas, ia membungkuk, meletakkan tangannya di permukaan batu yang dingin, dan mengukir setiap kata, perlahan, merata, tanpa menoleh ke belakang. Tak seorang pun bertanya apa yang akan ia tulis. Tuan Khuyen hanya duduk di akar pohon, menghisap rokok lintingan. Setelah ukiran terakhir selesai, Thao menyeka debu dari batu dan melangkah mundur. Matahari baru saja terbit di atas pepohonan adas manis, bersinar miring menembus kanopi, cahayanya berkelap-kelip seolah-olah seseorang baru saja menyalakan api. Pada prasasti batu itu, hanya tertulis satu baris: Seseorang pernah melangkah mundur ke sini agar hari ini aku dapat melangkah maju.
Tak seorang pun berkata apa-apa. Anak-anak menundukkan kepala. Perempuan tua itu membungkus kepalanya dengan selendang dan menangkupkan tangannya, berdoa, menghadap lereng La Tham. Angin hutan bertiup lembut, dedaunan berguguran ke samping seolah-olah seseorang baru saja mundur dari lereng gunung.
Sumber: https://baolangson.vn/con-doc-cu-5062374.html


![[Foto] Da Nang: Air berangsur surut, pemerintah daerah memanfaatkan pembersihan](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/1200x675/vietnam/resource/IMAGE/2025/10/31/1761897188943_ndo_tr_2-jpg.webp)




















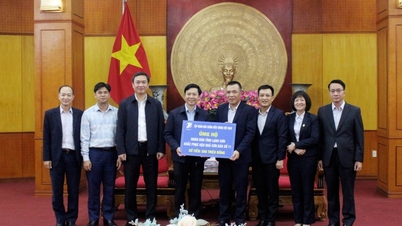






























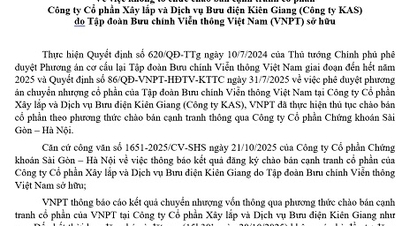

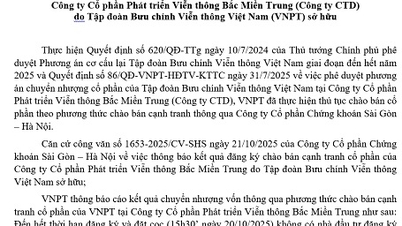
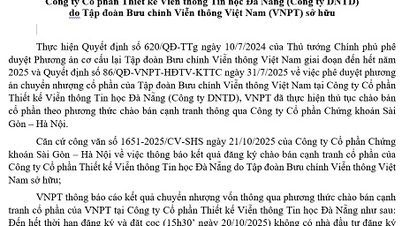














































Komentar (0)