Misi mereka bukanlah untuk melindungi manusia, tetapi untuk melindungi aset paling berharga di zaman kita: data.
Di tengah ketenangan pedesaan Kent, Inggris, berdiri pagar kawat berduri setinggi 3 meter yang mengelilingi sebuah bukit berumput raksasa. Tak seorang pun akan menyangka bahwa, 30 meter di bawah tanah, sebuah pusat komputasi awan canggih sedang beroperasi.
Dulunya ini adalah bunker nuklir, dibangun pada tahun 1950-an sebagai pusat komando jaringan radar Angkatan Udara Kerajaan, tempat para prajurit terpaku pada layar, mencari tanda-tanda pesawat pengebom Soviet.
Saat ini, setelah Perang Dingin berakhir, pusat data ini dioperasikan oleh Cyberfort Group sebagai pusat data yang sangat aman.
Secara antropologis, tempat-tempat ini melanjutkan tradisi umat manusia yang telah lama ada: menyimpan harta karun paling berharga di bawah tanah, sebagaimana nenek moyang kita mengubur emas, perak, dan permata di gundukan tanah. Satu-satunya perbedaan adalah harta karun zaman ini berupa angka 0 dan 1.
Cyberfort tidak sendirian. Di seluruh dunia , warisan Perang Dingin sedang terlahir kembali.
Tempat perlindungan bom tua di Tiongkok, pusat komando Soviet yang terbengkalai di Kyiv, dan bunker Departemen Pertahanan AS semuanya telah dikemas ulang sebagai lokasi penyimpanan data yang “tidak dapat ditembus”.

Pusat data Tencent sedang dibangun di provinsi Guizhou, Cina (Foto: Wired).
Bahkan tambang dan gua pun digunakan kembali, seperti kompleks Mount10 AG - "Swiss Fort Knox" di pedalaman Pegunungan Alpen atau Arsip Dunia Arktik (AWA) di Norwegia.
Jika bunker nuklir merupakan refleksi arsitektur dari ketakutan akan kehancuran, bunker data masa kini mencerminkan ancaman eksistensial baru: prospek mengerikan hilangnya data.
Data - tambang emas era ini
Para pakar teknologi telah menyebut data sebagai "tambang emas"—sebuah metafora yang semakin nyata karena fakta bahwa data disimpan di tambang yang terbengkalai. Seiring meningkatnya nilai data, semakin besar pula rasa takut kehilangannya.

Pintu baja tebal di luar bunker Cyberfort (Foto: Wired).
Bagi individu, hal ini berarti hilangnya ingatan dan pekerjaan berharga. Bagi perusahaan dan pemerintah , kehilangan data yang serius dapat mengancam pembangunan dan keamanan nasional.
Serangan siber baru-baru ini terhadap Jaguar, Marks & Spencer, dan insiden ransomware yang membuat TravelEx bangkrut adalah contohnya. Menghadapi kemungkinan "kiamat" akibat kehilangan data, berbagai bisnis beralih ke tempat perlindungan ini.
Di dalam area penerimaan bunker Cyberfort, sebuah silinder beton dipajang di balik kotak kaca, memperlihatkan ketebalan dinding bunker yang hampir satu meter. Kekokohan dan kekokohannya sangat kontras dengan metafora "awan" data yang ceria.
Faktanya, tidak ada “cloud,” yang ada hanya mesin; ketika data diunggah ke “cloud,” data tersebut dikirim ke server yang terletak di gedung yang disebut pusat data.
Infrastruktur fisik ini merupakan tulang punggung hampir setiap aktivitas dalam masyarakat modern: mulai dari pembayaran kartu kredit, transportasi, perawatan kesehatan, keamanan nasional, hingga pengiriman email atau menonton film.
"Kebanyakan orang hanya memikirkan keamanan siber—peretas, virus—dan mengabaikan aspek fisiknya," kata Rob Arnold, kepala digital di Cyberfort. "Pusat data konvensional dibangun dengan cepat, tidak dirancang untuk tahan terhadap bom atau pencurian."
Di tengah ketegangan geopolitik, infrastruktur internet menjadi target bernilai tinggi.
“Pelanggan mungkin tidak akan selamat dari kiamat, tetapi data mereka akan selamat,” Rob menyimpulkan.
Pintu masuk bunker adalah pintu baja berat yang dirancang untuk menahan ledakan termonuklir. Di dalamnya, udara terasa dingin dan pengap; untuk masuk lebih dalam, seseorang harus melewati tangga logam, lalu menuruni tangga baja.
Pintu anti-ledakan dan dinding beton ini tampak kuno di hadapan aliran data tak kasat mata. Tapi itu keliru.
Bayangkan "cloud" sebagai rumah yang menampung semua aset digital kita. Seaman apa pun, ia tetap berada di bumi dan dapat dipengaruhi oleh dunia nyata.

Pintu antiledakan di bunker Cyberfort, di dalamnya terdapat sistem server pusat data (Foto: Wired).
Rumah tersebut bisa dibobol pencuri, terkena bencana alam seperti badai, atau bahkan menghadapi risiko kecil seperti hewan yang menggigit kabel. Ketika "rumah" ini bermasalah dan berhenti berfungsi, bahkan hanya beberapa menit, konsekuensi finansialnya sangat besar, mungkin mencapai jutaan dolar.
Insiden Cloudflare, Fastly, Meta, dan CrowdStrike tahun 2024 adalah contoh utama dari kerapuhan ini.
Geografi juga sangat penting. Menempatkan pusat data di negara tertentu membantu pelanggan mematuhi undang-undang kedaulatan data negara tersebut. Bertentangan dengan ilusi awal internet tanpa batas, geopolitik sedang membentuk kembali "cloud".
Saat pintu ledakan terakhir bunker Cyberfort terbuka, keberadaan ruang server - jantung benteng - terungkap.
Ratusan server ditumpuk rapi dalam rak, berputar dalam lingkungan yang dikontrol ketat untuk mencegah panas berlebih.
Untuk mempertahankan kondisi optimal ini, pusat data mengonsumsi energi dan air dalam jumlah yang sangat besar. Secara global, pusat data menyumbang sekitar 1% dari total permintaan listrik – lebih besar daripada yang dikonsumsi beberapa negara.
Di tengah hiruk pikuk AI yang memicu pembangunan pusat data yang semakin boros energi, internet perlahan-lahan disebut sebagai "mesin bertenaga batu bara terbesar di dunia." Meskipun ada upaya untuk menggunakan energi terbarukan, kenyataannya jelas: Melestarikan data dengan segala cara meninggalkan jejak karbon yang sangat besar.
Warisan abadi atau utang seumur hidup?
“Bunker ini dibangun agar tahan lama, seperti piramida,” kata Richard Thomas, kepala keamanan di Cyberfort.

Ruang server di dalam bunker Cyberfort (Foto: Wired).
Perbandingannya sungguh mendalam. Bunker dirancang untuk mengangkut isinya melintasi waktu. Demikian pula, raksasa teknologi seperti Apple dan Google mengubah penyimpanan cloud menjadi layanan seumur hidup.
Mereka menganjurkan pengguna untuk mengarsipkan daripada menghapus, karena hal itu mengunci pelanggan ke dalam paket langganan yang semakin mahal.
Ruang penyimpanan perangkat semakin mengecil, memaksa pengguna untuk bergantung pada "cloud". Dan setelah berkomitmen pada satu penyedia, beralih menjadi sangat sulit.
Pengguna menjadi penimbun digital, terikat pada layanan yang sebenarnya bukan milik mereka. Banyak pakar teknologi berpendapat bahwa jika kita benar-benar menganggap data sebagai emas, mungkin pengguna seharusnya dibayar untuk menyimpannya, bukan sebaliknya.
Kelangsungan data – baik yang disimpan dalam brankas atau akun cloud “seumur hidup” – bergantung pada volatilitas pasar, ketahanan infrastruktur, dan organisasi di baliknya.
Sumber: https://dantri.com.vn/cong-nghe/hoi-sinh-di-san-thoi-chien-tranh-lanh-thanh-cac-trung-tam-du-lieu-20250928194557290.htm










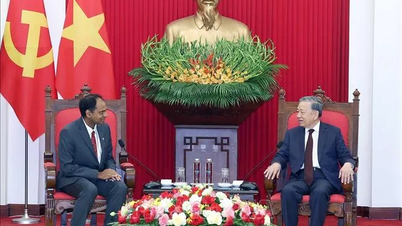












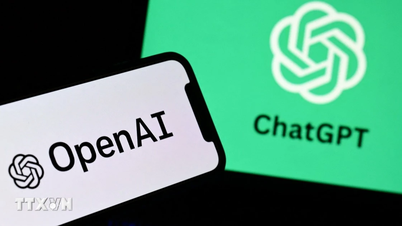





























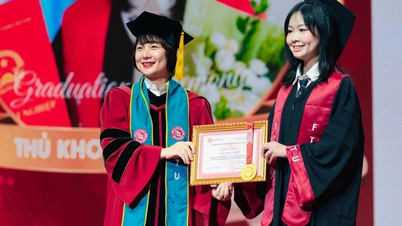














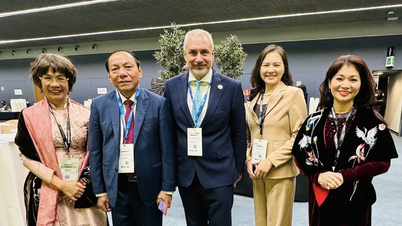




































Komentar (0)