Turun dari bus, menghirup udara segar, mendengarkan panggilan pegunungan dan hutan, saya diam-diam merenungkan keunikan desa Thailand yang terletak di antara desa-desa Mong—sebuah daya tarik tersendiri atau perpaduan budaya yang luar biasa. Sambil memegang buku catatan kecil, saya mulai menulis seperti biasa untuk para jurnalis—tetapi kali ini, saya ingin memperlambat langkah.

Jalan yang curam dan berliku membuat saya mual, tetapi ketika saya melihat atap-atap menjulang di antara pegunungan, semua rasa lelah saya hilang. Meskipun komune Mu Cang Chai sangat tinggi, cara orang Thailand memilih tempat untuk membangun rumah selalu sama di mana pun.
"Orang Thailand hidup di tepi air" adalah pepatah rakyat yang merujuk pada cara hidup yang bergantung pada sungai dan aliran air untuk bertani dan beraktivitas sehari-hari. Oleh karena itu, Ban Thai di komune Mu Cang Chai menyusuri aliran sungai yang berkelok-kelok, di samping hamparan sawah yang panjang, menciptakan suasana Ban Thai yang damai dan berkesan.
Di jalan beton menuju desa, mudah untuk bertemu orang-orang Thailand yang ramah, yang selalu menyambut tamu dengan senyum lembut dan mata secerah sungai. Homestay milik Ibu Dieu Thi Hien adalah tujuannya. Kesan pertama saya adalah di sini, semuanya berjalan sangat lambat, bukan karena mereka malas, tetapi karena mereka menjaga ritme alam yang tetap stabil.
Pada hari pertama di Ban Thai, saya terbangun pagi-pagi sekali karena suara kokok ayam jantan. Saya mengikuti suara kokok itu ke halaman dan melihat api unggun menyala di dapur, sementara Bu Hien mengaduk pelan panci berisi nasi ketan. Nasi ketan ungu yang bercampur aroma daun pandan dan aroma padi gogo yang menyengat mengingatkan saya pada masakan pedesaan masa kecil saya.
Orang Thailand menyantap hidangan asin yang mengenyangkan untuk mengawali hari kerja, tetapi sarapan mereka tidak terburu-buru. Mereka duduk melingkar, mengobrol, dan saling bercerita tentang kabar desa. Di sini, makan seolah menjadi ritual penyambung lidah.

Para tetua di rumah bercerita tentang musim padi, bagaimana mereka memilih benih padi, dan panen. Setiap kisah diceritakan perlahan, diiringi dengan gerakan lembut seperti mengambil mangkuk, menyendok nasi ketan, dan saling memberi makanan lezat. Saya tiba-tiba menyadari bahwa ketika orang hidup dan makan dengan perlahan, mereka punya waktu untuk berbincang, mengenang asal-usul makanan, dan menghargai keringat serta jerih payah mereka sendiri dan para pekerja.
Saya mengikuti Ibu Hoang Thi Ha, seorang perempuan Thailand berusia empat puluhan, untuk mengunjungi ladang. Ia mengenakan sanggul tinggi, kemeja hitam gelap, dan kakinya penuh bekas kerja keras. Ia berjalan perlahan sambil memegang pisau kecil. Mengunjungi ladang hanyalah pekerjaan sampingan, pekerjaan utama Ibu Ha adalah memetik sayuran untuk makan siang.
Dengan tangan lincahnya memotong sayuran liar di pinggir jalan, Ibu Ha perlahan memandangi sawah yang mulai menua. Ia bercerita tentang membajak dan menanam, setiap musim tanam merupakan siklus yang berulang, menandai pergantian musim, interaksi antara manusia dan bumi.
Ia juga bercerita tentang bagaimana ibunya mengajarinya cara menanam padi secara bertahap, cara mendengarkan suara hujan untuk mengetahui kapan harus menanam dan memindahkan tanaman. "Ibu saya tidak banyak bicara. Ia hanya melakukan dan menunjukkannya kepada saya. Tindakan itu lebih penting daripada kata-kata," ujar Ibu Ha kepada saya.
Saya merasakan filosofi hidup Thailand - hidup mengikuti irama tanah, lebih percaya pada pengalaman tradisional ketimbang kata-kata indah.
Malam hari di desa adalah saat orang dewasa berkumpul, terutama bagi keluarga yang menjalankan bisnis pariwisata . Tak banyak telepon, tak ada televisi yang berisik; yang ada hanyalah api unggun yang berkelap-kelip, bisikan-bisikan, dan kisah-kisah yang diceritakan dari api unggun. Saya duduk di sebelah seorang seniman desa yang memainkan seruling dan diundang untuk melayani wisatawan di rumah Bu Hien. Bunyi seruling itu dalam dan halus, seolah merangkum nostalgia pegunungan dalam setiap nadanya. Bunyi seruling memanggil satu sama lain, memanggil cinta, memanggil musim yang datang dan pergi.
Ketika suara seruling pan mencapai klimaksnya, tarian lingkaran kecil dimulai. Para gadis dan lelaki menari berirama mengikuti alunan drum kecil yang ramai. Saya melihat mata merah, senyum malu-malu, dan tangan yang tergenggam erat seolah menepati janji. Di sini, cinta juga dipupuk perlahan, tanpa tergesa-gesa. Ritme kehidupan yang lambat membantu orang meluangkan waktu untuk satu sama lain, untuk saling memandang, untuk memahami, dan untuk menunggu...

Pada hari kedua di Ban Thai, saya duduk di beranda rumah ibu mertua Ibu Hien, Ibu Luong Thi Quanh. Meskipun keluarga Ibu Quanh tidak memiliki bisnis pariwisata, mereka sangat senang menyambut tamu. Ibu Quanh menceritakan legenda masyarakat Thailand Tao Xuong dan Tao Ngan, tentang masa-masa paceklik... Beliau menceritakannya dengan suara asli, merinci setiap detail, setiap nama, setiap aliran sungai. Saya mendengarkan, mencatat, dan merasakan bahwa kenangan para lansia adalah aset berharga bagi komunitas ini.
Ia berkata: "Saat ini, anak cucu pergi jauh dan seringkali melupakan desa mereka. Namun desa itu tetap ada, bagaikan batu di sungai, terkikis air tetapi tidak hilang." Kata-katanya membuat saya sedih. Hidup perlahan bagi masyarakat Thailand bukan hanya tentang menikmati, tetapi juga tentang melestarikan dan menjaga.
Tidak semuanya damai di sini. Saya mendengar kecemasan dalam suara anak muda, tentang pendidikan, pekerjaan, dan migrasi. Banyak gadis muda meninggalkan desa mereka setelah lulus, pergi ke kota untuk mencari pekerjaan, berharap mengubah hidup mereka, beberapa kembali dan beberapa menetap. Perkembangan pariwisata memiliki dua sisi, ekonomi meningkat, tetapi nilai-nilai budaya mudah dikomersialkan. Orang Thailand di sini ingin mempertahankan identitas mereka, tetapi juga perlu berubah untuk hidup lebih baik.
Suatu sore yang hujan, saya duduk di rumah panggung, mendengarkan rintik hujan yang jatuh di atap, mengamati tetesan air yang mengalir melalui celah-celah kayu. Saya merenungkan bagaimana masyarakat Thailand di sini mengelola pariwisata. Mereka memanfaatkan dan mengeksploitasi budaya dan alam secara maksimal untuk menciptakan produk wisata yang unik seperti bercocok tanam, membuat brokat, mandi di dedaunan hutan... semuanya menciptakan hubungan antara manusia dan alam, antara modernitas dan budaya tradisional.
Saya juga menyadari bahwa saya belajar kesabaran, kerja keras, menunggu pohon tumbuh, menunggu musim berikutnya. Kesuksesan tidak datang dalam semalam, tetapi merupakan hadiah dari waktu. Hidup perlahan bukan berarti kembali ke masa lalu, melainkan memilih untuk hidup dengan kecepatan yang berbeda, tahu bagaimana menunggu dan mensyukuri. Di sini, konsep kesuksesan bukan hanya tentang uang, tetapi juga tentang keberlanjutan, rumah yang hangat, dan seorang anak yang tumbuh sehat di desa.
Hal yang istimewa dari hari-hari di Ban Thai adalah, baik saat makan untuk ibadah maupun makan biasa, orang-orang tetap mengenang leluhur mereka sebagai ucapan terima kasih atas makanan yang mereka terima hari ini. Saya merasa dapat menyentuh iman mereka melalui ajakan untuk makan, melalui tindakan mengangkat anggur...

Hari ketika saya meninggalkan desa, langit cerah, matahari pagi menyinari setiap sawah terasering, berkilau keemasan. Saya memeluk induk semang, orang-orang Thailand tetap hangat seperti saat mereka menyambut saya, menciptakan kenangan indah bagi setiap tamu. Mereka memberi saya beberapa kentang, sekantong beras gogo, dan sebuah tas brokat kecil yang cantik. Saya menghargai setiap hadiah sebagai janji untuk kembali, untuk memberi tahu mereka, untuk menyimpan kenangan ini di hati saya.
Dalam perjalanan turun, saya berhenti di tikungan, memandang lembah, memandangi atap-atap kecil yang berselimut kabut. Saya berkata pada diri sendiri, hidup perlahan di Ban Thai adalah pelajaran yang mengajarkan kita untuk melihat kembali diri kita sendiri, belajar mendengarkan, menghargai hal-hal kecil. Saya membawa kembali kisah-kisah, wajah-wajah, butiran beras, dan kesadaran yang berbeda ke kota ini—mengingatkan diri sendiri "di tengah kehidupan yang terburu-buru, belajarlah untuk hidup perlahan, mencintai, memahami, dan melestarikan".
Sumber: https://baolaocai.vn/song-cham-de-yeu-de-giu-gin-post884226.html





![[Foto] Kota Ho Chi Minh dipenuhi bendera dan bunga pada malam Kongres Partai ke-1, periode 2025-2030](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/1200x675/vietnam/resource/IMAGE/2025/10/10/1760102923219_ndo_br_thiet-ke-chua-co-ten-43-png.webp)
![[Foto] Pembukaan Festival Budaya Dunia di Hanoi](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/1200x675/vietnam/resource/IMAGE/2025/10/10/1760113426728_ndo_br_lehoi-khaimac-jpg.webp)
![[Foto] Sekretaris Jenderal menghadiri parade untuk merayakan ulang tahun ke-80 berdirinya Partai Buruh Korea](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/1200x675/vietnam/resource/IMAGE/2025/10/11/1760150039564_vna-potal-tong-bi-thu-du-le-duyet-binh-ky-niem-80-nam-thanh-lap-dang-lao-dong-trieu-tien-8331994-jpg.webp)


























































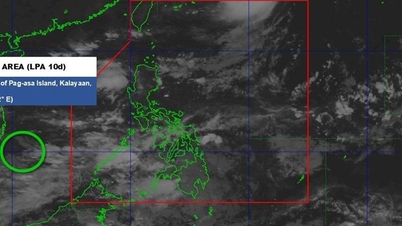































Komentar (0)