Waktu berlalu begitu cepat! Sudah bulan April.
Dari April 1975 hingga hari ini—cukup waktu bagi saya untuk menyebutnya suatu masa—hari itu, gadis kecil di sebelah rumah hanyalah seorang anak kecil yang meringkuk di samping ibunya, menatap kosong ke arah perang, dan saya, sejak hari itu, terseret dari satu wilayah ke wilayah lain oleh perang. Dan April ini, gadis kecil yang "menatap kosong ke arah perang" sejak saat itu telah menjadi seorang ibu muda yang sukses dalam hidup, sementara saya, sang wanita tua, menatap kosong ke arah kehidupan!

April itu, aku mengucapkan selamat tinggal padanya tanpa tanggal untuk bertemu dengannya lagi. Tahun-tahun berikutnya, karena aku merindukan tanah airku, aku kembali dan bertemu dengannya. Rasanya baru kemarin, kini ia telah dewasa dan beruntung hidup tanpa dosa dalam damai . Ia berkata padaku, sayang sekali ia hanya mengenal perang melalui buku dan film... Aku berharap bisa menghadapinya secara langsung untuk merasakan kepedihan bersama mereka yang telah kehilangan dan menderita akibat perang. Apakah ucapannya terlalu idealis dan romantis?
April lainnya telah tiba!
Sore ini, di suatu sore di bulan April, aku kembali ke kampung halamanku. Aku dan adikku, yang satu tua dan yang satu muda, berjalan berdampingan di jalan desa. Desa ini telah banyak berubah. Berbeda dengan dulu, rumah adikku dan rumahku dipisahkan oleh deretan kembang sepatu. Deretan kembang sepatu itu hanya melambangkan batas tanah, bukan pemisah hati. Rumah-rumah kini berdinding tinggi, seolah ada tali tak kasat mata yang memisahkan desa dan kasih sayang antartetangga? Banyak orang kini tertutup dalam hal makan, kekayaan mereka tertutup dalam hati, hanya tanah yang terbuka karena tak dapat disembunyikan, meskipun ada... emas di tanah itu.
Sudah lama kita tak mendengar deru pesawat yang membelah langit, deru meriam di sepanjang malam, dan tak lagi melihat ibu muda itu pingsan mendengar kabar gugurnya suaminya di medan perang... bayangan itu tak lagi ada. Itulah sukacita kedamaian.
April ini, saya dan adik perempuan saya berkesempatan berjalan-jalan bersama di suatu sore yang cerah di kampung halaman saya. Matahari bagai api, memutihkan rerumputan dan pepohonan, menguningkan dedaunan, terik matahari bagai tungku, menyinari kota kecil itu bagai telapak tangan, dengan nama yang sangat kebarat-baratan: La Gi. Meskipun berada tepat di kampung halaman saya, ke mana pun saya memandang, saya merasa asing, jalan-jalan asing, tanah asing, rumah-rumah asing, orang-orang asing. Saya bertanya kepadanya, di kampung halaman saya, siapa yang masih ada dan siapa yang telah tiada? Hanya sedikit yang tersisa, banyak yang hilang. Sore di bulan April perlahan datang, matahari tak lagi menyengat, saya berhenti di sebuah kafe pinggir jalan untuk minum kopi dan mendengarkan "Proud Melody": "... Membebaskan Selatan, kita bersumpah untuk maju...". Ia mendengarkan dan berkata bahwa sudah lama sekali ia tak mendengar lagu ini – sebuah lagu yang tak terlupakan dari kedua belah pihak – sisi ini dan sisi yang lain. Dan ia terus bertanya, saudaraku, ketika orang mati dalam perang, mati karena usia tua, mati karena kecelakaan, mati karena penyakit... apakah mereka tahu hal lain ketika mereka mati? Murid Konfusius yang terkasih, pernah bertanya kepadanya pertanyaan ini, dan dia menjawab, "Jika kau ingin tahu apakah kau tahu sesuatu setelah kematian, tunggu saja sampai kau mati, dan kau akan tahu!" Lihatlah aku, jawaban Konfusius sangat bijaksana, bukan?
Masa lalu ada dalam diri setiap orang, setiap bangsa, setiap negara. Masa lalu telah bercampur aduk antara suka dan duka, kejayaan dan kehinaan, darah dan air mata, perpisahan dan penderitaan, kematian dan dendam. Sore ini, bulan April, aku kembali mengunjungi tempat kelahiranku setelah bertahun-tahun mengembara ke kota itu sejak perang berakhir. Dalam senja yang sunyi, kau dan aku pun terdiam mendengarkan gema masa lalu...
“… Setelah tiga puluh tahun berpisah, kita bertemu lagi, mengapa air mata mengalir lagi…” (Xuan Hong).
Sumber



![[Foto] Surat Kabar Nhan Dan meluncurkan “Tanah Air di Hati: Film Konser”](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/1200x675/vietnam/resource/IMAGE/2025/10/16/1760622132545_thiet-ke-chua-co-ten-36-png.webp)

![[Foto] Sekretaris Jenderal To Lam menghadiri Kongres Partai Hanoi ke-18, periode 2025-2030](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/1200x675/vietnam/resource/IMAGE/2025/10/16/1760581023342_cover-0367-jpg.webp)


































![[Video] TripAdvisor menghormati banyak objek wisata terkenal di Ninh Binh](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/402x226/vietnam/resource/IMAGE/2025/10/16/1760574721908_vinh-danh-ninh-binh-7368-jpg.webp)

















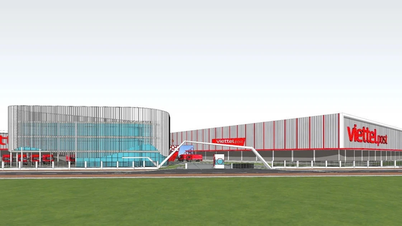

















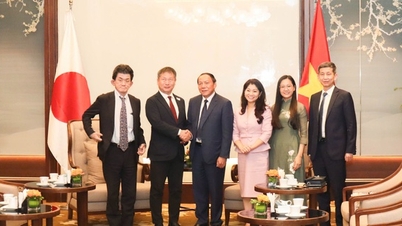

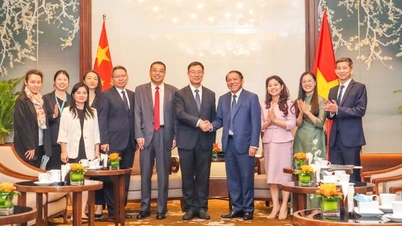




























Komentar (0)