(QBĐT) - Sore di pedesaan selalu diwarnai lembut, seolah langit dan bumi pun ingin sedikit tenang untuk memberi ruang bagi kedamaian. Di halaman kecil, teralis sirih nenek saya terbentang menyambut sinar matahari yang pucat, dedaunan hijaunya yang sejuk bergoyang tertiup angin sepoi-sepoi.
Aroma daun sirih yang manis dan pedas menguar di udara, merangkai gambar di mana setiap helai daun dan ranting membawa sepenggal kenangan. Aku masih ingat pagi-pagi sekali ketika Nenek berdiri di dekat teralis sirih, tangannya yang kapalan membelai lembut setiap helai daun, tatapan matanya yang penuh kasih sayang seakan mencurahkan seluruh isi hatinya ke dalam warna hijau itu. Teralis sirih adalah tempat ia melekat sepanjang hidupnya, sejak rambutnya masih hijau hingga punggungnya bungkuk dan rambutnya berbintik-bintik perak. Daun sirih itu masih penuh kehidupan, seperti cinta yang ia miliki untuk keluarganya, untuk anak-cucunya, dan untuk taman yang penuh kenangan.
Setiap pulang sekolah, aku selalu berlari menghampirinya, terpesona oleh kelincahan tangannya memetik daun sirih segar. Ia dengan lembut meletakkan beberapa helai daun di tanganku, lalu tertawa ketika aku dengan penasaran mengambil sebatang kecil daun sirih dan mendekatkannya ke hidungku untuk diendus. Aroma sirih itu sedikit pedas, tetapi anehnya, aroma itu seolah mengandung kehangatan yang familiar. Ia pernah berkata bahwa sirih tidak hanya untuk dikunyah, tetapi juga obat mujarab yang membantu menyembuhkan penyakit, menyejukkan badan, dan mengusir roh jahat. Suaranya saat itu, pelan dan hangat, bagaikan lagu pengantar tidur yang lembut, perlahan merasuk ke dalam pikiranku. Setiap katanya, bagaikan benih yang diam-diam tertanam dalam ingatanku, menjadi kenangan indah yang masih kusimpan selama bertahun-tahun.
 |
Setiap musim sirih, ia dengan hati-hati memetik daun-daunnya yang hijau subur, mengeringkannya dengan sabar, lalu menyimpannya dalam toples keramik untuk digunakan nanti. Sambil mengunyah sirih, ia kerap bercerita tentang masa lalu: tentang masa mudanya, tentang pasar-pasar di pedesaan yang ramai, tentang cinta pertama suaminya yang terjalin dengan sirih dan pinang sederhana, dan tentang kenangan yang telah memudar selama bertahun-tahun. Ia berkata bahwa sirih bukan sekadar daun, melainkan perasaan, budaya, dan jiwa masyarakat Vietnam. Dalam setiap helai sirih, terbungkus dan diwariskan berbagai ritual dan adat istiadat leluhur. Oleh karena itu, teralis sirihnya bukan sekadar deretan pohon di sudut taman, melainkan juga tempat menyimpan kenangan sakral—bagian tak terlupakan dari jiwa pedesaan.
Suatu kali, saya bertanya kepadanya: "Nenek, kenapa menanam begitu banyak daun sirih?" Ia tersenyum dan berkata, daun sirih itu untuk dikunyah kakek-nenek, untuk menjamu tamu, dan untuk dipajang di altar saat peringatan kematian dan hari raya. Terkadang ia bahkan menggunakan daun sirih untuk menyembuhkan penyakit. Saya telah mendengar banyak cerita tentang pengobatan Timur ketika ia masih muda. Saat itu, ia adalah seorang tabib yang membantu tetangganya dengan penuh sukacita dan antusiasme. Ia tidak pernah menolak siapa pun, dan kapan pun seseorang membutuhkannya, ia selalu siap sedia.
Setiap sore menjelang senja, para nenek-nenek di lingkungan itu berkumpul di sekitar teralis sirih mereka. Saya masih ingat betul masing-masing: Bu Tu dengan langkahnya yang agak goyah karena kakinya yang sakit, Bu Sau dengan rambut yang sudah memutih namun matanya masih berbinar, dan Bu Nam dengan senyum ramahnya, meskipun beberapa giginya sudah tanggal, ia tetap tak bisa melepaskan kebiasaan mengunyah sirih. Mereka sahabat karib, saling menemani melewati musim sirih, pasar-pasar desa, dekat sejak rambut mereka masih hijau hingga memutih. Setiap orang memegang segenggam sirih, mengunyah tanpa gigi, menghirup rasa pedas yang menjalar di ujung lidah. Usai mengunyah sirih, para nenek tertawa terbahak-bahak, berceloteh tentang kisah-kisah lama dari masa-masa menanam padi di tengah hujan, hari-hari mereka terpapar terik matahari di sawah, hingga hari-hari pertama menjadi menantu, masih bingung dan canggung. Tiap cerita seakan telah diceritakan ratusan kali, tetapi setiap kali saya mendengarkannya, saya merasa hangat di dalam, seakan-akan kenangan itu disuling dari kasih sayang.
Setiap kali mereka menyebut orang-orang terkasih, mata mereka berbinar-binar, seolah kenangan lama kembali membanjiri. Beberapa perempuan menitikkan air mata ketika bercerita tentang anak-anak mereka yang jauh dari rumah, atau cucu-cucu mereka yang terakhir kali mereka temui saat masih sangat kecil. Kemudian, kisah-kisah bahagia berlanjut, dan tawa renyah menggema, membuat seisi taman semarak. Kami, anak-anak, duduk diam mendengarkan dari kejauhan, tak mengerti semua ini, hanya melihat para perempuan mengunyah sirih dan tersenyum, pipi mereka merona seolah-olah masa muda telah kembali.
Kini, setelah aku dewasa dan pergi jauh dari desa, sulur sirih nenekku masih hijau, berdiri tegak di sudut kebun, dengan tenang menemani setiap musim hujan dan cerah. Setiap kali aku kembali ke kampung halaman, memandangi sulur sirih yang hijau nan rimbun, hatiku teringat tangan-tangan tua nenekku, saat-saat ia duduk bercerita, sirih-sirih pahit yang penuh cinta untuk keluarganya. Sulur sirih itu bagaikan bagian dari jiwa kampung halamanku, mengingatkanku pada tahun-tahun damai dan sederhana bersama nenekku, dan pada cintanya yang begitu besar untuk kami, bagaikan sulur sirih itu, yang selalu hijau dalam ingatanku.
Linh Chau
[iklan_2]
Sumber: https://www.baoquangbinh.vn/van-hoa/202504/gian-trau-cua-ba-2225623/





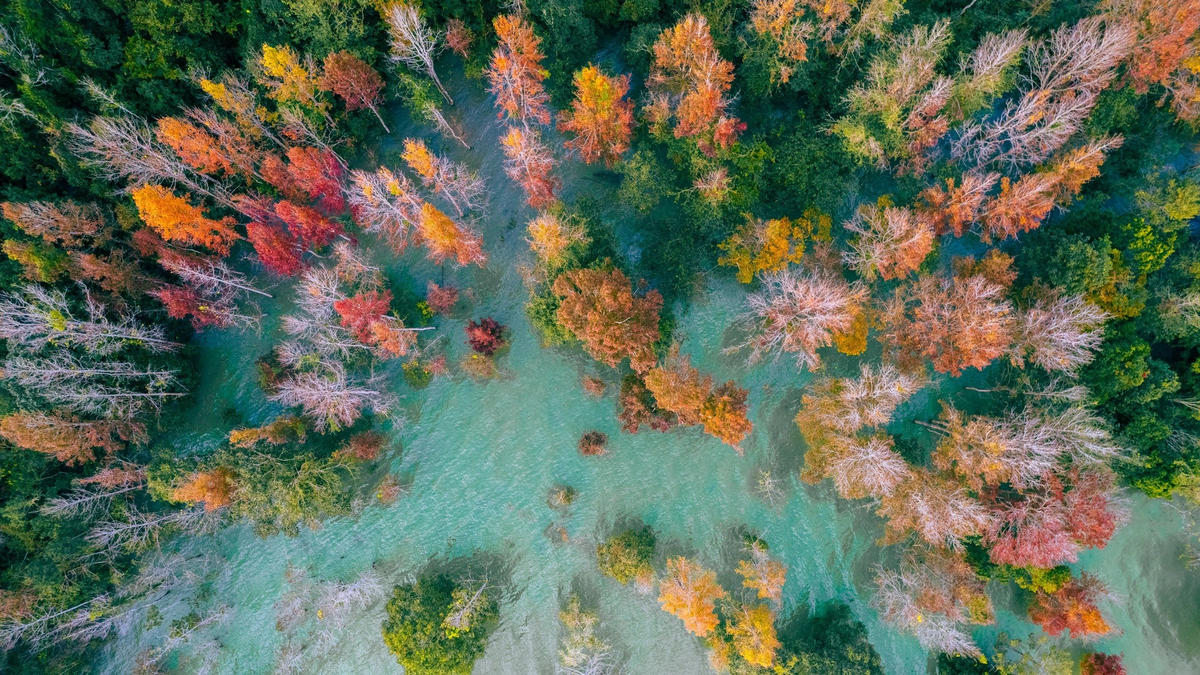






















































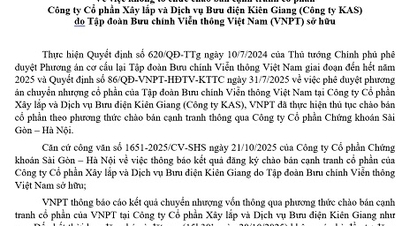

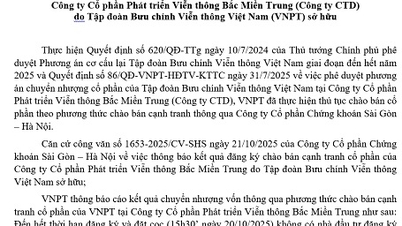

















































Komentar (0)