 |
| Ilustrasi: PV |
Ibu saya pergi ke halaman untuk memeriksa tambang batu bara, yang mengepulkan asap putih.
"Anginnya kencang sekali; kalau kita tidak hati-hati, lubang di tambang batu bara ini akan terbakar habis," kata ibuku sambil berteriak saat berjalan, membuatku terkejut dengan saran yang telah kuucapkan berkali-kali: "Ayo kita tinggal di kota, Bu!"
Aku tidak menjawab, hanya berdeham, cukup bagi Ibu untuk tahu bahwa aku sedang merespons.
Tungku pembakaran arang masih mengeluarkan asap dengan tenang. Penduduk desa di tepi hutan hidup terutama dengan membakar arang, atau memanen madu, atau memasang perangkap di sungai untuk menangkap udang dan ikan. Kehidupan sederhana namun penuh sukacita, terutama karena orang-orang tinggal di tempat kelahiran mereka, jiwa mereka terhubung dengan tanah dan sungai yang sangat mereka cintai. Di malam yang sunyi, desa saya hanya bisa mendengar gemerisik hutan melaleuca, derak tungku pembakaran arang, dan gumaman suara anak-anak dari desa hutan yang baru saja memulai kelas satu.
Aku mengikuti ibuku menuju gudang batubara. Pohon-pohon pisang di samping gudang masih hijau dan sehat, berbuah lebat, hampir matang. Ibuku membungkuk untuk menambal lubang-lubang yang hampir jebol. Jika gudang tidak tertutup rapat, angin akan masuk dan membakar semua kayu bakar. Asap membuat ibuku batuk hebat, dan air mata mengalir di wajahnya. Aku menatapnya, hatiku terasa sakit. Di masa-masa ketika aku tidak ada di sini, ibuku pasti akan kesepian di rumah ini, yang sudah lama tanpa ayahku. Dia akan sendirian dari pagi hingga larut malam. Kehidupan ibuku penuh dengan kesulitan dan perjuangan. Suatu kali, aku tidak tahan lagi dan berkata kepadanya:
- Bu! Aku tidak bisa berhenti kerja dan tinggal di sini bersamamu, dan Ibu juga tidak bisa tinggal sendirian di sini selamanya. Aku khawatir! Bu, datanglah dan tinggallah bersamaku di kota. Di sana ada rumah besar, dan kita akan bersama...
Ibu saya berpikir lama sekali. Saya melihatnya menatap altar ayah saya, lalu ke kanal kecil di depan rumah. Matanya berwarna putih keabu-abuan. Tiba-tiba, saya melihatnya dengan lembut menyeka sudut matanya dengan sapu tangan. Saya memegang tangannya, mata saya berlinang air mata.
Ibu! Jika aku mengatakan sesuatu yang salah, tolong jangan marah. Aku hanya ingin hidup di sisimu, agar kau bisa menikmati kedamaian dan ketenangan seumur hidupmu.
Ibu saya menyela saya:
- Tidak, Ibu sama sekali tidak marah padamu. Kamu benar, hanya saja Ibu masih terikat dengan tempat ini, beliau belum bisa meninggalkan kampung halamannya.
Kata-kata ibuku, "meninggalkan rumah," membuat hatiku sakit. Aku telah "meninggalkan rumah" pada hari pertama aku tiba di kota untuk belajar, dan sejak itu, hari-hari aku pulang ke rumah dapat dihitung dengan jari satu tangan. Rumahku, kampung halamanku, tempat aku tinggal sepanjang masa kecilku, kini telah menjadi tempat tinggal sementara, tanah asing, meskipun aku masih merindukan tempat ini. Aku mengerti bahwa, untuk sesaat, ibuku tidak bisa memaksakan diri untuk pergi ke kota bersamaku. Kota itu familiar bagiku, tetapi asing bagi ibuku. Tidak ada lagi aroma samar asap arang dari tungku setiap pagi dan sore, tidak ada lagi gemerisik daun melaleuca tertiup angin, dan tidak ada lagi sepetak tanah yang ditumbuhi gulma yang menyimpan begitu banyak kenangan indah bagi kami.
Bagi ibuku, tanah kelahirannya adalah darah dagingnya, jiwanya, surga yang indah. Separuh hidupnya telah berlalu sejak pertama kali tiba di tanah ini. Separuh hidupnya telah ia jalani, terikat, mencintai, melahirkan aku, dan kemudian menempatkan hatinya di sini. Ibuku sangat mencintai sungai, mencintai hutan bakau tempat ayahku dulu mendayung perahu untuk memasang sarang lebah dan kembali dengan sarang lebah yang penuh madu, mencintai aroma asap yang mengepul dari tungku arang dan menyebar di sepanjang sungai, memberikan pedesaan ini karakter unik yang tak akan pernah dilupakan ibuku. Pada masa itu, ia banyak berjuang. Namun ia tetap puas dan tidak menginginkan sesuatu yang mewah atau ilusi. Ia tetap setia pada tanah, hutan, sungai, dan ayahku.
Melihat sekeliling dan menyadari bahwa gudang batubara sudah penuh, ibuku masuk ke dalam rumah. Aku mengikutinya. Lampu yang berkedip-kedip memancarkan lingkaran cahaya sempit di halaman. Aku merasakan kehangatan dan kelembutan yang aneh di tubuhku. Selalu seperti ini; setiap kali aku pulang, aku merasakan kedamaian yang mendalam. Beberapa kali aku mempertimbangkan untuk membangun rumah baru untuk ibuku, tetapi dia menghentikanku. "Rumah tua itu berharga karena menyimpan begitu banyak kenangan," katanya. Aku mendengarkannya, sebagian karena aku juga berencana membawanya tinggal di kota dalam waktu dekat, jadi aku meninggalkan ide untuk membangun kembali rumah di pedesaan. Rumah tua itu hangat dan nyaman; semuanya dipelihara dengan teliti oleh ibuku, tidak berubah selama beberapa dekade. Jarak dari kota ke pedesaan hampir dua ratus kilometer, namun setiap kali aku bisa, aku akan mengendarai mobil kembali, dan ketika aku lelah, aku akan naik bus. Meninggalkan ibuku sendirian di pedesaan membuatku merasa tidak nyaman.
Malam menyelimuti pedesaan, dan seiring malam semakin larut, angin bertiup semakin kencang. Aroma bunga melaleuca dari hutan terbawa angin, memenuhi udara dengan wangi yang harum. Aku duduk di samping ibuku, dan tiba-tiba, waktu seolah berputar kembali ke masa kecilku, ketika aku duduk di sampingnya seperti ini, di bawah lampu minyak, sementara dia memperbaiki pakaian ayahku dan mengajariku mengeja setiap huruf… Masa-masa itu begitu indah dan damai!
"Ibu tahu kau sudah dewasa sekarang, dan kau hidup nyaman, jadi kau ingin menebus semua kesulitan yang Ibu alami saat masih kecil. Tapi anakku, tempat ini sangat berarti bagi Ibu. Kau boleh punya rumah sendiri, keluarga sendiri, tapi yang Ibu miliki hanyalah kenangan indah yang terkait dengan pedesaan ini. Ibu tidak bisa meninggalkannya, anakku..."
Aku menatap ibuku dengan penuh pertimbangan, dan air mata menggenang di mataku tanpa kusadari. Orang tua sering kali menghargai kenangan masa lalu; mereka hidup untuk kenangan itu, berpegang teguh pada suatu tempat karena tempat itu menyimpan kenangan yang tak terlupakan. Ibuku hidup untuk itu, dan begitu pula aku.
- Bu! Maafkan aku...
Ibuku mengelus kepalaku, lalu menarikku lebih dekat padanya. Aroma asap arang menempel di pakaian dan rambutnya, wangi yang manis. Ibuku berkata dengan penuh kasih sayang:
- Ibu selalu menginginkan anak-anaknya memiliki tempat untuk kembali. Ia akan selalu berada di sini, menjaga kehangatan rumah, aroma dupa yang menenangkan di altar Ayah, dan melestarikan bagi anak-anaknya akar yang tidak boleh mereka lupakan.
Aku memahami hati ibuku. Hatinya pemaaf. Akar seseorang adalah sesuatu yang, ke mana pun ia pergi, tidak boleh dilupakan, tidak boleh dibiarkan tercabut dari akarnya.
Aku duduk di samping ibuku. Malam itu sunyi. Desa itu tenggelam dalam tidur yang hening, hanya dipecah oleh tangisan pilu burung-burung hutan nokturnal dan gemerisik bara api yang terbawa angin. Dalam momen sederhana namun hangat itu, aku merasakan gema tanah, sungai-sungai di kampung halamanku, hutan bakau yang luas, dan gema hati ibuku yang baik dan murah hati. Suatu hari nanti, dalam perjalanan hidup yang tampaknya panjang dan berat, aku akan seperti ibuku, menghargai setiap kenangan indah dan menyimpannya untuk diriku sendiri.
Aku bersandar di pipinya, seolah bersandar di sungai, di tanah air, di bawah naungan pohon bakau, di asal usulku yang suci dan berharga!
Sumber: https://baophuyen.vn/sang-tac/202505/ben-que-con-ma-1ce28e9/



![[Foto] Perdana Menteri Pham Minh Chinh menerima Gubernur Provinsi Tochigi (Jepang)](/_next/image?url=https%3A%2F%2Fvphoto.vietnam.vn%2Fthumb%2F1200x675%2Fvietnam%2Fresource%2FIMAGE%2F2025%2F12%2F16%2F1765892133176_dsc-8082-6425-jpg.webp&w=3840&q=75)
![[Siaran Langsung] Gala Penghargaan Aksi Komunitas 2025](/_next/image?url=https%3A%2F%2Fvphoto.vietnam.vn%2Fthumb%2F1200x675%2Fvietnam%2Fresource%2FIMAGE%2F2025%2F12%2F16%2F1765899631650_ndo_tr_z7334013144784-9f9fe10a6d63584c85aff40f2957c250-jpg.webp&w=3840&q=75)
![[Gambar] Bocoran gambar menjelang acara gala Community Action Awards 2025.](/_next/image?url=https%3A%2F%2Fvphoto.vietnam.vn%2Fthumb%2F1200x675%2Fvietnam%2Fresource%2FIMAGE%2F2025%2F12%2F16%2F1765882828720_ndo_br_thiet-ke-chua-co-ten-45-png.webp&w=3840&q=75)
![[Foto] Perdana Menteri Pham Minh Chinh menerima Menteri Pendidikan dan Olahraga Laos Thongsalith Mangnormek](/_next/image?url=https%3A%2F%2Fvphoto.vietnam.vn%2Fthumb%2F1200x675%2Fvietnam%2Fresource%2FIMAGE%2F2025%2F12%2F16%2F1765876834721_dsc-7519-jpg.webp&w=3840&q=75)

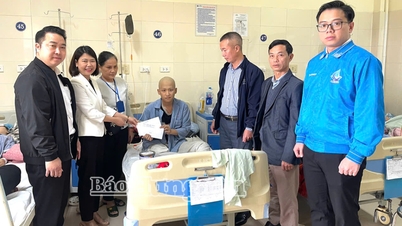

































































![[Siaran Langsung] Upacara Penutupan dan Penyerahan Penghargaan untuk Kontes Pembuatan Video/Klip "Pariwisata Vietnam yang Mengesankan" 2025](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/402x226/vietnam/resource/IMAGE/2025/12/17/1765974650260_z7273498850699-00d2fd6b0972cb39494cfa2559bf85ac-1765959338756946072104-627-0-1338-1138-crop-1765959347256801551121.jpeg)


























Komentar (0)