Di tengah Samudra Atlantik, terdapat sebuah kepulauan kecil yang harus diperbesar untuk dilihat di peta. Populasinya hanya lebih dari setengah juta jiwa, tanpa industri besar, dan tanpa kejuaraan yang gemilang. Namun ketika Tanjung Verde lolos ke Piala Dunia 2026, dunia tiba-tiba menoleh ke belakang – bukan hanya untuk keajaiban sepak bola, tetapi juga untuk bagaimana mereka mengubah kenangan, musik , dan nostalgia menjadi kekuatan.
Perjalanan ini adalah kisah tentang identitas: tentang pulau-pulau, tentang ekspatriat, tentang musik morna, dan kegembiraan jalanan. Sebuah negara kecil menceritakan kisahnya, dalam bahasa yang paling universal: sepak bola.
BAGIAN 1: TANJUNG VERDE, NEGARA KECIL DAN HARI PIALA DUNIA
Di tengah Samudra Atlantik, tempat angin Sahara yang asin bertiup di atas gunung berapi Fogo, sebuah negara berpenduduk lebih dari setengah juta jiwa baru saja melakukan hal yang tak terbayangkan: lolos ke Piala Dunia 2026. Sebuah pulau kecil telah menempatkan dirinya di peta sepak bola dunia.
Mulai sekarang, Tanjung Verde bukan hanya surga wisata atau olahraga bahari, tetapi juga negeri yang bermimpi dan berjuang mewujudkan cita-citanya.
Praia – ibu kota Pulau Santiago – menyala terang malam itu. Saat peluit akhir dibunyikan di Stadion Nasional Tanjung Verde, kota itu bergemuruh. Gendang Batuque bergema di lereng-lereng sempit, dan orang-orang berpelukan dan menari dalam cahaya redup.
Di bar pantai Quebra Canela, para nelayan menebar jala, turis berlama-lama. Di layar, para pemain berlari mengelilingi lapangan, menancapkan bendera nasional di rumput. Untuk pertama kalinya, bendera merah-biru-putih-kuning akan ditampilkan di festival sepak bola terbesar di dunia.

Keajaiban dari pulau berangin
Luas Tanjung Verde kurang dari 4.000 km², dengan populasi sekitar 540.000 jiwa – lebih sedikit daripada populasi sebuah distrik di Lisbon (Portugal), kota yang dulunya merupakan "tanah air". Generasi demi generasi penduduk Tanjung Verde terpaksa meninggalkan tanah air mereka karena tanah yang tandus demi impian belajar dan bekerja di Eropa.
Namun, migrasi inilah yang membawa semangat dan aspirasi baru ke tanah air. Sepak bola , seperti angin, tak berhenti di perbatasan.
Tim mereka – “Tubaroes Azuis” , Hiu Biru – memang tidak diperkuat bintang-bintang top Eropa. Namun, mereka memiliki sesuatu yang lebih berharga: keyakinan bahwa tim kecil pun mampu menulis kisah besar.
Perjalanan kualifikasi Tanjung Verde sangat sulit, dengan kemenangan 3-0 atas Eswatini di babak final yang mengamankan tiket mereka ke AS, Meksiko, dan Kanada pada tahun 2026.
Musim panas lalu, mereka dianggap sebagai "tim biru" bagi Malaysia untuk berlatih dengan sekelompok pemain naturalisasi untuk bermain melawan tim Vietnam.
"Ini hari bersejarah bagi seluruh negeri," ujar pelatih Pedro Leito Brito – yang dikenal dengan julukan Bubista (nama Portugis untuk tanah kelahirannya). "Mulai hari ini, dunia akan tahu bahwa Tanjung Verde bukan hanya tentang pantai-pantai indah."
Kepulauan Mendongeng
Setiap pulau di kepulauan ini memiliki jiwanya sendiri – dan bersama-sama, mereka menulis simfoni bangsa muda ini.
Sal, tempat para turis berselancar di atas bukit pasir putih. Boa Vista, dengan garis pantainya yang panjang dan berangin – surga bagi para peselancar. Fogo, dengan gunung berapi yang masih bernapas dan kebun anggur yang rimbun di atas bebatuan hitam. Santo Antao, pulau awan dan lembah.
Dan Santiago, jantung sejarah, tempat orang-orang menyanyikan morna setiap sore, musik yang sedih dan indah, membawakan “sodade” – nostalgia tak berujung untuk tanah air seseorang.
Sekarang, dengan morna (musik tradisional di sini) , sepak bola menjadi bahasa kedua. Ketika Tanjung Verde menang, orang-orang bernyanyi; ketika kalah, mereka tetap bernyanyi. Diiringi suara drum dan ombak, orang-orang berbicara tentang "impian samudra" mereka : sekecil apa pun mereka, mereka ingin dunia mendengar nama mereka.

Sepakbola – cerminan negara
Kisah sepak bola mencerminkan sejarah Tanjung Verde: pergi mencari jalan pulang. Banyak pemain lahir di Portugal, Belanda, Prancis, dan Amerika Serikat; mereka tumbuh besar di kota-kota terpencil, tetapi memilih untuk mengenakan seragam tanah air mereka.
Di sana, mereka tidak hanya bermain untuk tim mereka – mereka bermain untuk orang tua mereka, kakek-nenek mereka, untuk pulau yang dulunya hanya sebuah titik kecil di lautan biru.
"Kita tidak punya populasi besar, kita tidak punya stadion besar, tapi kita punya hati," ujar kapten Ryan Mendes saat perayaan. Kutipan itu viral di media sosial, dibagikan sebagai pengingat bahwa hal-hal terkecil pun dapat mengarah pada hal-hal besar.
Tanjung Verde telah lama dikenal sebagai destinasi matahari dan angin, dengan pariwisata menyumbang lebih dari 20% PDB, tetapi Piala Dunia membuka dimensi lain: kebanggaan nasional.
Mulai sekarang, nama-nama pulau tersebut tak hanya akan terngiang di buku panduan perjalanan, tetapi juga di daftar grup Piala Dunia. Di mata anak muda, ada satu alasan lagi untuk tetap tinggal, yaitu untuk percaya bahwa tanah air mereka cukup besar untuk menggapai mimpi.
Keesokan paginya di Pantai Praia, anak-anak bermain sepak bola tua sambil tertawa. Seorang anak laki-laki mengangkat tangan dan berteriak: "Aku Tanjung Verde di Piala Dunia!" Orang-orang dewasa saling memandang dan tertawa – tawa bahagia sekaligus terkejut. Di sana, di tengah pasir dan ombak, mereka menyadari: sejarah baru saja berubah.
Sebuah pulau yang menceritakan sebuah kisah. Kisah itu, pada musim panas 2026, akan didengar oleh seluruh dunia.
Sumber: https://vietnamnet.vn/cape-verde-gianh-ve-world-cup-2026-co-tich-giua-dai-duong-2453748.html


![[Foto] Perdana Menteri Pham Minh Chinh bertemu dengan Ketua Majelis Nasional Hongaria Kover Laszlo](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/1200x675/vietnam/resource/IMAGE/2025/10/20/1760970413415_dsc-8111-jpg.webp)


![[Foto] Pembukaan Sidang Pleno ke-10, Majelis Nasional ke-15](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/1200x675/vietnam/resource/IMAGE/2025/10/20/1760937111622_ndo_br_1-202-jpg.webp)
![[Foto] Ketua Parlemen Hongaria mengunjungi Mausoleum Presiden Ho Chi Minh](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/1200x675/vietnam/resource/IMAGE/2025/10/20/1760941009023_ndo_br_hungary-jpg.webp)
![[Foto] Ketua Majelis Nasional Tran Thanh Man mengadakan pembicaraan dengan Ketua Majelis Nasional Hongaria Kover Laszlo](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/1200x675/vietnam/resource/IMAGE/2025/10/20/1760952711347_ndo_br_bnd-1603-jpg.webp)



























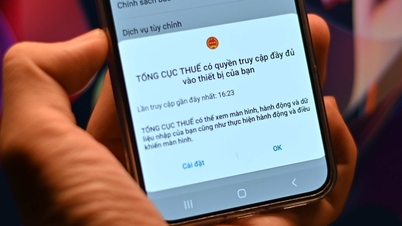
![[Foto] Panitia Pengarah Pameran Musim Gugur 2025 memeriksa kemajuan penyelenggaraan](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/1200x675/vietnam/resource/IMAGE/2025/10/20/1760918203241_nam-5371-jpg.webp)






















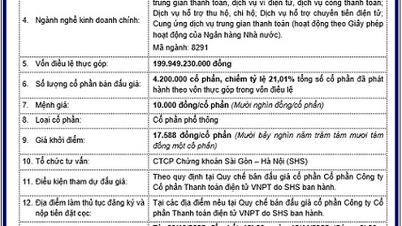






















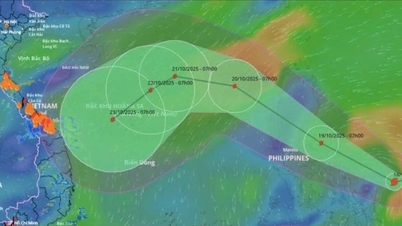















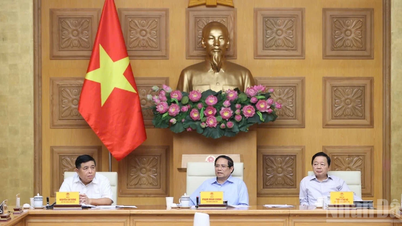










Komentar (0)