
Pagi ini, aku berjalan-jalan di pasar sekitar satu kilometer dari sekolahku. Belum sampai setengah kilometer, bajuku sudah basah kuyup keringat akibat udara panas dan lembap kota besar sejak pagi. Tiba-tiba aku merindukan angin sejuk dari ladang tebu di kota asalku.
Sejak saya pergi ke kota untuk kuliah, sudah hampir dua bulan saya tidak keluar dari area sekolah dan asrama. Biasanya, saya hanya keluar gerbang, berjalan beberapa meter, dan di sana ada restoran mahasiswa, banyak pedagang kaki lima, dan juga beberapa restoran vegetarian. Harganya murah dan mengenyangkan. Namun pagi ini, tiba-tiba saya ingin pergi ke pasar untuk mencari cara makan yang lebih hemat. Saya bangun pukul 5 pagi, menunggu gerbang asrama dibuka pukul 5.30 pagi. Saya berjalan di halaman asrama yang tenang, merasa lega seolah-olah saya tidak lagi terkurung di tempat asing.
Tak lama kemudian, jalanan semakin ramai, dan langkahku semakin cepat. Saat aku melangkah cepat, aku tiba-tiba teringat masa lalu, ketika setiap beberapa hari sekali ibuku mengajakku ke pasar. Aku juga menghitung berapa hari lagi sampai ujian, agar setelah ujian aku bisa pulang ke rumah orang tuaku.
Sesampainya di sana, suasana pasar di sini sangat berbeda dengan pasar yang dulu sering dikunjungi Ibu. Para penjual dan pembeli datang dari berbagai daerah, dan saya melihat banyak produk untuk pertama kalinya. Sebagai mahasiswa baru, saya memutuskan untuk sekadar merasakan suasana pasar kota dan mencari makanan murah. Saya berjalan-jalan di pasar, dan tiba-tiba aroma sup bihun langsung tercium di benak saya.
Aku ragu-ragu di depan kios soto bihun di pojok pasar. Aku teringat hari ibuku mengirimku ke kota, beliau memasak sepanci penuh soto bihun dengan kepiting. Aku ingat ayahku menghabiskan sepanjang sore yang hujan di ladang menangkap setiap kepiting yang masih keras. Aroma soto bihun tiba-tiba membuatku ingin membuang-buang uang. Melihat harga kios yang dua puluh hingga tiga puluh ribu dong per mangkuk, aku merasa kasihan dan berbalik.
Baru beberapa langkah, mataku tertuju pada sosok di balik kedai mi. Seorang pria kecil kurus berambut abu-abu, mengenakan kemeja kotak-kotak dengan benang-benang pudar dan berjumbai.
Kemeja itu persis seperti kemeja yang dipakai ayahku saat pergi ke ladang. Warnanya sama, kancingnya sama, bahkan bahunya memiliki garis panjang yang berumbai. Dia sangat mirip ayahku. Bahu ayahku bengkok ke satu sisi karena membawa tebu, bahu pamanku juga bengkok, mungkin karena menjual mi di jalan. Satu-satunya perbedaan adalah tangan ayahku lebih kasar karena mencangkul tanah selama lebih dari separuh hidupnya. Kakinya juga tidak dalam kondisi yang baik karena dia lebih sering bertelanjang kaki daripada memakai sandal, telapak kakinya kapalan, hitam dan keras, setiap jari kaki pecah-pecah dan kasar. Ada beberapa bekas darah di tumitnya. Saya ingat bulan-bulan hujan, setiap kali dia pulang dari ladang tebu, dia bersikeras tidur di rumah belakang, meskipun ibu dan saya memintanya untuk pergi ke rumah depan. Dia takut kakinya, yang basah kuyup dalam air sepanjang hari, akan berbau dan memengaruhi tidur istri dan anak-anaknya.
Di tengah kota, di tengah terik matahari, bau mobil dan asap yang menyengat mata orang-orang yang lewat, aku berdiri terpaku, memandangi penjual mi. Tanganku tanpa sadar merogoh saku mencari uang lima puluh ribu dong yang kusimpan dan tak berani kubelanjakan. Aku menatapnya, begitu merindukan ayahku hingga hatiku sakit, lalu berjalan menuju kedai mi itu.
Dia membungkuk untuk mengambil beberapa mi dan merebusnya dalam panci berisi air mendidih. Postur tubuhnya membungkuk, tangannya yang berurat-urat tampak gelisah. Aku tak kuasa menahan diri lagi dan berkata:
- Paman! Beri aku semangkuk mi seharga 20 ribu.
Dia meraih beberapa sayuran, lalu menatapku. Dia tersenyum, senyum lembut, dan berkata dengan lantang:
Oke, tarik kursi dan cari tempat yang sejuk untuk duduk. Tunggu sebentar, aku akan segera melakukannya.
Saya duduk memperhatikannya berjualan mi dan mengobrol dengan orang-orang. Ia dekat dengan para siswa yang tinggal di dekatnya dan datang ke rumahnya untuk makan mi. Setiap kali melihat seseorang yang masih kecil, ia akan menambahkan sepotong sup kepiting atau beberapa potong tahu dan bercanda: "Beri aku sepotong lagi, makanlah agar aku cepat besar." Ia membawakan semangkuk sup mi kepiting untuk saya, uapnya mengepul, aromanya begitu harum. Saya berterima kasih, lalu menundukkan kepala, mengambil sumpit, dan makan perlahan. Setiap mi yang hangat, setiap sendok sup kepiting membuat mata saya perih. Setiap kali saya mendongak, saya melihatnya dengan hati-hati membagikan semangkuk mi kepada pelanggan, dan ketika ia punya waktu luang, ia membersihkan mangkuk dan piring. Ia tampak sangat mirip ayah saya, tenang dan hangat. Saya menatapnya, mata saya merah. Itu pertama kalinya saya jauh dari rumah, sudah beberapa bulan saya tidak pulang, tiba-tiba melihat punggung yang sangat mirip ayah saya, sungguh rasa rindu yang tak terlukiskan.
Saya selesai makan dan berjalan untuk membayar. Dia memulai percakapan:
- Apakah itu bagus?
- Ya, lezat sekali! - kataku sambil tersenyum, air mata mengalir di mataku.
- Kalau enak, balik lagi dan makan lagi, Nak! Kamu murid baru, ya?
Ya, saya baru datang ke sini beberapa bulan lalu.
Dia tersenyum dan berkata lembut:
- Aku kasih kamu lima ribu untuk mengenalku. Ssst, jangan bilang siapa-siapa. - Dia kasih aku kembalian dan berusaha membuatku bahagia.
- Tidak, Paman, Anda bekerja sangat keras. Mengurangi seperti itu tidak menguntungkan...
- Siswa baru yang pandai akan diberi lebih sedikit!
Setelah itu, dia berpesan agar saya berusaha belajar dengan giat, lalu dia pun bergegas membuat semangkuk mie baru untuk para pelanggan.
Jantungku berdebar kencang di tengah kota. Aku menundukkan kepala dan berpamitan kepada pamanku sebelum pergi. Dalam perjalanan, aku menelepon ayahku dua kali, tetapi tidak ada yang menjawab. Aku kembali ke asrama, menatap ponselku. Aku jarang menelepon ayahku, biasanya aku menelepon ibuku di Zalo, lalu aku akan berbicara dengan ayahku...
Hari sudah siang ketika ayahku meneleponku kembali.
"Kau meneleponku? Ada apa?" Suara Ayah terdengar agak mendesak.
- Enggak, nggak apa-apa, aku cuma telepon karena mau dengar suaramu. Kamu baru pulang dari lapangan, kan?
- Ya, saya baru saja selesai memotong setengah daun tebu.
Saya mengobrol dengan ayah saya selama hampir setengah jam. Itu adalah panggilan telepon terlama yang pernah saya lakukan berdua dengannya. Setelah menutup telepon, saya masih sangat merindukan orang tua dan kampung halaman saya. Saya berkata pada diri sendiri untuk terus berusaha, karena sejauh apa pun jaraknya, orang tua saya akan selalu ada di sana menunggu panggilan telepon saya dan menunggu saya kembali...
Sumber: https://baocantho.com.vn/giua-pho-chot-co-nguoi-giong-cha-a193331.html






![[Foto] Presiden Luong Cuong menerima Menteri Perang AS Pete Hegseth](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/1200x675/vietnam/resource/IMAGE/2025/11/02/1762089839868_ndo_br_1-jpg.webp)































































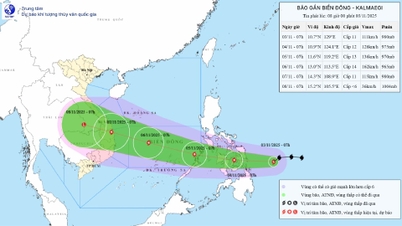




































Komentar (0)