Jepang hanya menginginkan tenaga kerja, bukan imigrasi
Ngu Thazin ingin meninggalkan negaranya yang dilanda perang demi masa depan yang lebih baik. Ia pun pergi ke Jepang.
Di Myanmar, ia belajar bahasa Jepang dan lulus dengan gelar sarjana kimia dari salah satu universitas paling bergengsi di negara itu. Namun, ia dengan senang hati menerima pekerjaan mengganti popok dan memandikan lansia di sebuah panti jompo di sebuah kota berukuran sedang di Jepang.
"Sejujurnya, saya ingin tinggal di Jepang karena aman," kata Thazin, yang berharap bisa lulus ujian untuk bekerja sebagai asisten rumah tangga berlisensi. "Dan saya ingin mengirimkan uang untuk keluarga saya."

Ngu Thazin di rumah bersama tempat ia tinggal bersama pekerja asing lainnya di Maebashi. Foto: New York Times
Jepang sangat membutuhkan orang-orang seperti Thazin untuk mengisi lowongan pekerjaan yang ditinggalkan oleh populasinya yang menua dan menyusut. Jumlah pekerja asing telah meningkat empat kali lipat sejak 2007, menjadi lebih dari dua juta di negara berpenduduk 125 juta jiwa.
Namun, meskipun pekerja asing semakin terlihat di Jepang, bekerja sebagai kasir minimarket, staf hotel, dan pelayan restoran, mereka masih diperlakukan secara ambigu. Para politisi masih enggan membuka jalan bagi pekerja asing, terutama mereka yang bekerja di pekerjaan berketerampilan rendah, untuk menetap tanpa batas waktu.
Hal itu pada akhirnya dapat merugikan Jepang dalam bersaing dengan negara tetangga seperti Korea Selatan, atau bahkan lebih jauh seperti Australia dan Eropa, yang juga tengah berjuang untuk mencari pekerja.
Perlawanan politik terhadap imigrasi di Jepang, serta masyarakat yang terkadang waspada dalam mengintegrasikan pendatang baru, telah menyebabkan sistem hukum dan dukungan yang ambigu sehingga menyulitkan orang asing untuk menetap.
Pekerja kelahiran luar negeri rata-rata dibayar sekitar 30% lebih rendah daripada warga negara Jepang, menurut data pemerintah Jepang. Karena takut kehilangan hak tinggal di Jepang, para pekerja seringkali memiliki hubungan yang tidak aman dengan perusahaan tempat mereka bekerja, dan kemajuan karier pun sulit diraih.
Kebijakan Jepang dirancang untuk "membuat orang bekerja di Jepang dalam jangka waktu pendek," kata Yang Liu, seorang peneliti di Institut Penelitian Ekonomi , Perdagangan, dan Industri (RIETI) di Tokyo. "Jika sistem ini terus berlanjut, kemungkinan pekerja asing akan berhenti datang ke Jepang akan menjadi sangat tinggi."
Ada perubahan, tapi belum cukup
Pada tahun 2018, pemerintah Jepang mengesahkan undang-undang yang secara drastis meningkatkan jumlah pekerja asing berketerampilan rendah yang diizinkan masuk ke negara tersebut. Awal tahun ini, Tokyo berjanji untuk menggandakan jumlah tersebut dalam lima tahun ke depan menjadi 820.000. Pemerintah juga merevisi program magang teknis yang selama ini digunakan oleh para pengusaha sebagai sumber tenaga kerja murah.

Winda Zahra, asal Indonesia, bekerja di panti jompo di Maebashi, ibu kota Prefektur Gunma di Jepang bagian tengah. Foto: New York Times
Namun, para politisi masih jauh dari membuka perbatasan negara. Jepang belum mengalami migrasi signifikan seperti yang mengguncang Eropa atau AS. Jumlah total penduduk kelahiran luar negeri di Jepang – termasuk pasangan dan anak-anak yang tidak bekerja – adalah 3,4 juta, kurang dari 3% populasi. Angka di Jerman dan AS, misalnya, hampir lima kali lipatnya.
Jauh sebelum orang asing dapat memperoleh status penduduk tetap, mereka harus lulus persyaratan visa yang ketat, termasuk tes bahasa dan keterampilan. Berbeda dengan Jerman, di mana pemerintah menawarkan hingga 400 jam pelajaran bahasa kepada penduduk asing baru dengan subsidi lebih dari 2 euro per pelajaran, Jepang tidak memiliki program pelatihan bahasa yang terorganisir untuk pekerja asing.

Ngun Nei Par (kanan), warga negara Myanmar dan manajer wisma Ginshotei Awashima, berbincang dengan staf dari Myanmar dan Nepal. Foto: New York Times
Sementara para politisi mengatakan negara harus berbuat lebih baik dalam pengajaran bahasa Jepang, "mereka belum siap untuk menggelontorkan uang pajak ke dalamnya," kata Toshinori Kawaguchi, direktur divisi pekerja asing di Kementerian Kesehatan, Tenaga Kerja, dan Kesejahteraan Jepang.
Hal ini membuat pemerintah kota dan pemberi kerja harus memutuskan apakah dan seberapa sering mereka akan memberikan pelatihan bahasa. Pengelola panti jompo yang mempekerjakan Thazin di Maebashi, ibu kota Prefektur Gunma di Jepang bagian tengah, menyediakan satu hari pelajaran bahasa Jepang berkelompok bagi beberapa pengasuh, serta satu pelajaran tambahan berdurasi 45 menit setiap bulan. Namun, para pekerja yang menyiapkan makanan di panti jompo hanya menerima satu pelajaran berdurasi 45 menit setiap bulan.
Akira Higuchi, presiden perusahaan Hotaka Kai, mengatakan ia mendorong karyawan untuk belajar bahasa Jepang secara otodidak. Mereka yang lulus tes kemampuan bahasa Jepang tingkat kedua tertinggi dari pemerintah, katanya, "akan diperlakukan sama dengan orang Jepang, dengan gaji dan bonus yang sama."
Terutama di luar kota-kota besar, orang asing yang tidak bisa berbahasa Jepang mungkin kesulitan berkomunikasi dengan pihak berwenang setempat atau sekolah. Dalam keadaan darurat medis, hanya sedikit staf rumah sakit yang bisa berbahasa selain bahasa Jepang.
Hotaka Kai telah mengambil langkah-langkah lain untuk mendukung karyawannya, termasuk menyediakan akomodasi bagi pendatang baru di apartemen perusahaan bersubsidi dan menyediakan pelatihan keterampilan.

Gurung Nissan (kanan), seorang pekerja asal Nepal, menggelar futon di wisma Ginshotei Awashima. Foto: New York Times
Dapur bersama yang dihuni 33 perempuan berusia 18 hingga 31 tahun menawarkan sekilas gambaran warisan mereka yang saling terkait. Dari tempat sampah plastik berlabel nama-nama penghuni, tampak bungkusan merica bubuk Ladaku (pasta lada putih khas Indonesia) dan bungkusan bumbu babi rebus ala Vietnam.
Di seluruh Prefektur Gunma, ketergantungan pada tenaga kerja asing terlihat jelas. Di Oigami Onsen, sebuah desa di lereng gunung tempat banyak restoran, toko, dan hotel tutup, separuh dari 20 staf penuh waktu di Ginshotei Awashima, sebuah penginapan pemandian air panas tradisional, berasal dari Myanmar, Nepal, atau Indonesia.
Karena penginapan itu terletak di daerah pedesaan, "tidak ada lagi orang Jepang yang mau bekerja di sini," kata Wataru Tsutani, pemilik penginapan itu.
Ngun Nei Par, manajer hostel, lulus dari sebuah universitas di Myanmar dengan gelar di bidang geografi. Ia berharap pemerintah Jepang akan memfasilitasi naturalisasinya agar ia dapat membawa keluarganya ke Jepang suatu hari nanti.
Namun Tuan Tsutani, pemilik penginapan, mengatakan masyarakat, yang belum menyadari kenyataan, akan protes jika terlalu banyak orang asing yang mengajukan kewarganegaraan.
"Saya sering mendengar orang bilang Jepang itu 'negara yang unik'," kata Pak Tsutani. "Tapi tidak perlu mempersulit orang asing yang ingin tinggal di Jepang. Kami ingin pekerja."
Quang Anh
[iklan_2]
Sumber: https://www.congluan.vn/nhat-ban-can-lao-dong-nuoc-ngoai-va-nghich-ly-khong-the-giu-chan-post306483.html



![[Foto] Siap untuk Pameran Musim Gugur 2025](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/1200x675/vietnam/resource/IMAGE/2025/10/14/1760456672454_ndo_br_chi-9796-jpg.webp)
















































































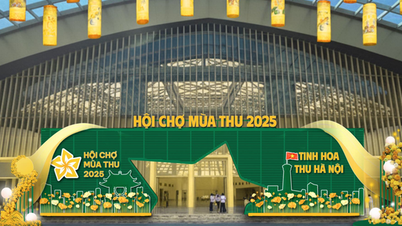











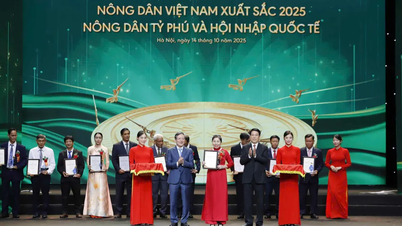

















Komentar (0)