Bau kapur dan cat baru masih tercium di ruangan kecil itu. Chi berdiri di depan pintu kayu bercat biru muda, dengan tulisan "Kelas Intervensi Dini" yang ditulis dengan teliti oleh Guru Lan.
Dari dalam terdengar tangisan anak-anak yang sumbang dan tak beraturan, bercampur dengan dentingan benda jatuh. Chi menarik napas dalam-dalam, tangannya menggenggam erat tas kulit tuanya—hadiah pemberian ibunya saat ia mengikuti ujian masuk universitas, dengan harapan ia akan menjadi guru terkenal.
 |
| Ilustrasi: AI |
Tiga tahun lalu, di persimpangan jalan yang menentukan, Chi memilih jalan yang ditentang semua orang. " Pendidikan khusus? Apa kau gila?" suara ibunya menggema di tengah makan malam yang menentukan itu. "Apa gunanya kuliah? Gaji rendah, kerja keras, dan harus berurusan dengan... anak-anak yang tidak biasa." Ayahnya terdiam, hanya menggelengkan kepala, kekecewaan terpancar di matanya.
Pak Minh, wali kelas 12, memanggil Chi ke ruang pribadinya hari itu. "Kamu punya potensi untuk mendapat nilai tinggi di ujian, kenapa kamu memilih jurusan ini? Apa kamu sudah memikirkannya matang-matang? Mencari pekerjaan di jurusan keguruan biasa saja sulit, apalagi pendidikan khusus." Guru itu menatap Chi dengan cemas, "Saya sarankan kamu berpikir ulang."
Namun Chi tahu, sejak hari itu, sejak sore itu empat tahun lalu, ketika ia kebetulan melewati pusat intervensi dini di dekat rumahnya. Seorang anak laki-laki, sekitar lima tahun, sedang duduk sendirian di sudut halaman, memegang sehelai daun kering di tangannya, menggumamkan suara-suara yang tak seorang pun mengerti.
Guru muda itu berjalan mendekat, duduk di sampingnya, tanpa berkata apa-apa, hanya diam memetik daun bersama anak laki-laki itu. Sepuluh menit kemudian, anak laki-laki itu menatap matanya untuk pertama kalinya, dan tersenyum kecil. Dan Chi berdiri di luar gerbang, entah kenapa, air matanya terus mengalir.
Pintu terbuka. Guru Lan keluar, rambutnya diikat rapi, matanya agak gelap. "Chi ada di sini? Masuklah, anak-anak sudah menunggu saya." Suaranya lembut namun sedikit lelah.
Kelasnya kecil, hanya berisi lima anak. Seorang gadis kecil duduk di pojok, terus-menerus mengetuk-ngetukkan jarinya. Seorang anak laki-laki kecil tergeletak di lantai, matanya terpaku pada ubin di lantai. Anak lainnya berlarian ke sana kemari, terus-menerus berseru "ah... ah... ah...". Anak-anak ini istimewa, masing-masing punya dunianya sendiri, tak ada dua yang sama.
"Namaku Chi, panggil saja aku Nona Chi," kata Chi, berusaha terdengar tenang meskipun jantungnya berdebar kencang. Tak seorang pun anak-anak memandangnya. Anak laki-laki itu masih terbaring di tanah, anak perempuan itu masih menghitung dengan jari, dan anak yang satunya lagi masih berlarian.
"Anak saya autis, tidak melakukan kontak mata, tidak merespons kata-kata," jelas Bu Lan kepada setiap anak satu per satu. "Mereka membutuhkan kesabaran yang tak terbatas. Ada hari-hari di mana mereka tidak mendengar apa-apa, ada hari-hari di mana mereka berteriak berjam-jam. Tetapi ada juga hari-hari di mana, meski hanya sedetik, mereka menatap mata saya, tersenyum, mengucapkan sepatah kata... lalu semuanya terbayar lunas."
Beberapa minggu pertama bagaikan mimpi buruk. Chi pulang setiap malam dengan tangan digaruk oleh saudara-saudaranya, dan suaranya serak karena berbicara keras seharian tanpa mereka dengar. Suatu hari, An akan menjentikkan jari dan berteriak selama dua jam karena ia tidak suka warna bajunya. Di hari lain, Minh akan berbaring di lantai dan memukul wajahnya ketika ia mencoba mengangkatnya.
"Kenapa kamu tidak keluar saja? Cari pekerjaan lain," kata ibunya ketika melihat memar di lengan Chi. "Sudah kubilang dari awal, tapi kamu tidak mau dengar."
Chi tak tahu harus menjawab apa. Malam-malam itu, ia terjaga, bertanya-tanya apakah ia telah melakukan kesalahan. Gaji rendah, kerja keras, tak seorang pun mengenalinya, dan ia terluka fisik dan mental. Mengapa ia memilih jalan ini?
Hingga Kamis pagi di minggu kedelapan. Chi, seperti biasa, duduk di sebelah An, tanpa berkata apa-apa, hanya diam menyusun balok-balok kayu berwarna. Satu merah, satu biru, satu kuning. Berulang kali. An terus menghitung dengan jari-jarinya, tanpa melihat. Namun kemudian, bagaikan keajaiban kecil, tangan mungil An terulur, mengambil balok kayu merah itu, dan meletakkannya di atas tumpukan balok yang baru saja disusun Chi.
"An... An berhasil!" teriak Chi, air mata menggenang di matanya. Bu Lan berlari menghampiri, melihat kejadian itu, dan memeluk Chi. "Delapan minggu! Delapan minggu bagi An untuk akhirnya bisa berinteraksi. Kamu hebat!"
Malam itu, Chi menelepon ke rumah, suaranya tercekat karena emosi: "Bu, hari ini aku mengajari seorang anak memegang bola kayu. Kedengarannya sepele, kan? Tapi bagi anak itu, itu adalah langkah maju yang luar biasa."
Ibu terdiam di ujung telepon, lalu mendesah: "Kalau kamu suka, silakan saja. Ibu tidak begitu mengerti, tapi mendengarmu terdengar senang..."
***
Tahun berikutnya, Chi dirawat di pusat intervensi yang lebih besar di pinggiran kota. Kelas itu beranggotakan sepuluh anak, masing-masing dengan tingkat autisme yang berbeda. Beberapa menderita sindrom Down, beberapa menderita cerebral palsy, dan beberapa mengalami keterlambatan perkembangan. Wajah mereka polos tetapi mengandung banyak kesulitan.
Duc yang berusia tujuh tahun masih belum bisa bicara. Ibunya menghampiri Chi dengan mata merah: "Bu, Duc bisa belajar?" Chi memegang tangan ibunya, "Ibu Duc, setiap anak punya caranya sendiri untuk berkembang. Aku yakin Duc pasti bisa bicara."
Namun setelah tiga bulan, Duc masih diam. Enam bulan berlalu, Duc hanya mengeluarkan suara "uh... uh...". Chi mulai meragukan dirinya sendiri. Apakah ia tidak cukup mampu? Haruskah ia belajar lebih banyak, menemukan metode baru?
Larut malam, Chi duduk membaca dokumen-dokumen dan menonton video para pakar asing yang mengajar anak-anak autis. Ia mempelajari teknik ABA (analisis perilaku terapan), terapi sensorik, dan bahasa isyarat. Setiap pagi ia bangun dengan lingkaran hitam di bawah matanya, tetapi ia tetap pergi ke kelas dengan senyum.
"Duc, hari ini kita akan belajar kata 'ibu'," kata Chi sambil menunjuk gambar itu. "I-ibu. Coba ucapkan kata itu setelah aku." Duc menatap gambar itu, mulutnya bergerak, tetapi tidak ada suara yang keluar. Satu hari, dua hari, satu minggu, dua minggu...
Bulan kesembilan, pagi yang normal. Ibu Duc datang menjemputnya dari sekolah. Duc berlari menghampirinya, memeluknya erat, dan untuk pertama kalinya, dari tenggorokannya yang kecil, sebuah suara yang jelas keluar: "Bu..."
Ruang kelas terasa membeku. Ibu Duc berlutut, memeluk anaknya, dan menangis. Chi berdiri di sana, air mata mengalir dengan sendirinya. Bulan-bulan yang penuh kesulitan, malam-malam tanpa tidur, semuanya terbayar lunas. Hanya karena satu kata itu, "Ibu".
"Terima kasih... terima kasih banyak," kata ibu Duc sambil menggenggam tangan Chi dan terisak. "Kau tahu, selama tujuh tahun terakhir, aku tak pernah memanggilmu Ibu sekali pun. Hari ini... hari ini aku bisa mendengarmu memanggilku Ibu..."
***
Lima tahun telah berlalu sejak Chi memulai kariernya. Ia kini menjadi pemimpin kelas intervensi dini. Anak-anak telah tumbuh dewasa, beberapa di antaranya telah dapat berintegrasi ke sekolah reguler. An, gadis kecil yang hanya tahu cara menghitung jari, kini duduk di kelas dua, belajar bersama teman-temannya. Duc telah belajar mengucapkan banyak kata dan sedang belajar membaca buku bergambar.
Namun masih ada anak-anak baru, tantangan baru. Hung, autis berat, berusia delapan tahun, masih belum bisa berkomunikasi. Lan, sindrom Down, berusia sepuluh tahun, masih belajar huruf pertamanya. Di hari-hari ketika Chi lelah dan ingin menyerah, ia menatap mata anak-anak itu—jernih, polos, dan penuh harapan.
"Kenapa kamu tetap di sini?" tanya seorang teman lama kepada Chi saat reuni. "Gaji rendah, tekanan tinggi, dan banyak kesulitan. Apa kamu tidak berpikir untuk beralih mengajar di sekolah biasa?"
Chi memandang ke kejauhan, lalu tersenyum: "Dulu aku berpikir begitu. Tapi kemudian aku sadar, anak-anak ini membutuhkanku. Mereka tidak terlahir sempurna, tetapi mereka pantas dicintai, dididik, dan diberi kesempatan. Dan setiap kali aku melihat seorang anak berkembang, meski hanya sedikit, aku merasa semua itu sepadan."
Malam itu, Chi duduk di ruang kelas yang kosong. Di atas meja terdapat coretan-coretan anak-anak, tulisan tangan yang berantakan, dan mainan-mainan yang berantakan. Ia mengambil buku catatan Hung dan membolak-balik halamannya. Halaman pertama hanya coretan-coretan, halaman tengahnya lingkaran yang terdistorsi, halaman terakhir... sebuah figur manusia yang sederhana namun jelas. Dan di sebelahnya, dua kata yang ditulis dengan rapi: "Nona Chi".
Air mata Chi jatuh di atas garis-garis itu. Ia mengambil pena dan menulis di halaman berikutnya:
Anak-anak istimewa tidak butuh belas kasihan. Mereka butuh rasa hormat, kesabaran, dan kasih sayang tanpa syarat. Jalan pendidikan khusus tidaklah mudah. Ada kalanya saya ingin menyerah, dan ada kalanya saya bertanya-tanya apakah saya masih punya cukup kekuatan. Namun, setiap kali saya melihat seorang anak tersenyum atau melihat kemajuan, saya tahu inilah jalan yang ditakdirkan untuk saya tempuh.
Di luar jendela, matahari terbenam di balik pepohonan royal poinciana. Kicau tonggeret menandakan datangnya musim panas. Dan di ruang kelas kecil itu, di antara mainan, buku catatan, dan coretan, cinta tumbuh perlahan.
***
Sepuluh tahun kemudian, Chi berdiri di atas panggung untuk menerima sertifikat "Guru Berprestasi Pendidikan Khusus". Ibunya duduk di barisan depan, rambutnya beruban, tetapi matanya berbinar bangga. Ayahnya berdiri di sampingnya, berusaha menahan tangis.
"Saya ingin berterima kasih kepada anak-anak yang telah mengajari saya arti kesabaran dan kasih sayang tanpa syarat," kata Chi dengan suara gemetar. "Saya ingin berterima kasih kepada orang tua saya yang, meskipun ragu, tetap membiarkan saya mengikuti jalan yang saya pilih. Dan saya ingin mengatakan kepada anak-anak muda yang masih ragu-ragu: percayalah pada panggilan hatimu. Ada pekerjaan yang tidak mendatangkan ketenaran atau kekayaan, tetapi memberi makna – makna hidup yang sesungguhnya."
Di auditorium, anak-anak Chi yang dulu bertepuk tangan. An, yang kini duduk di kelas delapan, tersenyum lebar. Duc, yang kini fasih berbicara, melambaikan tangan padanya. Dan anak-anak baru, yang masih berjuang, dibawa oleh orang tua mereka untuk menyaksikan momen ini.
Chi turun dari panggung dan memeluk erat kedua orang tuanya. "Aku tidak menyesal," bisiknya. "Meskipun sulit dan melelahkan, aku sangat bahagia."
Ibu mengelus rambut putranya, air mata mengalir: "Aku tahu, Nak. Aku tahu hanya dengan melihatmu. Maafkan aku karena pernah menolakmu."
Sore perlahan memudar. Sinar matahari bersinar menembus jendela-jendela besar, menyinari wajah-wajah yang tersenyum. Chi tahu bahwa jalan yang dipilihnya, meskipun berduri dan mewah, adalah jalan paling benar yang pernah ditunjukkan hatinya.
MAI HOANG (Untuk Linh Chi)
Sumber: https://baovinhlong.com.vn/van-hoa-giai-tri/tac-gia-tac-pham/202511/truyen-ngan-lop-hoc-cua-chi-26e0458/




![[Foto] Presiden Luong Cuong menerima Menteri Perang AS Pete Hegseth](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/1200x675/vietnam/resource/IMAGE/2025/11/02/1762089839868_ndo_br_1-jpg.webp)


















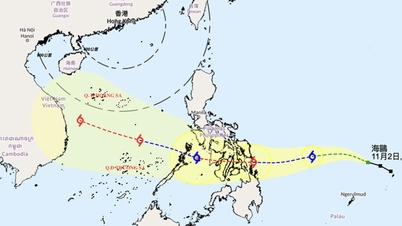



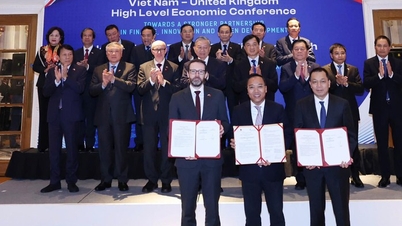









































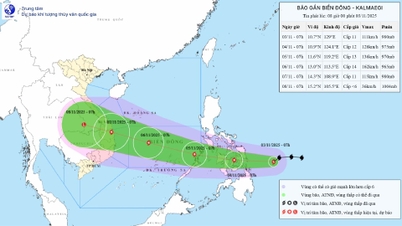







































Komentar (0)