Identitas yang tidak stabil di tengah pusaran integrasi
"Badai 4.0" tak hanya menyapu bersih jarak geografis, tetapi juga nilai-nilai budaya asli. Ekspresi hibrida, pemujaan asing, dan peniruan buta tren daring perlahan-lahan menjadi populer di kalangan anak muda di dataran tinggi. Mereka mudah terjerumus ke dalam "tren kehidupan virtual", ke dalam budaya "datar" tanpa seleksi, di mana semua batas identitas terhapus.
Yang paling kentara adalah hibriditas budaya di media sosial. Anak-anak muda dataran tinggi menerima tren global dengan sangat cepat, tetapi kurang memiliki pilihan. Banyak klip di TikTok, Facebook, dan YouTube menggunakan gambar kostum tradisional, tetapi terlalu banyak ditransformasikan, menjadi properti "kehidupan virtual", alih-alih simbol budaya. Banyak kasus anak muda mengenakan kostum bergaya yang menyinggung, menari di tempat-tempat sakral, menjadikan warisan budaya sebagai alat untuk menarik perhatian dan suka.
Contoh kontroversialnya adalah wisatawan berkostum eksotis yang berfoto di Sungai Nho Que (Tuyen Quang)—sebuah wilayah yang terkait dengan kehidupan spiritual dan kepercayaan masyarakat Mong. Tindakan yang tampaknya tidak berbahaya ini menyentuh kebanggaan budaya, karena tempat itu bukan hanya tempat yang indah, tetapi juga ruang identitas. Ketika pariwisata menjadi "tren trendi", memasukkan unsur-unsur eksotis ke dalam simbol budaya nasional secara sembarangan adalah cara tercepat untuk "mengikis" identitas.
 |
| Kelompok etnis Thuy di desa Thuong Minh, kecamatan Minh Quang saat ini hanya melestarikan 3 set pakaian tradisional. |
Tak hanya orisinalitas yang hilang, generasi muda juga kehilangan kemampuan untuk mengidentifikasi budaya mereka sendiri. Bahasa daerah tergantikan oleh "bahasa internet" campuran: "Xoa", "khia", "mlem", "viral", "check-in"... Sementara ajaran para tetua desa dibayangi oleh idola virtual, "khen memanggil teman" perlahan-lahan digantikan oleh klip-klip tak bermutu yang tersebar di internet.
Di Pasar Sa Phin, tempat suara seruling panpipe dan suling dulu menggema memanggil teman, kini musik elektronik mengalahkan suara para pedagang. Gaun brokat tenun tangan yang indah telah tergantikan oleh pakaian jadi yang murah. Mong Sung Thi Sinh, 16 tahun, tertawa terbahak-bahak di ponselnya: "Sekarang, membeli pakaian jadi sangat praktis, murah, dan indah, dan menonton video di ponsel itu menyenangkan." Kata-kata itu polos namun memilukan – ketika nilai-nilai budaya berusia ribuan tahun tergerus oleh dunia maya di generasi muda.
Ibu Ly Gia Tan, suku Nung, komune Ho Thau, berbagi: “Anak muda zaman sekarang suka berselancar di TikTok dan Facebook, mencari "standar" kecantikan dan gaya yang umum. Itulah yang membuat banyak anak muda membandingkan diri dan menganggap budaya etnis mereka "kasar" dan ketinggalan zaman. Banyak anak muda meninggalkan pakaian tradisional mereka dan mengenakan celana jin dan kaus, berbicara bahasa Kinh alih-alih bahasa ibu mereka, menyanyikan lagu-lagu komersial alih-alih lagu daerah etnis mereka sendiri. Saya merasa sangat sedih!”
Budaya tradisional mengandung nilai-nilai humanis bakti kepada orang tua, keimanan, dan kohesi komunitas. Namun, ketika pengetahuan budaya kurang dan tidak memiliki dasar untuk "memisahkan yang kotor dan mengeluarkan yang bersih", jejaring sosial justru turut menyebarkan adat istiadat buruk, mengubah nilai-nilai menjadi beban, ritual menjadi formalitas, dan warisan menjadi alat untuk "menarik perhatian".
Pada tahun 2023, Bapak VMG di komune Meo Vac mengadakan pemakaman untuk ibunya sesuai adat istiadat lama: berlangsung selama tiga hari, menyembelih banyak ternak, dan tidak memasukkan jenazah ke dalam peti jenazah. Setelah pemakaman, beliau terlilit utang yang besar, dan keluarganya jatuh miskin. Di media sosial, foto-foto pemakaman mewah itu dibagikan dan dikomentari, sehingga tradisi tersebut secara tidak sengaja digambarkan sebagai perwujudan bakti kepada orang tua atau "mempertahankan adat istiadat lama", padahal sebenarnya, tradisi tersebut kuno dan mahal.
Jejaring sosial tidak hanya menjadi tempat penyebaran tren menyimpang, tetapi juga menjadi alat bagi jaringan penipuan, perdagangan manusia, penyebaran ajaran sesat, dan penyebaran paham sesat. Trik seperti "kerja mudah, gaji tinggi", "nikah mewah", atau "hasilkan uang lewat TikTok" telah menjerat banyak warga di dataran tinggi. Baru-baru ini, Thao Mi Sinh (Kelurahan Son Vi, Tuyen Quang , kelahiran 1995) ditangkap karena menggelapkan lebih dari 556 juta VND dari 11 orang dengan tipu daya "membuat kanal jejaring sosial untuk menghasilkan uang". Ini adalah contoh nyata sisi gelap teknologi ketika kurangnya pemahaman dan kewaspadaan. Hanya dari satu klik virtual, konsekuensinya nyata: uang hilang, kepercayaan dicuri, dan rusaknya kepercayaan masyarakat.
Risiko erosi identitas tidak hanya berasal dari pusaran teknologi atau masuknya gaya hidup modern, tetapi juga dari proses globalisasi dan pengaruh halus kekuatan-kekuatan yang bermusuhan. Yang lebih berbahaya, kekuatan-kekuatan yang bermusuhan telah memanfaatkan jejaring sosial untuk mengubah ranah ideologis dan budaya secara damai.
Banyak aliran sesat dan organisasi reaksioner berkedok agama telah menyusup ke wilayah perbatasan, menyebarkan takhayul dan memecah belah kepercayaan masyarakat. Contoh tipikal adalah aliran "San su khe to" yang pernah menyihir lebih dari 1.200 rumah tangga dengan hampir 6.000 jiwa di Dataran Tinggi Batu Dong Van, menyebabkan banyak desa menjadi kacau. Atau fenomena aliran "Duong Van Minh", yang selama tiga dekade terakhir telah meninggalkan konsekuensi serius dalam kehidupan spiritual sebagian masyarakat Mong di Tuyen Quang.
Dengan kedok "keyakinan baru", Duong Van Minh menyebarkan ideologi separatis, menggelapkan uang dengan trik "Dana Emas", dan bahkan berencana mendirikan "Negara Mong". Meskipun organisasi sesat ini telah diberantas, jejak ideologi ekstremis tersebut masih membara bagai benih beracun di dunia maya, di mana elemen-elemen kuncinya telah terhubung dengan organisasi reaksioner Viet Tan dan Dan Lam Bao, membuat halaman penggemar dan kanal YouTube untuk mendistorsi, memicu perpecahan etnis, dan menebar kebingungan di komunitas Mong.
Manifestasi-manifestasi di atas bukan hanya kisah tentang "lunturnya identitas", tetapi juga peringatan akan kesenjangan pengetahuan dan identitas budaya. Ketika generasi muda semakin terlena dalam jejaring sosial, tanpa memahami akar mereka; ketika nilai-nilai material mengalahkan nilai-nilai spiritual, kepercayaan dan identitas mudah goyah—dan itulah kelemahan yang dimanfaatkan oleh kekuatan-kekuatan musuh untuk menyerang.
"Penjaga api" dan ketakutan terhadap bara api
Setiap seniman adalah "obor hidup" yang melestarikan jiwa bangsa. Namun ketika obor itu perlahan padam, ketika bahasa ibu tak lagi terdengar dalam suara anak-anak, kekhawatirannya bukan hanya hilangnya adat istiadat atau bahasa, tetapi juga menyusutnya "wilayah lunak" – inti yang membentuk ketahanan budaya daerah perbatasan.
Di komune perbatasan, tempat orang Mong mencapai lebih dari 80%, suara seruling Mong adalah jiwa, sumber abadi. Namun, generasi yang tahu cara membuat dan memainkan seruling kini dapat dihitung dengan jari. Di sebuah rumah kecil yang terletak di lereng berbatu di Dong Van, pengrajin Ly Xin Cau bertanya kepada cucu-cucunya yang sedang asyik bermain ponsel:
"Setelah aku meninggal, apakah kalian anak-anak yang lain tahu cara memainkan seruling Mong?"
Keponakan yang polos itu menjawab: "Aku akan memfilmkanmu dan mengunggahnya ke internet, mungkin akan ditonton sejuta orang."
Pak Cau terdiam. Generasi muda percaya bahwa media sosial dapat "menyelamatkan" budaya, tetapi ia jelas memahami bahwa budaya tidak bisa hanya hidup dalam video. Budaya perlu dihembuskan dengan kehidupan nyata, dengan kebanggaan dan kecintaan anak muda terhadap akar mereka.
Di Desa Ma Che, komune perbatasan Sa Phin—tempat tinggal bersama suku Mong dan Co Lao—profesi menenun pernah dianggap sebagai "museum hidup". Namun, menurut Sekretaris Sel Partai Sinh Mi Minh, kini hanya tersisa 8 rumah tangga yang masih menekuni profesi ini. Setiap pasang tangan yang berhenti menenun adalah benang kenangan yang putus, bagian dari warisan yang hilang diam-diam di tengah hiruk pikuk mencari nafkah.
Ketakutan akan kemunduran tidak berhenti di satu desa. Di awal tahun 2023, kabar meninggalnya seniman Luong Long Van, seorang etnis Tay di distrik An Tuong (Tuyen Quang), di usia 95 tahun membuat banyak orang terdiam. Ia adalah salah satu dari sedikit orang yang masih fasih berbahasa aksara Tay Nom – "kunci budaya" yang membuka khazanah pengetahuan rakyat. Sepanjang hidupnya, ia diam-diam menyusun, menerjemahkan, dan mengajarkan lebih dari seratus buku kuno, puluhan jilid doa, nasihat, dan resep obat. Karya-karya seperti "Beberapa Istana Then Kuno dalam Aksara Nom - Tay" atau "Van Quan dari Desa Tuyen Quang" adalah bukti kehidupan yang didedikasikan untuk budaya. Rumah kecil yang dulu ramai dengan suara mahasiswa kini setenang ruang kosong "harta karun hidup" yang baru saja ditutup.
Orang Dao dan Tay dulu menyimpan buku-buku doa dan buku-buku ajaran sebagai pusaka, mewariskan semangat klan mereka kepada banyak generasi. Namun kini, banyak keluarga telah lupa cara membaca dan menyalin; pusaka tersebut terlipat, ditaruh di sudut lemari, menunggu untuk tertutup debu. Bagi orang Lo Lo, yang tidak memiliki tulisan sendiri, bahaya ini bahkan lebih nyata. Ketika para tetua—"perpustakaan hidup" desa—berangsur-angsur meninggal, khazanah pengetahuan rakyat lisan pun ikut memudar.
Seniman berprestasi Lo Si Pao, dari komune Meo Vac, khawatir: "Saat ini, anak muda hanya berbicara dalam bahasa umum, hanya sedikit yang menggunakan bahasa ibu mereka. Mereka takut berbicara, lalu lupa berbicara, dan akhirnya kehilangan bahasa mereka sendiri." Sebuah ungkapan sederhana namun mengandung kepedihan dari sebuah budaya yang berada di ambang kehancuran.
Tak hanya bahasa, tetapi juga pakaian dan gaya hidup—simbol identitas budaya—berubah dengan cepat. Di banyak desa, warna nila dan linen yang dulu menjadi nafas masyarakat Giay dan Mong juga menghilang. Pengrajin Vi Dau Min, seorang Giay di komune Tat Nga, dengan sedih berkata: "Pakaian bukan sekadar pakaian, tetapi juga identitas masyarakat Giay. Sekarang, anak-anak hanya menyukai pakaian modern. Ketika diminta mengenakan pakaian tradisional, mereka tertawa dan berkata, "Ini hanya cocok untuk perayaan." Saya khawatir di masa depan, adat istiadat lama akan hilang bersama para lansia."
Kurangnya ruang bagi budaya untuk “bernapas”
Jika identitas adalah jiwa suatu bangsa, maka ruang budaya adalah napas jiwa tersebut. Di banyak desa di dataran tinggi, napas itu memudar bukan karena kurangnya kesadaran, melainkan karena kurangnya ruang bagi budaya untuk "hidup".
Institusi budaya yang lemah, infrastruktur yang lemah, mekanisme yang lambat, dan kehidupan masyarakat yang sulit telah menyebabkan banyak kegiatan masyarakat memudar. Festival-festival tradisional di banyak tempat hanya hadir dalam gaya "pertunjukan", bahkan dipentaskan dan dikomersialkan, kehilangan jiwanya. Sementara itu, ruang-ruang budaya baru—pariwisata dan urbanisasi—tidak cukup mendalam untuk memelihara inti nasional. Budaya "tertahan" di antara dua celah: masa lalu tak lagi tersentuh, masa kini tak lagi punya tempat untuk dipupuk.
Di komune perbatasan seperti Son Vi, Bach Dich, Dong Van, dll., rumah-rumah tanah emas—simbol arsitektur Mong—tergantikan oleh rumah-rumah beton bergaya "melintasi perbatasan". Seniman rakyat Mua Mi Sinh, Desa Sang Pa B, Komune Meo Vac, khawatir: "Memperbaiki perumahan memang baik, tetapi ketika arsitektur tradisional hilang, ruang budaya pun hilang. Rumah tanah bukan hanya tempat tinggal, tetapi juga kristalisasi tangan, pikiran, dan filosofi hidup yang selaras dengan pegunungan dan hutan. Ketika rumah tak lagi mempertahankan jiwa aslinya, desa juga kehilangan bentuk budayanya."
Di Desa Lung Lan, komune perbatasan Son Vi, terdapat 121 rumah tangga dari 9 kelompok etnis yang hidup berdampingan, 40 di antaranya adalah orang Xuong, dengan jumlah penduduk hampir 200 jiwa. Ibu Hoang Thi Tuong, 63 tahun, bercerita: “Dalam KTP kami, kami tercatat sebagai “kelompok etnis Xuong (Nung)” - artinya orang Xuong hanyalah cabang dari orang Nung. Meskipun mereka memiliki bahasa, adat istiadat, dan kostum sendiri, karena kurangnya mekanisme pengakuan dan keterbatasan ruang hidup, budaya Xuong secara bertahap berasimilasi dan harus “bernapas” di ruang kelompok etnis lain.”
Tak hanya orang Xuong, banyak komunitas kecil lainnya juga perlahan menghilang dari peta budaya etnis. Di Desa Thuong Minh, Komune Minh Quang, kelompok etnis Thuy—satu-satunya komunitas yang tersisa di Vietnam—hanya memiliki 21 rumah tangga dan kurang dari 100 orang. Bapak Mung Van Khao, 81 tahun, "harta karun hidup" orang Thuy, dengan sedih berkata: "Sekarang semua kartu identitas warga negara kita bertuliskan nama kelompok etnis Pa Then. Generasi mendatang tidak akan lagi tahu bahwa mereka adalah orang Thuy. Hanya orang tua yang masih ingat bahasa kuno, dan seluruh desa hanya memiliki tiga set pakaian yang tersisa."
Kisah-kisah ini menunjukkan bahwa ketika budaya tidak memiliki ruang untuk “bernapas”, warisan tidak dapat hidup, tidak peduli seberapa baik kebijakannya.
Pada tahun 2016, Dewan Rakyat Provinsi Ha Giang (lama) mengeluarkan Resolusi 35 - yang diharapkan menjadi "angin baru" untuk membantu membangkitkan potensi pariwisata komunitas, menciptakan mata pencaharian berkelanjutan yang berkaitan dengan budaya adat. Lebih dari 24,6 miliar VND digelontorkan untuk mendukung 285 organisasi dan individu berinvestasi di bidang akomodasi dan mengembangkan pariwisata komunitas - sebuah model yang diharapkan dapat mengubah budaya menjadi sumber daya pembangunan. Namun, hanya setelah tiga tahun, Resolusi 35 harus "dihentikan". Memiliki kebijakan dan modal, tetapi kurang perencanaan, mekanisme operasional, dan "subjek budaya" yang memimpin, membuat model-model ini hanya berhenti di tingkat "pembentukan", bukan menjadi landasan identitas.
Kisah masyarakat Pa Then adalah contoh lain. Kelompok etnis ini tinggal di komune Tan Trinh, Tan Quang, Minh Quang, Tri Phu, yang terkenal dengan kekayaan tarian api, tarik alu, sembahyang panen, dan tenun—warisan yang sakral sekaligus unik. Namun, jumlah pengrajin yang berpengetahuan dan mampu mengajar semakin berkurang.
Pada tahun 2022, Proyek 6 dalam Program Target Nasional untuk Pembangunan Sosial-Ekonomi Kawasan Etnis Minoritas dilaksanakan, dengan harapan memulihkan identitas yang terkait dengan pariwisata. Proyek ini memiliki 19 konten spesifik. Dalam periode 2022-2025, dengan total modal lebih dari 224 miliar VND, 7 festival dilestarikan, 3 jenis budaya yang terancam punah dipulihkan, dan 19 kelas belajar dibuka.
Namun, angka tersebut masih terlalu kecil dibandingkan dengan kenyataan: Menurut Dinas Kebudayaan, Olahraga, dan Pariwisata Tuyen Quang, hampir 30% festival dataran tinggi terancam punah hanya dalam 5 tahun terakhir. Banyak lembaga budaya terdegradasi, rumah adat desa terbengkalai, dan ruang hidup masyarakat menyempit, sehingga mustahil untuk sepenuhnya mereproduksi ritual dan festival. Orang-orang tidak memiliki tempat untuk bernyanyi, menari Sluong, mementaskan Khen, atau menabuh genderang festival. Jika budaya ingin hidup, pertama-tama ia harus memiliki tempat untuk "bernapas".
Oleh karena itu, menjaga ruang bagi budaya untuk "bernapas" bukan hanya soal melestarikan warisan, tetapi juga menjaga fondasi spiritual, menjaga "perisai lembut" keamanan perbatasan. Budaya hanya benar-benar hidup ketika masyarakat menjadi subjek, mengamalkannya, dan bangga dengan identitas mereka. Kita perlu mengembalikan rumah-rumah budaya yang bercahaya, lapangan festival yang ramai dengan alunan suara Khen, kelas-kelas pengajaran bahasa, dan restorasi kerajinan tradisional ke desa-desa. Hanya dengan demikianlah budaya dapat benar-benar "bernapas" dan perbatasan benar-benar berkelanjutan.
(Bersambung)
Dilakukan oleh: Mai Thong, Chuc Huyen, Thu Phuong, Bien Luan, Giang Lam, Tran Ke
Sumber: https://baotuyenquang.com.vn/van-hoa/202510/vanh-dai-van-hoa-soi-sang-bien-cuong-ky-2-nguy-co-xoi-mon-cot-moc-van-hoa-a483a3a/





![[Foto] Banjir di sisi kanan gerbang, pintu masuk Benteng Hue](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/1200x675/vietnam/resource/IMAGE/2025/10/28/1761660788143_ndo_br_gen-h-z7165069467254-74c71c36d0cb396744b678cec80552f0-2-jpg.webp)
![[Foto] Perdana Menteri Pham Minh Chinh memimpin pertemuan untuk membahas solusi mengatasi dampak banjir di provinsi-provinsi tengah.](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/1200x675/vietnam/resource/IMAGE/2025/10/29/1761716305524_dsc-7735-jpg.webp)
![[Foto] Ketua Majelis Nasional Tran Thanh Man menerima delegasi Partai Sosial Demokrat Jerman](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/1200x675/vietnam/resource/IMAGE/2025/10/28/1761652150406_ndo_br_cover-3345-jpg.webp)































![[Foto] Draf dokumen Kongres Partai ke-14 sampai di Kantor Pos Budaya Komune](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/1200x675/vietnam/resource/IMAGE/2025/10/28/1761642182616_du-thao-tai-tinh-hung-yen-4070-5235-jpg.webp)
![[Foto] Presiden Luong Cuong menghadiri Peringatan 80 Tahun Hari Adat Angkatan Bersenjata Daerah Militer 3](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/1200x675/vietnam/resource/IMAGE/2025/10/28/1761635584312_ndo_br_1-jpg.webp)










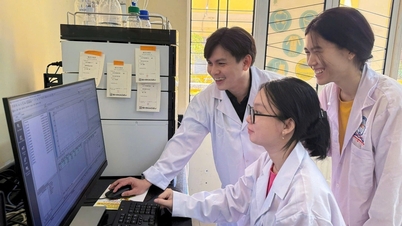






























































Komentar (0)