Sitar itu tetap sama selama bertahun-tahun, masih bekerja tanpa lelah di atas pasir, menunggu seseorang kembali?
"Jika kamu pergi sendiri, kamu akan tahu jalan kembali."
Ayah berteriak, tangannya mengambil beberapa ikan yang mati lemas dari jaring. Ikan-ikan itu terkapar kering di tengah keremangan musim badai, tergeletak di dasar panci, ditata dengan tergesa-gesa dalam wadah makanan tanpa tangan seorang wanita. Makananku dan Ayah, di antara dua pria, ke mana pun kami memandang, hanya ada keheningan dan kehampaan.
"Air bersih dari toples, buang rasa asinnya."
Ayah mendongak dan berbicara kepada bibinya. Gerombolan ikan itu berjuang keras melepaskan diri dari jaring berwarna melon. Suara Ayah mulai menghilang diterpa angin yang bersiul di atas pasir. Asinnya laut menghantui kehidupan para nelayan. Di malam hari, hati orang-orang seramai ombak. Bibi mengangguk pelan menanggapi Ayah, lalu membungkuk pelan dan masuk ke dalam rumah, persis seperti saat ia pergi.
Ayah menikahinya ketika kerinduannya pada ibunya perlahan mereda. Mereka menyebutnya pernikahan, tetapi mereka hanya menyiapkan tiga kali makan dan beberapa kotak sirih. Ia bertubuh kasar dan bermulut seperti ikan yang menonjol, seperti kata penduduk desa. Kisah-kisah penduduk desa nelayan berkisar seputar laut. Kecantikan bagaikan ikan, dan keburukan juga mendatangkan ikan.
Pada hari Ibu meninggal, Ayah mendaki bukit pasir dengan sebotol anggur putih yang setengah kosong. Ia menghabiskan sisa anggur itu hingga hari berakhir, hingga bulan terbit dan menyinari pasir putih.
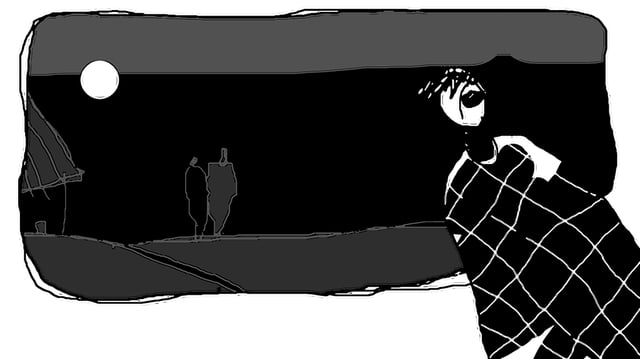
ILUSTRASI: VAN NGUYEN
Pada hari-hari ketika ayah mabuk, bibinya sendirian sibuk memasak untuk keluarga.
Laut mulai mengamuk. Suatu malam, ketika ayahku terhuyung mundur dari bukit pasir, bibiku berkata: "Kalau kau tak punya nyali untuk mati, kau harus hidup seperti manusia." Dua kata "manusia" tercekat di tenggorokan bibiku, gemerisik pohon cemara terdengar begitu dekat, menerbangkan nyawa seorang gadis. Bibiku hanya mengucapkan satu kalimat lalu pergi. Aku berbaring di sisi lain, berpura-pura tidur, langkah kaki bibiku terdengar jelas dan terhenti di samping tempat tidurku untuk waktu yang lama, badai berhenti di balik pintu, hati bibiku berdebar kencang. Aku tak membuka mata, tetapi tahu bibiku sedang menatapku, napasnya berembus lembut di kegelapan malam. Aku tak punya cukup nyali untuk menggenggam tangan bibiku. Bibiku harus menemukan kebahagiaannya sendiri di masa depan, seperti bunga kembang sepatu laut yang selalu menuju ke pantai. Kupikir begitu, dan aku sangat marah pada ayahku. Bibiku pergi karena ayahku yang terus-menerus mabuk? Ia telah bekerja keras membangun rumah ini, tetapi pada akhirnya, ia hanya menerima usaha yang sia-sia. Keesokan paginya, ketika laut masih mengantuk dalam kabut, aku tidak tahu apakah laut benar-benar tertidur, tetapi tadi malam ayahku tetap menyalakan lampu hingga fajar. Suara para nelayan mulai terdengar bagai sarang lebah yang patah. Anak-anak putus sekolah, membiarkan mimpi mereka hanyut bersama laut lebih awal.
Ketidakhadiran bibinya membangunkan ayahnya.
Pagi harinya, ayahku mengajakku ke laut. Sore harinya, bibiku mengajakku menyelami luasnya kenangan-kenanganku yang tak utuh. Luasnya laut, luasnya pasir putih, luasnya mimpi-mimpi yang jauh.
Ayah menenggelamkanku di air laut yang asin. Ayah bilang, kalau lahir di laut, harus bisa berenang agar bisa hidup. Aku meronta seperti ikan yang terjaring. Aku tersedak air dan kepalaku terus bergetar. Ayah berkata, "Kalau mau lihat laut dalam, tundukkan kepalamu. Lautan itu luas karena ia memilih tempat yang paling rendah." Aku berdebat dengan ayahku, bertanya-tanya mengapa ayahku tidak merendahkan harga dirinya selama bertahun-tahun bersama bibiku. Ia sesombong penguasa lautan. Ayah mengayunkan tangannya dan menamparku keras-keras, apa yang anak-anak tahu? Setiap malam, saat ayahku menatap potret ibuku, aku mencuri pandang dan tak bisa marah padanya. Aku tahu pria itu sedalam laut. Ibuku meninggal dunia, dan ayahku meletakkan kendi berisi air tawar di sebelah kanan pintu masuk. Ayah menyuruh anggota keluarga untuk mencuci kaki mereka ketika masuk rumah. Suatu kali, bibiku lupa dan dimarahi ayahku. Ia tetap diam dan menunduk memandangi kakinya yang kotor. Aku melakukan apa yang dikatakannya tanpa sepenuhnya memahami apa maksud ayahku.
Suatu hari, ayahku mengajariku melempar jaring. Ia melepas bajunya, memperlihatkan dadanya yang berotot, garis yang ia buat lebih halus daripada rambut ibuku. Ia melempar seolah ingin membuang semua dendam di hatinya, ia membuang semua rasa kantuk di malam hari yang membuncah bagai buih putih.
Di masa remajaku, tubuhku kurus kering seperti ikan yang jiwanya telah terkuras. Aku cepat menyerap ajaran ayahku, tetapi tak cukup kuat untuk mengayunkan jala. Ilusi pengembaraan terasa berat di pundakku. Ayahku tak berkata apa-apa, tetapi sorot matanya menunjukkan kekecewaan yang mendalam.
Sejak dini aku tahu bahwa aku bukan milik lautan. Sepanjang masa kecilku, aku tak pernah bermimpi tentang lautan, hanya sekawanan kuda putih yang menarikku mendaki gunung, menjauh dari deru ombak.
Konon, ibu melahirkanku di musim panas, di atas bukit rumput berduri. Matahari terbit di atas kepalaku, rumput berduri itu bergoyang tertiup angin. Hari itu, ayahku sedang memancing di laut yang jauh. Kemudian, dalam kisah-kisah yang membangkitkan kenangan, ia berkata bahwa itu adalah pelayaran laut paling gagal dalam hidupnya. Terkadang, aku meragukan hubungan antara kehadiranku dan pelayaran itu. Gelombang kenangan mencari lautan yang tak bisa kuberi nama. Aku menangis keras di atas rumpun rumput berduri. Tubuhku dipenuhi bunga rumput berduri. Apakah itu sebabnya kemudian, pikiranku juga tertutup duri? Ketika aku berhenti di suatu titik dalam hidupku, ketika aku menoleh ke belakang, aku melihat bahwa setiap orang yang menyentuhku berdarah.
***
Bibi pulang, sibuk dengan pekerjaan lamanya. Pagi hari ia memotong ikan untuk disewa, sore harinya ia kembali untuk membuat saus ikan. Ayah masih bekerja keras di laut.
Makanan saat bibiku pulang juga lebih layak, dengan sup bayam yang dimasak dengan udang dan ikan tenggiri rebus. Ayahku makan lebih banyak dari biasanya. Untuk pertama kalinya, aku melihat ayahku mengambil makanan untuk bibiku. Sejenak rasa damai muncul di hatiku. Melihat sikap ayahku terhadap bibiku, aku mengerti bahwa ia telah berusaha keras untuk berubah. Setelah makan, ayahku berdiri dan keluar untuk membalik keranjang ikan kering, dan suatu hari bibiku akan mengemasnya dan membawanya ke pasar untuk dijual dan dibeli daging segarnya. Hidangan lezat itu akan terus ada selamanya. Tiba-tiba aku tersadar dari lamunanku ketika bibiku bertanya, "Bagaimana menurutmu, T?". Saat itu, jejak langkah ayahku telah pergi sangat jauh.
"Aku masih sama, Bibi. Mungkin aku akan pergi ke kota untuk belajar suatu keahlian."
"Bagaimana dengan ayahmu?"
"Aku akan merasa lebih aman bersamamu di sini" - jawabku.
"Maksudmu, ayah ingin aku tinggal di laut."
"Aku tahu."
Dia terdiam.
Sore harinya, langit tampak luar biasa cerah. Aku ingat ayahku pernah berkata bahwa itu pertanda badai akan datang. Di kejauhan, bibi dan ayahku sedang memperbaiki jala mereka untuk menangkap ikan dan udang di hari yang berat. Perahu-perahu keranjang yang mengapung membawa nasib manusia. Di atas bukit pasir, kawanan sapi kuning menyeret padang rumput yang jauh, para pengembara menghabiskan hidup mereka mencari tanah baru, momen dalam hidup yang mencintai langkah kaki. Di malam hari, derit rangka tempat tidur terdengar karena dibalik pelan. Suara bambu, suara bambu memanggil kembali tidur.
"Badai nomor berapa ini, Bibi?"
Dia menggelengkan kepalanya dan berkata dia tidak ingat.
***
"Saya akan pergi ke kota untuk belajar menggambar."
Kataku kepada ayahku pada suatu pagi yang cerah.
Ayah tidak keberatan, tetapi matanya tampak sedih. Katanya, pilihlah kehidupan yang stabil, jangan hidup dalam kesengsaraan.
Setelah beberapa minggu, aku pulang ke rumah karena tak puas dengan guru seniku. Aku ingat berteriak bagai ombak yang mengamuk, kujatuhkan kanvas di depan puluhan mata saat guru meminta semua murid telanjang saat menggambar. Aku tak menunggu alasan yang meyakinkan untuk permintaan menyebalkan ini. Ia ingin membuat kami telanjang bak sekawanan ikan yang terdampar, berjuang mencari kebebasan. Ia mencengkeram kerah bajuku, hei makhluk tak bersirip, ambil kuasmu dan berenanglah ke dunia kami. Hei T, bukankah nenek moyangmu ikan? Ia meraung. Aku berlari keluar galeri, di belakangku berwajah-wajah manusia bertubuh ikan. Lele, mullet, croaker... begitu banyak nama yang aneh, ayahku pernah marah hanya karena aku tak bisa membedakannya.
Kekalahan ini bagaikan seember air dingin yang disiramkan ke wajahku.
Terkadang, kegagalan seseorang adalah kebahagiaan bagi orang lain. Kali ini, aku mengikuti keinginan ayahku dan belajar melaut. Setidaknya untuk saat ini, aku merasa itu pilihan yang aman, ketika aku teringat wajah guru seni itu. Ayahku tertawa terbahak-bahak dan berkata anak ini hebat. Bibiku pun tersenyum karena kebahagiaan ayahku. Dengan pengalamannya selama puluhan tahun di laut, ayahku yakin ia akan mengajariku menjadi berbakat. Aku memang belum berbakat, tetapi bencana sudah di depan mataku. Aku menyingkirkan tangan berat ayahku dari bahuku, "Tidak, aku tidak butuh kau mengajariku." Raut wajah ayahku berubah, "Apa maksudmu?" Kau ingin mencari guru, yang berarti kau tidak akan pulang. Ayahku berkata, "Baiklah, tidak apa-apa." Ia membiarkanku pergi, seperti sore hari ketika aku membiarkan bayanganku jatuh di laut.
Musim kuning bunga kosmos telah berlalu, tetapi aku masih menyimpan dalam hati ayahku segala kekhawatiran dan keprihatinanku.
Bibi saya menyiapkan makan malam perpisahan untuk saya saat saya memulai perjalanan untuk "mempelajari jalan sang guru". Hidangannya terdiri dari salad ikan dengan daun ara, sepiring daun ubi jalar rebus, dan anggur. Daun ubi jalar yang tidak musimnya terasa pahit di mulut saya.
"Aku berangkat besok, jangan khawatir, Ayah dan Bibi."
Selama aku pergi, rumah tetap tak berubah. Bantal-bantal masih di setiap tempat tidur, satu di setiap tempat tidur, tak bergeser. Kali ini aku tak bertanya, bibiku bilang badai telah mereda di daerah bertekanan rendah, dan akan ada hujan lebat. Ia menyuruhku tidur lebih awal. Aku menghela napas lega.
Besok aku pergi, ayahku akan mengikat atap agar terhindar dari angin. Bibiku berlari ke kebun untuk memetik labu dan waluh yang tersisa. Malam harinya, satu-satunya malam yang tersisa untuk kami berdua adalah malam permohonan, malam itu memberiku harapan untuk banyak hal. Sesungguhnya, tak ada gerombolan ikan yang berenang di sekitar setiap malam. Ayahku masih menghadap dinding, dan di sisi lain adalah bibiku. Di altar, ibuku tersenyum lembut bak peri.
***
Nama guruku Quy. Katanya, "Panggil saja aku Quy Tua, aku tidak mengajar siapa pun, kata 'guru' itu berat sekali." Ia melanjutkan, "Tapi hei, namaku Quy, tapi aku selalu berdiri tegak sepanjang hidupku, aku belum pernah berlutut di hadapan siapa pun." Quy Tua tinggal sendirian di gubuk beratap daun palem, rumahnya menghadap laut. Saat pertama kali bertemu dengannya, ia berkata, "Pulanglah." Aku menggeleng, tak mengerti. "Kau tidak cocok di laut, Nak," katanya. "Matamu tidak tajam, seumur hidupku aku hanya melihat ikan berlari, tapi aku tak bisa berhenti melihat manusia." Aku memohon padanya cukup lama sebelum ia mengangguk enggan. "Baiklah, tinggallah, aku senang ada yang menemaniku."
Pelajaran pertama yang ia ajarkan kepadaku bukanlah lautan. Ia berdiri, menyalakan kompor untuk memanaskan sepanci ikan gobi. Ia menaburkan merica dan bergumam, "Kasihan ikan gobi yang sedang jatuh cinta." Sesaat kemudian, ia keluar, memegang sebotol anggur di tangannya. Hujan semakin deras, langit gelap gulita. Tiba-tiba, angin berubah arah, melemparkan hujan ke udara, membuatnya mengulurkan tangan dan mengusap wajahnya, memperlihatkan mata yang termenung. Kali ini, ia terkekeh seolah tersedak. Melihatnya, aku tak tahu sudah berapa banyak malam yang ia habiskan sendirian, menyia-nyiakan hidupnya dengan kenangan-kenangan menyedihkan itu.
Malam itu suram dan berangin. Lelaki tua itu berkata bahwa setiap spesies memiliki suara, bahkan ikan sekalipun. Itulah pengalamannya di laut, yang telah ia kumpulkan selama bertahun-tahun. Kisahnya mengingatkan saya pada kisah paus paling kesepian di planet ini, seekor paus kesepian yang mati-matian mencari jenisnya sendiri.
"Manusia punya banyak suara, jadi hati mereka juga muram," ia menggosok-gosok tangannya agar tetap hangat, suaranya serak. Berbaring di tengah ombak besar di malam hari, bersama Quy tua, kuda liar di dalam diriku semakin membesar. Besok, aku akan pergi ke laut lagi bersama Quy tua, memikul jaring di bahuku untuk menenun harapan-harapan yang jauh. Ketika bayangannya menghilang, aku akan mengikuti jejak kakinya di pasir. Dan ketika aku sampai di laut, aku akan mulai memanggil namanya, karena laut tak punya jejak kaki.
Bertemu dengannya, aku bagaikan burung badai yang beristirahat di atas batu untuk penerbangan panjang. Suatu malam jauh dari rumah, aku bermimpi seorang Malaikat melahirkan bayi untuk bibiku, dan melihat ayahku tersenyum.
Kuda liar di dalam diriku berlari kencang, berlari sendirian melintasi padang rumput yang luas. Dan di belakangku, rerumputan berduri mulai tumbuh, tanpa jejak kaki sedikit pun.
Source: https://thanhnien.vn/chiem-bao-bien-truyen-ngan-du-thi-cua-le-van-than-18525110816005123.htm



![[Foto] Perdana Menteri Pham Minh Chinh bertemu dengan perwakilan guru berprestasi](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/1200x675/vietnam/resource/IMAGE/2025/11/15/1763215934276_dsc-0578-jpg.webp)
![[Foto] Sekretaris Jenderal To Lam menerima Wakil Presiden Luxshare-ICT Group (Tiongkok)](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/1200x675/vietnam/resource/IMAGE/2025/11/15/1763211137119_a1-bnd-7809-8939-jpg.webp)


![[Foto] Panorama Putaran Final Penghargaan Aksi Komunitas 2025](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/1200x675/vietnam/resource/IMAGE/2025/11/15/1763206932975_chi-7868-jpg.webp)


























































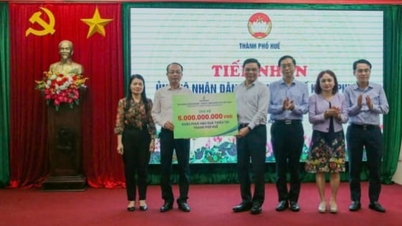






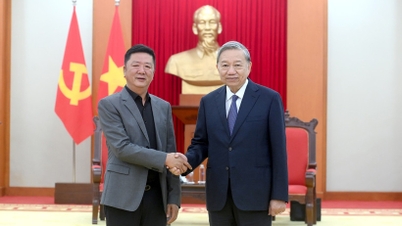



































Komentar (0)