Alun-alun itu luas, dengan deretan pohon pinang besar yang tumbuh di sepanjang perbatasan, cabang dan daunnya seperti sisir raksasa, berdesir diterpa hujan. Aku duduk di tempat yang familier. Sejak tiba di kota ini, setiap kali aku bermain dengan Phuc, Hung, dan Tien, rasanya sangat menyenangkan. Kami melukis patung, bermain foosball, makan tusuk sate, minum air tebu... tertawa dan bercanda. Tapi malam ini, hanya aku dan hujan yang menyilaukan. Kesepian. Alun-alun itu berjarak dua kilometer dari rumahku, tetapi aku merasa seperti berada di dunia yang jauh, dunia yang hanya berisi aku, hujan, dan angin.
Bu, aku kedinginan! Bagaimana mungkin angin dan hujan mendengar suaraku? Ke mana aku harus pergi sekarang, ke mana aku harus kembali? Adakah tempat di dunia ini yang lebih mencintaiku daripada tempat itu? Di mana ibuku dan... lelaki itu—ibu yang berkali-kali berjingkat menyarankan agar aku memanggilnya "ayah" alih-alih "paman". Oh, aku rindu merasakan hangatnya berbaring di kamarku yang sempit, dengan pamanku menjatuhkan kelambu dan mengomel: "Simpan ponselmu dan tidurlah lebih awal, kamu harus sekolah besok pagi!"—suara yang dingin namun anehnya hangat. Mengapa aku baru menyadari perasaan hening dan mendalam itu sekarang? Dasar bodoh. Kau pantas mendapatkannya! Aku duduk diam di bangku batu yang dingin, membiarkan hujan mengguyur kepalaku, leherku, membuat seluruh tubuhku mati rasa seperti burung kecil yang membeku, sebagai hukuman...

ILUSTRASI: AI
2. Terus terulang seperti itu sepanjang perjalanan masa kecilku dengan hari-hari sepulang sekolah yang membuatku ingin menangis. Aku malu untuk bercerita pada teman-temanku karena mereka punya hobi bercerita bagaimana ayah mereka mengajak mereka bermain ke sana kemari, membeli mobil-mobilan, robot-robotan... dan segala macam. Dan kalau saja itu saja, parahnya, mereka dengan polosnya akan berkata lantang bahwa ketika mereka di jalan, mereka melihat ayah mengajak ibu tiriku dan adik-adik An makan sate bakar, es krim, dan membeli balon superhero, buaya segala jenis. Aku tidak tahu apakah teman-temanku itu naif atau memang sengaja begitu ketika mereka dengan antusias bercerita seolah-olah aku benar-benar ingin mendengar cerita-cerita memilukan itu. Sungguh mengerikan, tidak ada yang tahu bahwa aku sedang sedih setengah mati atau setidaknya hanya ingin berlari entah ke mana dan menangis sejadi-jadinya.
Aku harus berusaha untuk tidak menunjukkan kesedihanku setiap kali pulang karena aku takut ibuku akan sedih. Aku tak pernah memberitahunya bahwa aku terus menghibur diri bahwa ayahku akan pergi ke suatu tempat dan kembali tanpa meninggalkanku. Rumahku bersebelahan dengan rumah kakek-nenek dari pihak ayah, ayahku sering ke sana, setiap kali ia pulang aku akan berlari untuk menemuinya, berbicara dengannya, dan mencari perhatian, tetapi ia selalu kembali pada seorang wanita bernama Tho dan dua anak dari pria lain, tetapi ia dengan alami memanggilnya "ayah" dengan manis di hadapanku - seolah-olah aku hanyalah setitik debu yang tak berakal. Ibuku bahkan tak repot-repot menyebut-nyebut tentang wanita cengeng yang meninggalkannya dalam trauma hampir mati.
Setelah percobaan bunuh diri yang gagal—karena teriakanku yang keras ketika ibuku menutup pintu untuk melukai dirinya sendiri—ibu itu pun terjun langsung mencari nafkah untuk membesarkan putra tunggalnya karena ia tidak dapat melahirkan seperti perempuan lain setelah kecelakaan yang disebabkan oleh ayahku dan kemudian harus pergi. Meskipun ia kembali bekerja, setelah kembali dari ambang kematian, setiap bulan ibuku harus berjuang melawan pingsan selama seminggu, sehingga aku harus menyembunyikan semua perasaanku, hanya menangis diam-diam ketika mandi, selebihnya selalu ceria seperti "pemuda kuat" yang sering dipanggil ibuku dengan penuh kasih sayang.
Sebenarnya, Ibu saya, meskipun pengertian, tidak mengatakan apa-apa, tetapi sangat memahami bahwa saya tidak bisa hidup tanpa kasih sayang seorang ayah. Jadi, beliau mengambil risiko lain - mencarikan seorang ayah untuk saya. Mungkin terdengar konyol, tetapi itu akan menjadi hal terbaik yang bisa beliau lakukan saat ini untuk menyembuhkan luka yang ditinggalkan oleh ayah saya yang mengerikan.
Ini kisah yang sulit. Nenek saya bilang, "Beda darah, beda hati." Saya ingat tahun itu, ketika saya kelas 5 SD, pertama kalinya rumah saya kedatangan tamu laki-laki. Dia hampir 20 tahun lebih tua dari ayah saya, jadi saya memanggilnya "paman". Wajahnya bak dewa laki-laki, penyayang, suka mengobrol, dan sering membelikan saya mainan, terutama saat kami makan bersama. Dia selalu menyimpan bagian terbaik untuk saya. Dia tidak memperlakukan saya seperti "anak malang" seperti orang dewasa lainnya. Saya sangat menyukai itu karena tidak ada yang mau dikasihani, itu memalukan. Lambat laun, saya mulai bersimpati padanya—seorang pria yang saya yakini akan membuat anak mana pun merasa terhormat jika dekat dengannya.
Sebenarnya, awalnya aku khawatir cinta sejatiku akan direnggut, jadi aku bingung dan linglung. Namun suatu malam, aku tiba-tiba merasa pusing, pucat, muntah, dan diare. Saat itu pukul 22.30, tetapi pamanku masih menempuh jarak 40 km untuk menemaniku dan ibuku. Ketika mobil berhenti di gerbang rumah sakit, pamanku menggendongku. Meskipun aku kelelahan, aku merasa ditopang oleh bahunya yang kuat dan aman. Saat itu, aku berharap punggung sekuat tembok ini milik ayahku.
***
Tahun itu ketika saya duduk di kelas 7, paman saya menjemput saya dan membawa saya kembali ke kota bersamanya.
Ketika kami tinggal bersama, saya masih bersikeras memanggilnya "paman". Sebenarnya, hambatan terbesar dari jarak "paman" - "ayah" adalah suasana hati saya yang tidak sebaik yang saya bayangkan. Ketika semua orang tinggal terpisah, paman saya mondar-mandir, mengurus saya dan membuat saya berharap, tetapi ketika kami tinggal bersama, saya membatasi diri karena takut. Paman saya sangat tegas, teliti dalam berbicara dan bekerja, jadi dia juga ingin mengajari anak-anaknya untuk teliti dengan caranya sendiri. Saya mulai merasa tertekan dengan aturan "belajar makan, belajar berbicara, belajar membungkus, belajar membuka". Gila, semuanya harus dipelajari. Paman saya mengancam, jika saya tidak belajar sekarang, saya pasti akan membayar harganya nanti. Apa yang dibutuhkan nanti, sekarang anak saya sudah "membayar harganya" karena kerinduannya akan seorang ayah. Hanya dengan mengucapkan kalimat tanpa subjek, saya akan diingatkan dengan lembut oleh paman saya.
Parahnya lagi, sejak kecil, Ibu begitu memanjakanku hingga aku punya kebiasaan yang sangat naluriah, seperti memegang sumpit tegak seperti orang lain, lalu lebih suka makan camilan daripada nasi, menonton TV tanpa henti, dan... Alhasil, setiap kali makan, Bibi selalu membantuku memegang sumpit dengan lebih rapi dan menjelaskan tentang budaya makan sambil duduk. Ia dengan sabar menunggu sampai aku baik-baik saja. Oh, aku berani bertaruh pada dunia bahwa tidak ada anak yang mau mendengarkan ceramah moral yang panjang. Jika aku tidak melawan, mungkin karena aku kalah atau tidak punya kemampuan itu—aku menebaknya begitu dan merasa sangat tidak puas.
Sering kali ketika saya sedang marah dan impulsif, saya mengucapkan kata-kata kasar. Melihat tatapan matanya, saya tahu dia sedih, tetapi saat itu dia hanya diam saja melakukan sesuatu tanpa berkata apa-apa. Ada kalanya dia tidak bisa mengendalikan emosinya, dia marah dan meninggikan suaranya, tetapi dia tidak berbicara kasar atau memukul pantatnya. Sebaliknya, dia akan sangat lembut dalam mengajari saya, dia menyatakan bahwa dia akan berlomba dengan saya untuk melihat siapa yang akan menyerah lebih dulu. Sering kali seperti itu, saya memahami hatinya yang luas.
Seperti suatu kali aku tak sengaja terjatuh dan patah tanganku saat bermain di sekolah, saat aku pulang sekolah di bawah terik matahari, pamanku berlari ke pintu untuk menyambutku, melihat tanganku tergantung, ia terdiam dan pucat. Ibuku pergi bekerja jauh, pamanku tak memberitahuku, hanya diam membawaku ke rumah sakit untuk diperban dan di hari-hari berikutnya, aku tak perlu menceritakan perawatan seperti apa yang kuterima. Aku tak ingin membandingkan tapi kebenaran tak bisa disembunyikan, pamanku mencintai dan menyayangiku bermiliar-miliar kali lipat lebih dari ayah yang ada di kertas A4. Bagaimana aku bisa lupa saat ayahku baru saja pergi, aku digigit anjing dan kulitku berdarah, aku tak sabar untuk divaksin tapi ia hanya memberiku sekotak Milo dan itu adalah akhir dari tugasnya. Tapi aku berharap aku digigit anjing lagi agar ayahku mencintaiku.
***
Tahun itu, selama pandemi Covid-19, siswa tidak bisa bersekolah dan terpaksa belajar daring. Ibu memberi saya laptop tua. Saking tuanya, gambar dan materi kuliah tidak bisa dipadukan. Paman saya diam-diam memantau setiap kelas saya. Menyadari masalah ini, ia bekerja keras sepanjang sore untuk memperbaikinya. Ibu saya menyuruh saya makan malam karena sudah waktunya makan malam. Tanpa henti, paman saya langsung memarahi ibu saya: "Perbaiki komputer tepat waktu untuk kelas besok, ngapain masak?"
Mesinnya bagus, tapi saya belajar untuk mengatasinya. Hasilnya memang pantas, dari siswa yang baik menjadi siswa yang biasa-biasa saja. Saya membuat paman saya marah. Dia memutuskan untuk menjadi "tutor" saya untuk menyelamatkan situasi. Sial, saya belum pernah setakut ini dengan kata-kata dan angka seperti saat itu. Harus duduk dan mendengarkan kuliah, menggaruk-garuk kepala dan menjambak rambut dengan latihan yang membuat saya ingin menghirup oksigen, saya tak tahan. Saya berpikir cepat. Jadi saya menunggu sampai paman dan ibu saya tidur siang, lalu "melarikan diri".
Bersepeda di jalan raya, melawan angin. Tak ada yang bisa membayangkan anak kelas 7 bersepeda lebih dari 40 km di tengah hujan untuk pulang ke rumah kakek-neneknya. Memikirkan omelan seperti: belajar seperti ini akan membuatku mengemis di jalanan nanti, mulai sekarang, ponselku akan disita, aku hanya akan menggunakan komputer ibuku jika harus belajar daring, mengurangi uang jajan, tidak mengizinkanku bergaul dengan teman-teman lagi... untuk mendapatkan lebih banyak kekuatan, aku harus melepaskan diri dari keketatan itu, terlalu menekan.
Aku tak perlu siapa pun menceritakan betapa gelisahnya Ibu dan Paman saat itu, mereka pasti pingsan berulang kali. Malam itu, aku dengan yakin menyarankan untuk tinggal bersama Nenek, tetapi anak panah itu meleset...
3. Ayah kandungkulah yang mengantarku pulang. Duduk di pelana kecil yang sama, aku merasa jarak antara aku dan beliau begitu jauh.
Mobil melaju ke belokan, mungkin karena takut berhadapan dengan ibu dan pamanku (karena ia tidak pernah memberiku uang tunjangan anak seribu dolar sejak aku kecil), ayahku meninggalkanku di jalan untuk masuk sendiri. "Aku sedang terburu-buru," katanya tanpa penyesalan dan tidak punya waktu atau tidak ingin melihat wajahku yang sedih. Aku berdiri ragu-ragu, tiba-tiba hujan turun, aku menarik tudung mantelku untuk menutupi kepalaku. Aku melangkahkan kakiku ke depan, entah kenapa terasa kaku. Aku mengerti, kakiku juga merasa malu. Bagaimana mungkin aku berani masuk ke dalam rumah. Jika pamanku hanya menamparku atau mencambukku untuk menghukumku, tetapi aku tahu itu hanya akan menjadi keheningan. Aku tak punya cukup keberanian untuk menghadapi tatapan itu.
Aku berjalan tertatih-tatih menuju alun-alun di tengah hujan. Saat berjalan, aku melihat Phuc digendong ibunya, tapi aku menutupi kepalaku agar kau mungkin tak mengenalinya. Tekanan udaranya rendah, tak heran alun-alun itu sepi. Aku pergi ke beranda panggung alun-alun dan meringkuk di bangku batu. Mantel saja tak cukup untuk menghangatkanku saat angin bertiup kencang. Saat ini, aku tak punya kekuatan untuk memikirkan hal baik. Aku akan berbaring di sini dan menangis sampai mati. Besok pagi, ketika hujan reda, orang-orang yang berolahraga akan melihat seorang anak malang yang meninggal bukan karena hujan yang dingin, melainkan karena kurangnya kasih sayang dari ayahnya. Dengan pikiran seperti itu, aku tak lagi takut dan menangis lebih keras daripada hujan...
Tepat saat itu, lampu mobil menerpa wajahku, ibuku bergegas menghampiri, dan pamanku dari jauh bertanya apakah aku baik-baik saja, lalu melepas mantelnya dan memakaikannya padaku, menyuruhku masuk ke mobil dan pulang, udaranya dingin. Aku tak ingin masuk ke mobil, aku berdiri diam, kedua tanganku yang kecil menggenggam erat lengan pamanku yang kuat, tiba-tiba aku terisak: "Ayah, maafkan aku...". Sesampainya di rumah, badai tiba-tiba semakin kuat. Biarlah hujan dan angin terus berlanjut. Aku menerimanya. Karena aku percaya bahwa meskipun langit runtuh, akan tetap ada tangan raksasa yang melindungiku. "Hidup Ayah!", bisikku di telinga ibuku, tersenyum, dan tertidur...

Sumber: https://thanhnien.vn/bo-oi-truyen-ngan-du-thi-cua-bao-kha-185251025081547288.htm



![[Foto] Komite Partai di Badan Pusat Partai merangkum pelaksanaan Resolusi No. 18-NQ/TW dan arahan Kongres Partai](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/1200x675/vietnam/resource/IMAGE/2025/10/27/1761545645968_ndo_br_1-jpg.webp)
![[Foto] Kongres Emulasi Patriotik ke-5 Komisi Inspeksi Pusat](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/1200x675/vietnam/resource/IMAGE/2025/10/27/1761566862838_ndo_br_1-1858-jpg.webp)


![[Foto] Ketua Majelis Nasional Tran Thanh Man menerima Ketua DPR Uzbekistan Nuriddin Ismoilov](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/1200x675/vietnam/resource/IMAGE/2025/10/27/1761542647910_bnd-2610-jpg.webp)












































































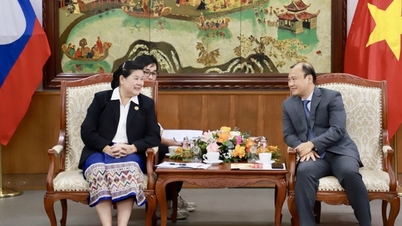



























Komentar (0)