Para pengamat memiliki pendapat yang berbeda mengenai kesepakatan antara AS dan China terkait penerapan kecerdasan buatan (AI) di bidang militer .
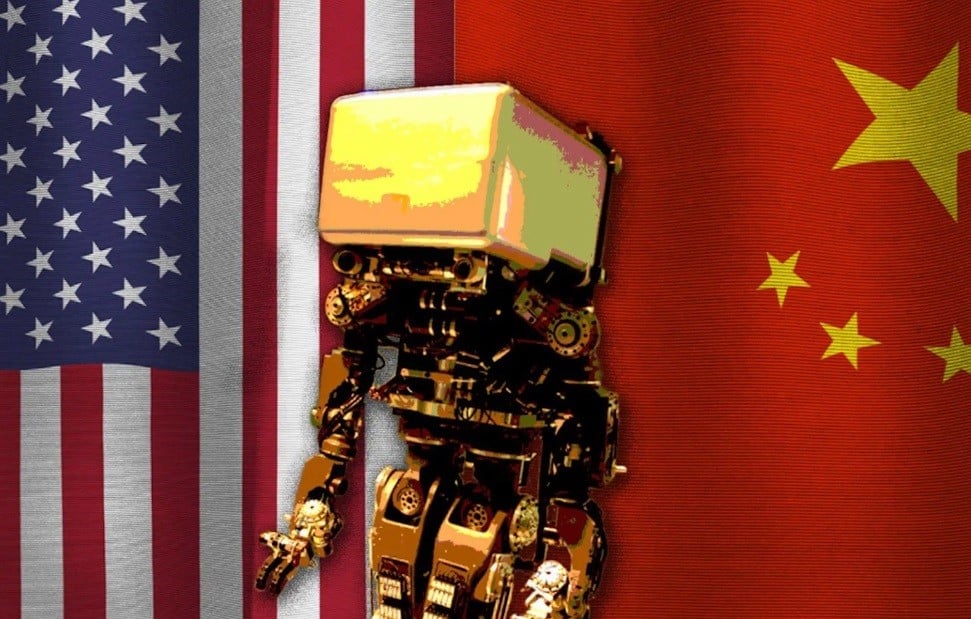 |
| Para pengamat memiliki pendapat yang berbeda mengenai kesepakatan antara AS dan China terkait penerapan kecerdasan buatan (AI) di bidang militer. (Sumber: Asia Times) |
Menyusul pertemuan antara Presiden AS Joe Biden dan Presiden Tiongkok Xi Jinping pada tanggal 16 November (waktu Vietnam) di sela-sela Konferensi Tingkat Tinggi Kerja Sama Ekonomi Asia-Pasifik (APEC) 2023 di San Francisco, California, kedua negara mencapai beberapa hasil penting, termasuk menyepakati untuk melanjutkan kontak militer, bekerja sama dalam memerangi perdagangan narkoba (terutama fentanyl), dan membahas risiko serta langkah-langkah untuk mengelola keamanan kecerdasan buatan (AI).
Dalam konferensi pers setelah KTT AS-Tiongkok, Presiden AS Joe Biden menyatakan: “Kami akan mengumpulkan para ahli untuk membahas risiko dan masalah keamanan yang terkait dengan penerapan kecerdasan buatan. Ketika saya bekerja dengan para pemimpin dunia , mereka semua mengangkat isu dampak kecerdasan buatan. Ini adalah langkah konkret ke arah yang benar untuk menentukan apa yang diperlukan, tingkat bahayanya, dan apa yang dapat diterima.”
Pemerintahan Biden baru-baru ini mengeluarkan perintah eksekutif pertamanya tentang kecerdasan buatan dan sangat mempromosikan standar global untuk penggunaan AI di bidang militer. China juga menunjukkan tanda-tanda kesediaan untuk membahas masalah ini, khususnya mengenai larangan penggunaan AI dalam sistem komando dan kendali (C2) senjata nuklirnya.
Meskipun Presiden Biden dan pengumuman Gedung Putih tidak secara eksplisit menyebutkan hubungan antara AI dan senjata nuklir, para ahli meyakini bahwa ini adalah topik utama diskusi antara AS dan China sebelum pertemuan tersebut.
Bonnie Glaser, yang mengepalai program Indo-Pasifik di German Marshall Fund, berkomentar: "China tertarik untuk berpartisipasi dalam diskusi untuk menetapkan aturan dan standar untuk AI, dan kita harus menyambut hal itu."
Ini bukan hanya masalah bagi AS dan Tiongkok.
Setelah SCMP , mengutip sumber anonim, melaporkan bahwa "Presiden AS Joe Biden dan Presiden Tiongkok Xi Jinping siap berkomitmen untuk melarang penggunaan AI dalam sistem senjata otonom, termasuk penggunaannya dalam mengendalikan drone (UAV) dan mengendalikan serta mengerahkan hulu ledak nuklir," opini publik meningkatkan harapan akan pernyataan bersama antara AS dan Tiongkok mengenai masalah ini.
Namun, tidak ada indikasi bahwa China atau AS akan menerima pembatasan yang mengikat terhadap kebebasan bertindak mereka di bidang AI.
Ini bukan hanya masalah bagi AS dan Tiongkok. Sejak Februari 2023, setelah AS mengeluarkan "Pernyataan Kebijakan tentang Penggunaan Kecerdasan Buatan yang Bertanggung Jawab untuk Militer," mereka telah berkampanye untuk membangun konsensus global tentang pengembangan dan penggunaan AI militer, yang berlaku tidak hanya untuk senjata otonom seperti UAV tetapi juga untuk aplikasi yang menggunakan algoritma untuk analisis intelijen atau perangkat lunak logistik.
Tujuan AS adalah untuk melawan seruan dari banyak aktivis perdamaian dan negara-negara non-blok untuk larangan yang mengikat terhadap "robot pembunuh," sehingga menciptakan peluang bagi AS dan sekutunya untuk menggunakan AI secara "bertanggung jawab," sebuah teknologi yang berkembang pesat dengan berbagai aplikasi.
Pada bulan Februari 2023, Pentagon juga melakukan perombakan besar-besaran terhadap kebijakannya mengenai AI militer dan sistem otonom. Setelah itu, Duta Besar Bonnie Denise Jenkins, Wakil Menteri Luar Negeri untuk Pengendalian Senjata dan Keamanan Internasional, merilis "Pernyataan Politik tentang Penggunaan Kecerdasan Buatan dan Otonomi yang Bertanggung Jawab di Militer" pada KTT Kecerdasan Buatan yang Bertanggung Jawab di Militer (REAIM) di Den Haag pada Februari 2023.
Tujuan dari Pernyataan ini adalah untuk menguraikan pendekatan AS, yaitu untuk mendapatkan konsensus internasional, sehingga militer dapat secara bertanggung jawab mengintegrasikan AI dan otonomi ke dalam operasi militer.
Sejak saat itu, banyak negara lain telah menyuarakan dukungan mereka untuk AS, termasuk sekutu utama seperti Australia, Inggris, Prancis, Jerman, dan Korea Selatan, serta negara-negara seperti Hongaria, Libya, dan Turki. Pada tanggal 14 November, kantor berita Yonhap melaporkan bahwa AS dan 45 negara lainnya mengeluarkan pernyataan bersama yang menyoroti penggunaan AI yang "bertanggung jawab" di bidang militer.
Beberapa pendapat yang saling bertentangan muncul setelah pertemuan antara kedua pemimpin tersebut, termasuk penilaian terhadap kesepakatan AS-Tiongkok mengenai penerapan kecerdasan buatan di bidang militer. Sementara sebagian berpendapat bahwa hal itu diperlukan, sebagian lainnya percaya bahwa Washington melepaskan keunggulannya. Christopher Alexander, Direktur Analisis di Pioneer Development Group, mempertanyakan perlunya kesepakatan ini, dengan menunjukkan bahwa AS akan melepaskan keunggulan strategisnya saat ini.
"Ini adalah keputusan yang buruk. China tertinggal di belakang AS dalam teknologi kecerdasan buatan. Oleh karena itu, melanjutkan kesepakatan ini berarti pemerintahan Biden melepaskan keunggulan strategisnya," kata Alexander.
Komentator Samuel Mangold-Lenett juga mempertanyakan apakah China akan menghormati perjanjian tersebut, dengan menunjuk pada kurangnya kepatuhan China terhadap Perjanjian Iklim Paris. Sementara itu, Phil Siegel, pendiri CAPTRS Center, berpendapat bahwa perjanjian semacam itu diperlukan, meskipun ia mencatat bahwa kekuatan besar seperti Rusia juga harus dilibatkan.
Apa yang diinginkan Beijing?
Tidak mengherankan, China belum menerima pendekatan AS. Pakar Tong Zhao menyatakan, “Strategi diplomatik negara itu tetap berfokus pada persaingan dan penyeimbangan upaya AS untuk menetapkan standar tata kelola AI di masa depan, khususnya di sektor militer.”
Lebih lanjut, menurut pakar ini, dalam mengelola teknologi militer baru, China sering menentang dukungan terhadap praktik-praktik yang "bertanggung jawab", dengan alasan bahwa ini adalah "konsep politik yang kurang jelas dan objektif."
Catherine Connolly, seorang peneliti di Stop Killer Robots, sebuah organisasi internasional yang menyatukan LSM yang berupaya melarang senjata otonom yang mematikan, mengatakan: “Jelas, kami mengharapkan AS untuk bergerak menuju dukungan yang jelas dan kuat untuk menetapkan kerangka hukum guna membatasi sistem senjata otonom. Kami pikir panduan dan pernyataan politik saja tidak cukup, dan sebagian besar negara juga tidak.”
Baru-baru ini, Kelompok Pakar Pemerintah Terkemuka (GGE) tentang senjata otomatis telah berulang kali mengadakan diskusi di Jenewa mengenai isu-isu terkait, dengan tujuan untuk mengusulkan pengembangan dan implementasi undang-undang tentang jenis senjata ini, serupa dengan yang sebelumnya diterapkan pada senjata kimia. Namun, hingga saat ini, upaya-upaya ini belum berhasil karena kurangnya konsensus di antara negara-negara peserta.
Oleh karena itu, gerakan anti-senjata AI mengusulkan rancangan resolusi kepada Majelis Umum PBB di New York. Alih-alih menyerukan pelarangan segera—yang hampir pasti akan gagal—resolusi yang diusulkan oleh Austria ini hanya "meminta Sekretaris Jenderal PBB untuk meminta pandangan negara-negara anggota."
Akibatnya, pada tanggal 1 November 2023, Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa mengadopsi Resolusi L.56, resolusi pertama tentang senjata otonom, yang menekankan “kebutuhan mendesak komunitas internasional untuk mengatasi tantangan dan kekhawatiran yang ditimbulkan oleh sistem senjata otonom.” Dunia usaha, peneliti akademis, dan organisasi non-pemerintah menyerahkan laporan dan secara resmi memasukkan isu tersebut ke dalam agenda PBB.
Resolusi L.56 disahkan dengan 164 suara mendukung, 5 menentang, dan 8 abstain. China adalah satu-satunya negara yang abstain.
Peneliti Catherine Connolly percaya bahwa fakta bahwa AS dan sebagian besar negara lain memberikan suara mendukung adalah pertanda positif, tetapi sangat disayangkan bahwa China abstain.
Namun, terkait Resolusi ini, ada beberapa aspek yang tidak disetujui China mengenai karakteristik dan definisinya. Faktanya, Beijing cenderung menggunakan definisi tunggal dan sempit tentang "senjata otonom," yang hanya mempertimbangkan sistem yang, setelah dikerahkan, "tidak diawasi dan tidak dapat dihentikan." Hal ini menyebabkan China mengklaim dukungan terhadap larangan tersebut, sementara pada kenyataannya hal itu mengecualikan sebagian besar sistem otonom yang saat ini sedang diteliti dan dikembangkan oleh militer banyak negara.
Pakar James Lewis berpendapat bahwa meskipun resolusi Majelis Umum PBB tidak mengikat, jika AS dapat melibatkan negara-negara lain seperti Inggris, Prancis, dan mungkin Uni Eropa dalam upaya komprehensif, kemajuan dapat dicapai dalam menetapkan aturan di bidang ini.
Sampai saat ini, diskusi internasional mengenai "deklarasi politik" yang tidak mengikat justru memaksa Washington untuk mengurangi ambisinya dengan menghapus bagian yang berkaitan dengan pemberian kemampuan kepada AI untuk mengendalikan senjata nuklir.
Sumber











































































































Komentar (0)