Beberapa kumpulan puisi karya jurnalis Nguyen Tien Dat - Foto: NK
Banyak orang mengenal penyair dan jurnalis Nguyen Tien Dat karena sebelum meninggalkan "dunia sementara" ini, ia telah meninggalkan "warisan" puisi, cerpen, dan karya jurnalistik yang cukup lengkap. Sedangkan saya, sejak mahasiswa sastra, di sore hari di Hue , saya sering pergi ke toko buku dekat Jembatan Trang Tien, di tepi Sungai Perfume, untuk membaca puisi-puisinya yang terbit di majalah bulanan Today's Knowledge: "Sayang, kembalilah ke sungai/Sungai itu memiliki mata jernih yang melamun/Akulah nelayan tua/Biarkan senja terbit di keluasan..." (Berbicara dengan mantan kekasih).
Lalu, saat-saat berikutnya saya pulang, saya sering bertemu keluarganya di feri Mai Xa yang bolak-balik ke Dong Ha karena rumahnya dan rumah saya hanya berjarak sebidang tanah. Setelah lulus, saya bertemu lagi dengannya di "rumah kos" Koran Quang Tri . Alasan mengapa Dat mencintai dan menghormati saya adalah karena kami memiliki seorang ibu tua di pedesaan yang selalu kami nanti-nantikan untuk kembali.
Oleh karena itu, di sepanjang puisinya, Dat bercerita tentang pedesaan miskin Lam Xuan, tempat tinggal seorang ibu tua dan beberapa gadis desa: "Kami lahir di tepi sungai, di tepi sungai/ Meringkuk di tubuhmu mencari udang dan udang" (Sungai Kehidupan); "Pedesaan yang malang! Ya, Ibu/ Hatiku dipenuhi kerinduan" (Gio Linh) dan ia selalu mengakui: "Meskipun aku mencintai mawar, mencium bunga violet/ Membaca puisi Pushkin dan menggenggam tangan para wanita cantik/ Aku tetaplah mugic desaku/ Di mana bulir padi musim dingin membentangkan sayap matahari" (Mugic). Karena di pedesaan itulah Dat selalu menemukan ibu dan saudara perempuannya: "Kupikir air matamu/ Adalah tetesan embun dari langit/ Aku seperti jangkrik/ Selalu haus akan embun" (Sepuluh Tahun)
Ketika bercerita tentang ibu saya yang sudah tua, saya dan saudara laki-laki saya sering membahas tentang pengorbanan. Ia berkata, "Ketika saya kuliah di Hue, setiap kali ibu melihat saya pulang setelah siang, ia akan bergegas keluar untuk merias wajah, memandangi wajah saya yang gemuk dan kurus, lalu membawa sedotan untuk memotong kayu poplar, membelahnya menjadi 5 atau 7 bagian untuk dijemur, dan membawanya ke Pasar Hom untuk dijual agar saya bisa pulang. Biasanya, saya pulang selama beberapa hari, tetapi suatu kali saya harus pulang lebih awal untuk ujian. Kayu poplar belum kering, dan saya tidak bisa menghasilkan uang. Ibu memberi saya sekantong beras, mendorong saya keluar pintu, dan menoleh ke belakang, air matanya mengalir deras."
Saya bilang padanya, "Ibu saya berjualan es teh. Kadang-kadang dia harus begadang sampai jam 1-2 pagi menunggu anak-anak desa yang sedang menggoda perempuan datang dan menghabiskan semua tehnya. Karena kalau dia tidak menjual semua air gula dan kacang-kacangan, dia bisa memberi makan anak-anaknya besok, tapi kalau air esnya mencair, dia akan rugi besok. Kadang-kadang saya bangun pagi dan melihat mata ibu saya merah dan bengkak." Saya dan adik saya saling berpandangan dan berseru, "Astaga, susah sekali!"
Pemandangan Desa Gio Mai - Foto: TL
Soal kesulitan dan kesederhanaan, Dat dan saya punya banyak kesamaan. Meskipun dia jurnalis ternama, dia tetap mempertahankan kepribadiannya yang jujur dan sederhana, terutama kegemarannya minum di atas tikar bambu di sudut beranda saya. Saya ingat waktu saya sedang membangun rumah, setiap sore dia datang, memarkir sepedanya di luar gerbang, merokok Jet, dan berbisik kepada saya: "Coba bangun beranda yang lebar supaya kamu punya tempat minum. Usahakan agar terlihat menarik di mata semua orang, kalau kamu butuh uang, saya akan pinjami kamu."
Saya menuruti keinginannya untuk punya teras yang cukup luas untuk menggelar tikar persegi untuk 4 orang. Karena utang yang menumpuk, saya beberapa kali pinjam uang, dan dia garuk-garuk kepala. Damai sekali! Namun suatu sore, dia bergegas pulang, wajahnya berseri-seri.
"Aku punya uangnya, kamu dan istrimu bisa datang ke sini malam ini untuk mengambilnya." Ternyata dia baru saja memenangkan penghargaan jurnalisme dan menghasilkan beberapa juta dong, yang dia pinjamkan kepada istrinya untuk membangun rumah. Dia selalu jujur, tipe pria yang selalu menganggap remeh uang.
“Kamu pulang jual tikar gon/Tikar gon sudah selesai ditenun untuk Tet/Aku tak ambil sepeser pun/Di musim dingin aku duduk menyalakan api” (Berbicara dengan mantan kekasihku). Adakah sosok lelaki yang lebih rupawan, adakah istri yang lebih bahagia daripada “memiliki” suami yang penyayang, pekerja keras, dan tenang menjalani hidup. Dengan memandang remeh uang dan menghindari hiruk pikuk kehidupan sehari-hari, Dat selalu yakin bahwa: “Selama masih ada gaji dan royalti, aku tetap benci utang/Chi chi akan hidup sampai rambutnya memutih” (Mengingatkan diri sendiri). Dan ia selalu tertawa bangga: “Chi chi juga manusia/Uang, uang, dan dunia berebut tempat/Makanan, pakaian, ketenaran, dan kekayaan/Dari atas ke bawah, lelaki ini tetaplah sama” (Tertawa bangga di usia tiga puluh).
Dulu, tikar persegi dan sudut beranda rumahku menjadi "tempat asyik" yang sering dikunjungi Dat setiap hari. Lambat laun, aku terbiasa, dan jika ia tak pulang sore harinya, aku merasa hampa. Tak ada makanan lezat, hanya setoples penuh anggur obat yang dituang ke dalam botol, dan beberapa ikan kering sebagai umpan. Terkadang, saat terdesak, ia akan memetik mangga hijau dari kebun tetangga dan mencelupkannya ke dalam garam. Ia tak rewel asalkan ada "taman bermain" untuk duduk dan bergosip. Harus kuakui ia memang punya bakat mengarang cerita yang membuat kami percaya, tetapi sayang, itu terjadi saat ia "bercerita sambil minum anggur" dan bukan penduduk desa Lam Xuan yang menceritakannya. Berkali-kali kebohongannya terbongkar, Dat terpaksa tertawa dan mengakui bahwa itu hanya untuk menghibur kami.
Namun takdir telah mengaturnya, rumahku yang berbentuk persegi tak mampu menampungnya. Saat itu, ia berkata: "Kali ini, aku juga akan memperluas beranda, menambahkan beberapa batu bata lagi agar lebih terang agar orang-orang bisa datang dan minum anggur." Ia melakukannya dan aku pun pergi melihatnya, tetapi sayang, sebelum aku sempat minum anggur bersamanya di rumah persegi itu, sebuah kecelakaan tak terduga menariknya kembali ke ladang Lam Xuan. Ketika aku membawanya keluar, ibunya pingsan, aku berhasil membantunya berdiri, dan membantunya mengikuti rasa sakit yang menyayat hati. "Apa yang bisa kulakukan, apa yang bisa kulakukan secara berbeda/Apa yang bisa kuharapkan! Beri ibuku sedikit ketenangan pikiran/Tiba-tiba sore ini, berdiri sendirian di tepi sungai/Berbalik ke kampung halamanku, memanggil feri yang sepi/Terkejut—ibuku—di hadapan langit dan awan..." (Sungai Kehidupan Ibu).
Puisi-puisi tersebut merupakan caranya untuk meminta maaf kepada orang tuanya karena tidak memenuhi kewajiban berbakti kepadanya, tetapi bagi Nguyen Tien Dat, puisi-puisi tersebut tampaknya tidak hilang tetapi "masih ada di sini untuk mengenang" saudara-saudara dan teman-temannya.
Ho Nguyen Kha
Sumber: https://baoquangtri.vn/nguyen-tien-dat-van-con-day-thuong-nho-194401.htm














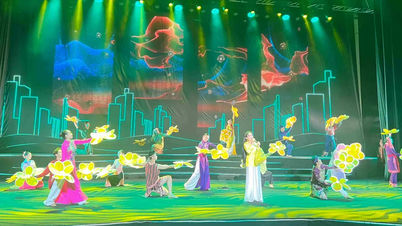





























![[Foto] Menyembah patung Tuyet Son - harta karun berusia hampir 400 tahun di Pagoda Keo](/_next/image?url=https%3A%2F%2Fvphoto.vietnam.vn%2Fthumb%2F1200x675%2Fvietnam%2Fresource%2FIMAGE%2F2025%2F12%2F02%2F1764679323086_ndo_br_tempimageomw0hi-4884-jpg.webp&w=3840&q=75)
![[Foto] Parade untuk merayakan hari jadi ke-50 Hari Nasional Laos](/_next/image?url=https%3A%2F%2Fvphoto.vietnam.vn%2Fthumb%2F1200x675%2Fvietnam%2Fresource%2FIMAGE%2F2025%2F12%2F02%2F1764691918289_ndo_br_0-jpg.webp&w=3840&q=75)
































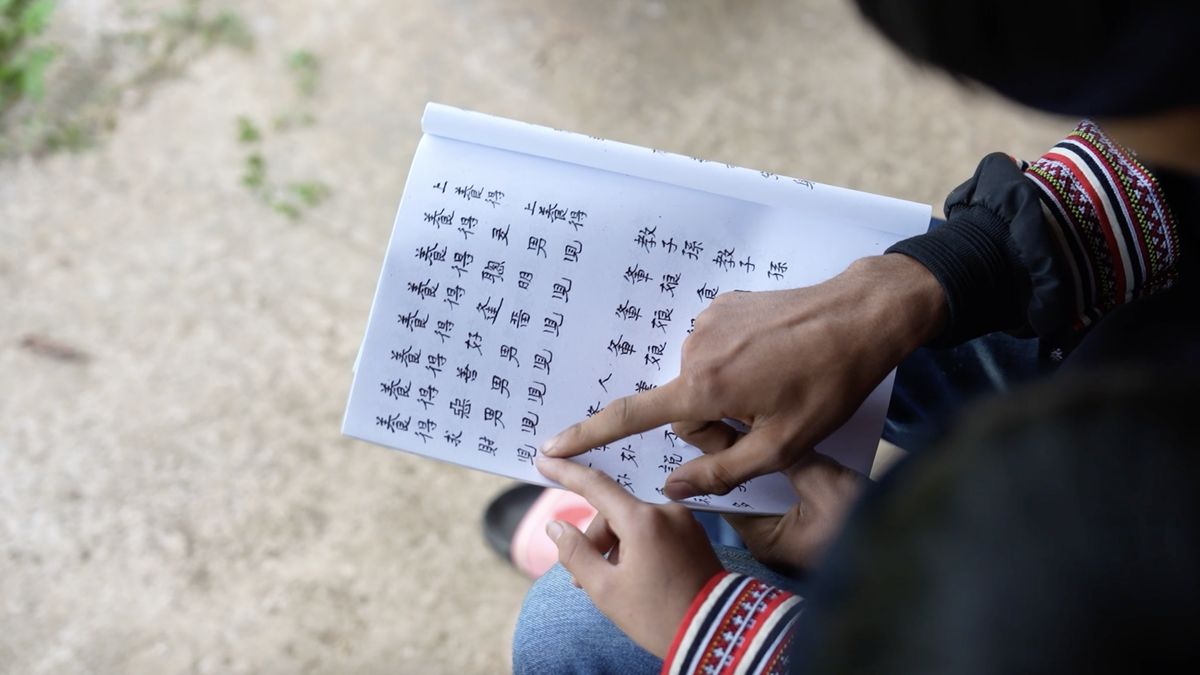















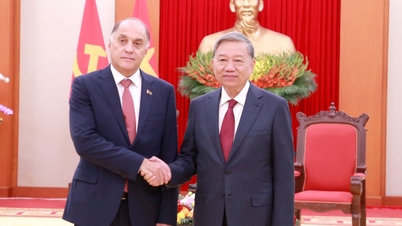





















Komentar (0)