Penulis bekerja dengan Ibu Ho Thi Pieng, 83 tahun, di Dusun 3b, Kota Khe Sanh, yang merupakan saksi pembantaian 94 orang di komunitas Ta Rut pada tahun 1955 - Foto: MT
Mengenang masa-masa awal karier saya, saya adalah seorang reporter magang, memegang perekam kaset tua, mengendarai sepeda motor rusak di bawah terik matahari siang kembali ke markas. Saat itu, jurnalisme bagi saya adalah sesuatu yang sangat glamor, saya bisa bepergian jauh, bertemu banyak orang, dan disebut jurnalis. Namun, semakin saya menekuni profesi ini, semakin saya menyadari bahwa di balik kartu pers terdapat banyak tekanan, kekhawatiran, dan terkadang bahkan bahaya.
Produk pertama saya adalah artikel tentang seorang ibu miskin di Desa Tham Khe, Kecamatan Hai Khe, Distrik Hai Lang. Kesan pertama saya adalah kemiskinan yang nyata di daerah pesisir terpencil di atas pasir yang terbakar. Ibu miskin itu hanya memiliki seorang putra yang belum menikah. Suatu hari, putranya pergi memancing di laut dan tak pernah kembali. Ia meringkuk di sudut tenda tanpa atap dengan selimut tipis dan compang-camping.
- Kamu sudah makan? tanyaku.
Sesaat kemudian dia berbisik: Kita sudah kehabisan beras selama tiga hari, paman!
Saya pergi ke kotak amunisi senapan mesin tua yang biasa ia gunakan untuk menyimpan beras. Ketika saya membukanya, saya terkejut melihat hanya ada delapan butir beras bercampur karat. Bagian bawah kotak penuh dengan goresan. Ia pasti mencoba memasak nasi lagi, tetapi tidak ada yang tersisa untuk menyalakan api. Ia sudah kelaparan selama tiga hari.
Kader desa yang menemani saya kebingungan saat menjelaskan. Ia telah hidup sendiri selama bertahun-tahun, tanpa kerabat. Tetangga sesekali membantu dengan makanan dan sayuran, tetapi di negeri yang penuh kekurangan, kebaikan hanya bertahan sebentar. Saya mengeluarkan dompet dan memberikan semua uangnya, jadi ketika saya kembali, motor saya kehabisan bensin di tengah jalan dan harus berjalan lebih dari 5 km sebelum akhirnya menggunakan telepon Pos Penjaga Perbatasan untuk menghubungi rekan-rekan saya dan meminta bantuan.
Sekembalinya ke redaksi, saya menulis artikel itu dengan perasaan yang berat. Artikel itu tercetak di halaman depan, dengan foto dirinya meringkuk di bawah atap yang robek, memandang menembus awan dan langit. Hanya dua hari kemudian, puluhan panggilan telepon masuk, dari orang-orang di Hue, Da Nang, hingga Hanoi dan Saigon. Sebuah lembaga amal membawa beras, selimut, dan bahkan uang tunai untuk membantu. Ia menangis, saya pun menangis. Itulah pertama kalinya saya melihat pena saya membawa kebahagiaan bagi seseorang. Dan saya juga belajar sesuatu. Jurnalisme yang menyentuh kehidupan, terkadang menyakitkan, mencekik, dan menceritakan kisah dengan segala kejujuran, rasa hormat, tanpa hiasan, tanpa sensasionalisme, tanpa penghindaran akan menghasilkan efektivitas yang nyata.
Artikel tentang ibu di Tham Khe adalah titik awal perjalanan saya selama 23 tahun. Setelah itu, saya menjelajahi banyak negeri, bertemu dengan begitu banyak kehidupan, tetapi perasaan berdiri di depan kotak amunisi kosong berisi 8 butir beras itu adalah sesuatu yang tak akan pernah saya lupakan.
Namun, jurnalisme bukannya tanpa momen-momen memilukan. Ada artikel-artikel yang mencerminkan opini negatif, meskipun telah diverifikasi secara menyeluruh, tetapi tanpa sengaja masih menjadi alat untuk kalkulasi keuntungan. Saya masih ingat dengan jelas sebuah kasus yang tampaknya jelas. Ketika kami menerima laporan dari orang-orang tentang penindasan yang mereka alami dalam pelelangan tambak udang dan ikan di sebuah komunitas pesisir, kami segera pergi ke lokasi untuk memverifikasi.
Begini ceritanya: pemerintah daerah mengadakan lelang untuk area laguna seluas hampir 2 hektar untuk akuakultur. Lelang berjalan lancar hingga pengumuman hasil lelang, dengan penawar tertinggi sebagai pemenangnya. Namun, tak lama kemudian, beberapa orang menemukan bahwa penawaran unit tersebut tidak memiliki angka nol, sehingga harga sebenarnya jauh lebih rendah.
Menurut peraturan, penawaran yang salah dicatat tidak sah dan unit berikutnya dengan harga lebih rendah akan dianggap sebagai pemenang lelang. Namun, yang menjadi kontroversi adalah selisih antara kedua unit tersebut mencapai ratusan juta dong. Pemerintah komune, di bawah tekanan "nilai aset negara yang hilang", mengumumkan pembatalan hasil lelang dan reorganisasi lelang. Dari sinilah dimulai serangkaian keluhan dan kecaman antara unit pemenang awal dan Komite Rakyat komune.
Kami terlibat, bertemu dengan banyak pemangku kepentingan, meninjau dokumen hukum dengan saksama, dan menyimpulkan bahwa pemberian kontrak kepada unit peringkat kedua setelah unit peringkat pertama dihapuskan sepenuhnya sesuai dengan peraturan. Di bawah tekanan dari berbagai pihak, termasuk suara pers, pemerintah komune akhirnya terpaksa mengakui hasil tersebut.
Saya pikir kasusnya sudah selesai. Namun, setahun kemudian, di suatu sore yang cerah, tiga petambak datang ke rumah saya membawa 2 kg udang awal musim. Mereka memperkenalkan diri sebagai pemenang kontrak tambak udang tahun itu, dan datang untuk memberi saya hadiah kecil sebagai ucapan terima kasih kepada wartawan atas bantuannya. Namun setelah beberapa percakapan, saya merasa ada yang tidak beres. Setelah banyak bertanya, mereka akhirnya mengakui bahwa seluruh lelang itu hanya sandiwara belaka.
Kedua penawar yang berpartisipasi sebenarnya telah bersekongkol sebelumnya. Salah satu penawar menawar dengan harga sangat tinggi, sengaja menuliskan angka 0 agar tereliminasi, membuka jalan bagi penawar lain dengan harga yang jauh lebih rendah untuk memenangkan penawaran "secara sah". Skenarionya begitu cerdik sehingga bahkan para pejabat komune, ketika mereka menemukan tanda-tanda penyimpangan, tidak berani bertindak karena tekanan publik, termasuk pers.
Kita, para penulis, telah terperangkap dalam drama yang dipentaskan dengan cermat di mana kebenaran diubah menjadi alat untuk mencari untung. Sebuah pelajaran yang menyakitkan, tidak hanya tentang profesi, tetapi juga tentang kepercayaan.
Saya ingat betul rasa kebingungan yang saya rasakan ketika berdiri di hadapan mereka, para petani yang tampak sederhana, tangan mereka masih berbau lumpur. Setiap kata mereka bagaikan pisau yang mengiris kepercayaan penuh pada integritas yang saya bawa sejak saya memasuki profesi ini. Ternyata, niat baik bisa dimanfaatkan. Ternyata, kepercayaan juga bisa menjadi tempat untuk perhitungan yang egois.
Keesokan paginya, saya duduk untuk menuliskan semuanya, tetapi kali ini bukan untuk dipublikasikan, melainkan hanya untuk mengungkapkan perasaan saya. Karena saya tahu jika saya terus mengungkapkannya kepada publik, saya mungkin tanpa sengaja menciptakan pusaran kontroversi, rasa sakit hati, dan keraguan yang baru. Saya harus belajar memilih waktu yang tepat untuk bersuara, dan cara yang tepat untuk menyampaikan kebenaran. Karena kebenaran tidak selalu diterima sebagaimana mestinya. Terkadang dibutuhkan kesabaran, persiapan, dan keberanian untuk menunggu.
Dari kisah itu, saya mengubah cara kerja saya. Setiap informasi yang diterima dari masyarakat, betapa pun emosional dan detailnya refleksi tersebut, diperiksa lebih dari sekali. Tidak hanya dengan membandingkannya dengan kata-kata tertulis atau lisan para pejabat, tetapi juga dengan menempatkannya dalam konteks hubungan yang lebih luas, sejarah lokal, dan motif tersembunyi di baliknya.
Sejak saat itu, kita menjadi lebih berhati-hati saat berpihak pada seseorang. Bukan berarti pers kehilangan dukungannya terhadap mereka yang rentan, melainkan untuk melindungi orang-orang yang tepat yang benar-benar membutuhkan perlindungan. Dan terkadang juga untuk melindungi kehormatan jurnalisme, yang telah berkali-kali digunakan sebagai tameng oleh kaum oportunis.
Seseorang bertanya. Setelah kejadian itu, apakah kamu takut? Saya menjawab tanpa ragu. Ya. Takut salah. Takut dimanipulasi. Tapi yang terpenting, takut menyakiti orang jujur lainnya. Dan saya belajar pelajaran berharga bahwa. Seorang jurnalis tidak hanya membutuhkan pena yang tajam, tetapi juga kepala dingin dan hati yang tenang. Kebenaran tidak selalu mayoritas. Dan terkadang, apa yang benar bukanlah yang menyenangkan semua orang.
Jika dipikir-pikir kembali, insiden itu bukan hanya kegagalan sebuah artikel, tetapi juga kegagalan iman dan hati nurani. Namun sejak saat itu, kami melangkah lebih teguh, lebih bertanggung jawab, dan lebih rendah hati dalam profesi kami. Tidak lagi dengan pola pikir "mengungkap kebenaran dengan segala cara", melainkan mengejar kebenaran dengan semangat keadilan, kerendahan hati, dan pemahaman yang cukup agar tidak terjebak dalam perhitungan di balik layar.
Sejak saat itu, setiap kali saya mengambil pena untuk menulis tentang kisah negatif, saya bertanya pada diri sendiri: Benarkah ini?, selalu bertanya lebih banyak lagi. Siapa dalang di balik kisah ini? Dan apakah kita sedang terseret ke dalam permainan lain yang tidak kita ketahui?
Selama 23 tahun berkarier sebagai jurnalis, saya telah melewati berbagai suka duka, mulai dari kebahagiaan yang tampaknya kecil namun berdampak besar, hingga kekecewaan yang memilukan yang membuat saya merenung. Terkadang pena menjadi jembatan cinta, terkadang menjadi pedang bermata dua jika tidak digenggam dengan keberanian dan kewaspadaan.
Namun, saya selalu percaya pada misi mulia jurnalisme, yaitu perjalanan mencari kebenaran, bukan dengan kesombongan seseorang yang memegang timbangan keadilan, melainkan dengan hati yang tahu bagaimana mendengarkan, tahu bagaimana meragukan bahkan emosi sendiri agar tidak secara tidak sengaja menjadikan diri sendiri alat bagi orang lain. Kini, ketika rambut saya sudah beruban, saya masih merasakan jantung saya berdebar setiap kali menemukan kisah hidup yang perlu diceritakan.
Sebab mungkin, motivasi yang membuat orang terus menekuni jurnalisme sepanjang hidupnya bukanlah halo, bukan pula gelar, melainkan momen ketika melihat kehidupan seseorang, suatu kejadian yang diterangi oleh cahaya hati nurani.
Minh Tuan
Sumber: https://baoquangtri.vn/vui-buon-nghe-bao-chuyen-ke-sau-23-nam-cam-but-194443.htm



![[Foto] Segera bantu masyarakat memiliki tempat tinggal dan menstabilkan kehidupan mereka](/_next/image?url=https%3A%2F%2Fvphoto.vietnam.vn%2Fthumb%2F1200x675%2Fvietnam%2Fresource%2FIMAGE%2F2025%2F12%2F09%2F1765248230297_c-jpg.webp&w=3840&q=75)






















































































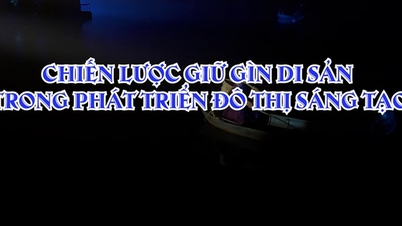



























Komentar (0)