Di pagi hari, saya sering membawa baskom berisi air hujan dan perlahan-lahan menyeka wajah ayah saya. Beliau sudah terbaring di sana selama hampir setengah tahun, sejak hari ia jatuh dari sarang orang-orangan sawah di ladang, kakinya sakit dan ia tidak bisa berdiri. Saat itu, ayah saya masih mencoba menggunakan tongkat untuk pergi ke Pasar Bung untuk berjualan daun ubi jalar, tetapi kemudian demam membuatnya jatuh sakit, membuatnya bungkuk di atas ranjang bambu.
Ibu saya kini menjadi ibu sekaligus ayah, dan satu-satunya pencari nafkah. Ia selalu mengenakan Ao Ba Ba usang yang sama, tangannya berurat sepanjang hari, menggali tanah, mencabuti rumput liar, dan memetik padi. Kadang ada makanan, kadang tidak, makanannya hanya terdiri dari beberapa kerupuk kulit babi kering dan semangkuk saus ikan asam, tetapi kami tetap merasa anehnya lezat. Mungkin karena semua kasih sayang dari ibu, ayah, dan atap reyot ini.

ILUSTRASI: AI
Sore ini gerimis. Saya duduk di ambang pintu, membetulkan buku catatan hijau putra bungsu saya. Dia baru saja masuk kelas tiga, dan tulisan tangannya masih miring. Setiap kali hujan, saya takut bukunya basah. Ibu berjongkok di halaman, mencuci kol manis yang dipetiknya dari kebun. Ayah berbaring diam, bernapas pelan.
Aku menatap air keperakan dan tiba-tiba ingin menangis. Bermalam-malam berbaring di tempat tidur gantung, aku terus bertanya-tanya: apa yang akan terjadi dalam hidupku? Akankah putra bungsuku mendapatkan pendidikan yang layak? Akankah ia harus mengikuti perahu untuk menggali pasir seperti ayahnya?
Anak laki-laki termuda berjalan perlahan, memegang buku catatan basah di tangannya. Ia menatapku, mata hitamnya sendu:
- Kakak, besok kita masih punya nasi nggak?
Aku menelan ludah dengan susah payah, tanganku meremas bahunya dengan lembut:
- Ya, ada. Ibu bilang besok dia akan menjual ikan linh kering dan membeli beras.
- Tapi… bagaimana jika tidak ada yang membeli?
- Kalau begitu, aku pergi memungut padi bersama Ibu. Aku sudah dewasa sekarang.
Ia menundukkan kepala, air matanya mengalir deras ke lumpur. Aku tak berani menghapusnya. Aku takut tanganku akan lebih dingin daripada hujan.
Malam itu, rumah gelap gulita. Lampu minyak menyinari dinding dengan cahaya kuning redup. Ibu duduk memperbaiki kelambu yang robek, sementara Ayah terdiam seolah tertidur. Aku mengikat eceng gondok kering untuk dibawa ke pasar besok.
Ibu mendongak, suaranya lelah namun lembut:
Hai, besok kamu bolos sekolah dan pergi ke ladang bersama ibumu untuk memanen padi. Ayahmu sedang sakit hari ini, aku khawatir aku tidak bisa membayar padi tepat waktu.
Aku mengangguk, tak berani menatap matanya. Di bawah cahaya redup, aku bisa melihat kerutan di pipinya yang kering, seperti jejak waktu dalam hidup seseorang.
***
Pagi-pagi sekali, aku terbangun karena kabut tebal. Putra bungsuku meringkuk, selimutnya menutupi dagunya. Aku mengusap punggungnya pelan, lalu membawa keranjang nasi di belakang ibuku. Jalan tanah licin karena hujan semalam. Langkahku terasa berat.
Di seberang kanal, dahan-dahan bakau bermekaran penuh, aroma manis tercium di udara. Ibu terdiam sepanjang perjalanan, hanya sesekali menoleh ke belakang untuk berkata:
- Hati-hati, jangan sampai jatuh, Nak.
Aku menjawab iya dengan lembut, sambil menatap punggungnya yang basah oleh embun.
Sesampainya di sawah, aku membungkuk untuk memunguti sisa bulir padi. Berasnya dingin dan tanganku mati rasa. Aku berusaha untuk tidak memikirkan perutku yang lapar sejak kemarin sore. Ibu berada di seberang sungai, punggungnya membungkuk, tangannya menggali lumpur untuk mencari bulir padi.
Seorang tetangga lewat, melihat ibu dan anak itu, lalu mendesah:
Kasihan sekali. Hai sudah besar tapi masih harus mengumpulkan beras untuk memberi makan orang tuanya.
Ibu mendongak, tersenyum tipis, suaranya seperti angin yang bertiup di antara rumput:
- Kalau kamu miskin, ya sudahlah. Asal anak-anakmu tidak kehilangan kesetiaan dan kasih sayang mereka.
Aku menggigit bibirku, mencoba mengisi keranjang itu.
Siang harinya, Ibu berbagi setengah mangkuk nasi dingin dengan beberapa potong nasi kering dan keras. Aku makan perlahan, mendengarkan kicauan serangga di luar ladang. Terik matahari menyengat, membuat mataku perih.
Ibu menyendokkan sesendok nasi lagi untukku, suaranya serak:
Makanlah sepuasnya, Nak. Hanya dengan kekuatan, kau bisa bertahan hidup dalam kemiskinan.
Aku mengangguk, tak bisa berkata apa-apa.
Sore harinya, angin bertiup kencang di tepi kanal. Ibu dan saya bergegas membawa dua keranjang beras pulang. Kami menyeberangi jalan yang rendah, airnya setinggi kaki celana kami. Ibu hampir terpeleset, saya melepaskan keranjang dan membantunya berdiri.
Tangan ibuku yang gemetar mencengkeram bahuku. Ia mengerucutkan bibirnya, tak berani menatapku:
- Ibu sudah tua dan sangat ceroboh.
Aku menundukkan kepalaku, suaraku hilang:
Tanpa Ibu, aku dan putra bungsuku tidak akan bisa makan. Jangan bilang begitu.
Dia tidak menjawab, hanya meremas tanganku dengan lembut.
Sesampainya di rumah, ayahnya masih terbaring tak bergerak. Putra bungsunya berjongkok di sampingnya, mengipasi dirinya dengan kipas daun palem. Ketika melihat ibunya kembali, ia bergegas keluar dan berbisik:
- Ibu… Ayah bilang dia haus.
Ibu meletakkan keranjang nasi dan buru-buru menuangkan air hujan ke dalam cangkir keramik yang pecah. Ia mengangkat kepala Ayah dan menuangkannya sedikit demi sedikit. Ayah mengembuskan napas pelan, suaranya sekering angin:
- Terima kasih… Terima kasih.
Saya berdiri bersandar di dinding, mendengarkan kalimat biasa yang beratnya seperti sepuluh gantang beras.
***
Malam harinya, aku duduk sendirian di tepi sungai. Airnya gelap gulita, dengan cahaya bulan yang menyinari deretan pohon kelapa. Aku ingat waktu kecil dulu, ayahku sering mengajakku naik perahu ke pasar terapung. Pagi-pagi sekali, perahu bergoyang, teriakan para pedagang terdengar jelas, ayahku membelikanku semangkuk mi ikan linh panas.
Kini ayah saya tak lagi bisa mendayung perahu. Ia menjual perahunya. Uangnya ia gunakan untuk membeli beras dan obat-obatan. Yang tersisa hanyalah rumah kosong, dan tiga atau empat orang yang hidup berdesakan dalam kemiskinan yang menyesakkan.
Aku mendongak, berusaha menelan gumpalan di tenggorokanku. Hanya ada satu pikiran di benakku: aku harus pergi besok.
Keesokan paginya, aku berkata kepada ibuku:
- Bu, izinkan aku pergi ke Saigon. Aku sudah meminta Paman Tu di sana untuk mengizinkanku bekerja sebagai kuli bangunan.
Ibu tertegun, matanya terbuka lebar, suaranya gemetar:
- Saya baru berusia tujuh belas tahun...
- Tapi aku baik-baik saja. Aku bisa. Sini... Bu, ini terlalu berat.
Dia tidak berkata apa-apa. Dia hanya diam-diam mengeluarkan tumpukan pakaian lama dan memasukkannya ke dalam kantong plastik:
- Aku tidak akan menghentikanmu. Pergi... jaga dirimu baik-baik.
Ayah berbaring di sudut tempat tidur, matanya berkaca-kaca. Ia mengulurkan tangannya yang kurus kepadaku:
- Pergilah, Nak. Selama kita saling mencintai, di mana pun adalah rumah.
Aku berjalan kembali, menundukkan kepala, dan menyentuh tangan ayahku. Tangan itu pernah menuntunku menyeberangi sungai, mendorong perahu menembus pusaran air. Kini tangan itu kering kerontang.
Sore itu, putra bungsuku duduk di teras, memperhatikanku memasukkan barang-barang ke dalam tas. Ia menggigit bibir dan berbisik:
- Kakak… kapan kamu pulang?
- Suatu hari nanti, jika aku punya uang, aku akan memperbaiki rumah dan membeli obat untuk ayahku.
- Aku tidak ingin kamu pergi.
Aku berhenti. Hatiku sakit. Tapi aku tahu kalau aku tidak pergi, kemiskinan akan menelan kita semua.
Aku membungkuk dan menepuk kepalanya:
- Kak, aku janji… sejauh apapun aku pergi, hatiku akan selalu di sini, sama kamu, sama ibu, sama ayah.
Dia menangis tersedu-sedu, dan membenamkan wajahnya di bahuku.
***
Sore harinya, Paman Tu mengendarai mobil tuanya untuk menjemputku. Aku memandang sekeliling rumah kosong itu untuk terakhir kalinya. Dinding bambunya lapuk, atap jeraminya compang-camping. Di tempat tidur, Ayah berbaring diam, matanya terpejam seolah sedang tidur. Ibu berdiri bersandar di pilar, tangannya terkepal erat.
Aku melangkah keluar ke halaman dan berbisik:
- Bu… aku pergi dulu.
Dia mendongak, bibirnya terkatup rapat, lalu mengangguk sedikit.
Paman Tu menyalakan mesin. Motornya melesat menembus jalan berlumpur. Aku menoleh ke belakang dan melihat ibuku yang kurus membungkuk di atas pintu, putra bungsuku berdiri di sampingnya, menyeka air matanya.
Mobil melaju pergi, tepi sungai pun menghilang. Angin sore berhembus menerpa wajahku, asin oleh keringat dan air mata. Aku memejamkan mata dan berkata dalam hati:
Saya miskin, tapi jangan biarkan hatimu kecil.
***
Bus melaju hampir sepanjang pagi sebelum tiba di Terminal Mien Tay. Saya turun dari bus, menggenggam tas berisi pakaian, dan memandangi kerumunan yang ramai. Bau debu dan asap knalpot tercium di wajah saya, sangat berbeda dengan bau lumpur dan jerami dari kampung halaman saya.
Paman Tu mengantarku ke sebuah rumah kos yang sempit. Deretan kamarnya penuh dengan buruh kasar, semuanya lelah setelah seharian mengangkut barang dan menuang beton. Ia menyuruhku tinggal di sini sementara dan akan membawaku mencari pekerjaan besok.
Malam pertama jauh dari rumah, aku berbaring di atas keset yang robek, mendengarkan dengungan nyamuk. Dalam pikiranku, aku terus membayangkan ayahku berbaring diam di tempat tidur, ibuku membungkuk untuk memperbaiki kelambu, dan putra bungsuku duduk meringkuk menyalin PR-nya. Aku meletakkan tanganku di dada, menyentuh selembar kertas kecil yang terselip di bajuku—surat yang diberikan ibuku saat aku masuk ke mobil: "Jaga dirimu saat kau pergi. Aku sayang padamu."
Aku meremas kertas itu, berusaha menahan isak tangis.
Keesokan paginya, saya pergi ke lokasi konstruksi bersama Paman Tu. Pekerjaannya biasa saja: mengangkut batu bata, mengaduk adukan semen, menyekop pasir. Namun, terik matahari Saigon terasa menyengat. Keringat membasahi punggung dan mata saya perih.
Siang itu, saya duduk bersandar di tumpukan batu bata, membuka sekotak nasi iga babi dingin. Sesaat, saya berharap sedang duduk di tengah dapur desa, menyantap semangkuk nasi dengan saus ikan bersama ibu dan putra bungsu saya. Di sini, nasi iga babi terasa hambar.
Seorang tukang batu berambut abu-abu menepuk bahuku:
- Kangen kampung halaman, nak?
Ya… saya ingat.
- Teruslah maju. Selama kamu mengingatku setiap hari, hatimu akan tetap hangat.
Aku menundukkan kepala, mendengarkan kata-kata lembut yang bagaikan tiang tambatan di hatiku.
Malam itu, saya mampir ke kantor pos dekat tempat kos saya dan mengirimkan 150.000—gaji pertama saya—ke rumah. Petugas pos bertanya:
- Bisakah saya menyampaikan pesan?
Aku mengangguk pelan, memegang pena, dan menulis setiap kata dengan hati-hati: "Bu, aku baik-baik saja. Gunakan uang ini untuk membeli obat Ayah. Aku sangat menyayangimu dan keluarga kita."
Tangan saya gemetar saat menempelkan surat suara. Tapi untuk pertama kalinya dalam hidup saya, saya merasa cukup besar untuk membantu ibu saya.
***
Malam harinya, aku duduk di tangga kosku. Di atas kepalaku, bulan sabit tipis menggantung. Aku merindukan dermaga sungai di kota kelahiranku, gugusan bakau berbunga putih, suara ayahku memanggil makan malam, dan kata-kata yang dibisikkan ibuku di telingaku: Asal kita saling mencintai, sepiring kecap ikan akan terasa nikmat.
Aku mendongak dan menarik napas dalam-dalam. Di tengah Saigon yang luas, hatiku masih merindukan sungai kecil Cai Con—yang atapnya reyot, tetapi cintaku tak pernah goyah.
Kontes Menulis Hidup Sejahtera yang kelima diselenggarakan untuk mendorong orang-orang menulis tentang tindakan-tindakan mulia yang telah membantu individu atau komunitas. Tahun ini, kontes berfokus pada pemberian pujian kepada individu atau kelompok yang telah melakukan tindakan kebaikan, membawa harapan bagi mereka yang berada dalam situasi sulit.
Sorotan utama adalah kategori penghargaan lingkungan baru, yang memberikan penghargaan kepada karya-karya yang menginspirasi dan mendorong aksi untuk lingkungan hidup yang hijau dan bersih. Melalui penghargaan ini, Panitia Penyelenggara berharap dapat meningkatkan kesadaran publik dalam melindungi planet ini untuk generasi mendatang.
Kontes ini memiliki beragam kategori dan struktur hadiah, termasuk:
Kategori artikel: Jurnalisme, reportase, catatan atau cerita pendek, tidak lebih dari 1.600 kata untuk artikel dan 2.500 kata untuk cerita pendek.
Artikel, laporan, catatan:
- 1 hadiah pertama: 30.000.000 VND
- 2 hadiah kedua: 15.000.000 VND
- 3 hadiah ketiga: 10.000.000 VND
- 5 hadiah hiburan: 3.000.000 VND
Cerpen:
- 1 hadiah pertama: 30.000.000 VND
- 1 hadiah kedua: 20.000.000 VND
- 2 hadiah ketiga: 10.000.000 VND
- 4 hadiah hiburan: 5.000.000 VND
Kategori foto: Kirimkan rangkaian foto minimal 5 foto yang terkait dengan kegiatan sukarela atau perlindungan lingkungan, beserta nama rangkaian foto dan deskripsi singkat.
- 1 hadiah pertama: 10.000.000 VND
- 1 hadiah kedua: 5.000.000 VND
- 1 hadiah ketiga: 3.000.000 VND
- 5 hadiah hiburan: 2.000.000 VND
Hadiah Terpopuler: 5.000.000 VND
Hadiah untuk Esai Luar Biasa tentang Topik Lingkungan: 5.000.000 VND
Penghargaan Karakter Terhormat: 30.000.000 VND
Batas waktu pengiriman karya adalah 16 Oktober 2025. Karya akan dievaluasi melalui babak penyisihan dan final dengan partisipasi juri yang terdiri dari nama-nama ternama. Panitia penyelenggara akan mengumumkan daftar pemenang di halaman "Beautiful Life". Lihat ketentuan selengkapnya di thanhnien.vn .
Panitia Penyelenggara Kontes Hidup Indah

Source: https://thanhnien.vn/chieu-ben-song-truyen-ngan-du-thi-cua-nguyen-tuan-khang-185250912113758608.htm


![[Foto] Pembukaan Konferensi ke-13 Komite Sentral Partai ke-13](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/1200x675/vietnam/resource/IMAGE/2025/10/6/d4b269e6c4b64696af775925cb608560)




![[Foto] Perdana Menteri Pham Minh Chinh memimpin konferensi daring Pemerintah dengan daerah-daerah](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/1200x675/vietnam/resource/IMAGE/2025/10/5/264793cfb4404c63a701d235ff43e1bd)









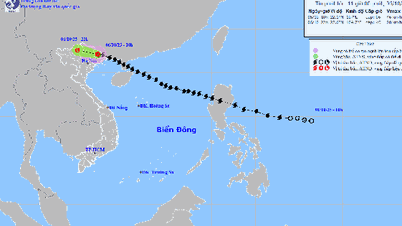















![[Foto] Perdana Menteri Pham Minh Chinh meluncurkan kampanye emulasi puncak untuk mencapai prestasi dalam perayaan Kongres Partai Nasional ke-14](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/1200x675/vietnam/resource/IMAGE/2025/10/5/8869ec5cdbc740f58fbf2ae73f065076)













































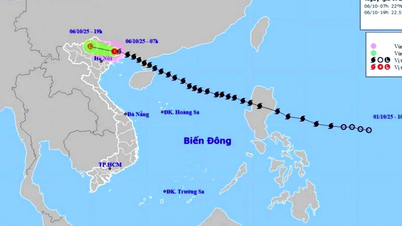























Komentar (0)