"Kelas literasi di tengah hutan"
Sin Thau adalah sebuah komune perbatasan yang terletak sekitar 250 km dari pusat Provinsi Dien Bien , terkenal dengan julukan "satu ayam jantan berkokok, tiga negeri bersahut-sahutan". Tempat ini tak hanya identik dengan perbatasan yang terjal, tetapi juga dikenal karena para gurunya yang diam-diam tinggal di desa dan sekolah untuk menabur setiap huruf, setiap benih harapan bagi etnis minoritas. Di antara mereka, guru Dao Thi Thoa, guru di Sekolah Asrama Dasar Sin Thau untuk Etnis Minoritas, adalah salah satu dari mereka yang diam-diam melanjutkan perjalanan pemberantasan buta huruf di ujung barat negara ini.
Saya masih ingat, beberapa tahun yang lalu, ketika Ibu Thoa masih bekerja di Sekolah Dasar untuk Etnis Minoritas Huoi Lech. Suatu sore, kami pergi ke sekolah Nam Pan 2, salah satu lokasi terpencil tersulit di komune Huoi Lech. Dengan sepeda motor tua, kami membutuhkan waktu hampir setengah jam untuk mendaki bukit dan menemukan jalan ke tempat Ibu Thoa mengajar. Suara anak-anak mengeja dan guru yang mengajar dengan sabar bergema di pegunungan dan hutan yang luas, membuat suasana itu semakin istimewa.
Sekolah ini terletak di perbukitan yang landai, dengan dua jenjang pendidikan: taman kanak-kanak dan sekolah dasar, dengan fasilitas sederhana yang sama. Satu-satunya kelas dasar adalah kelas gabungan 1+2 yang diajar oleh Ibu Thoa. Hanya ada 10 siswa, tetapi pada hari kunjungan kami, kelas tersebut hanya memiliki 8 siswa. Dua siswa lainnya tidak hadir karena keluarga mereka sedang mengadakan upacara, sesuai adat setempat, selama masa pantang, anak-anak tidak diperbolehkan meninggalkan desa.
"Mengetahui akan ada wartawan yang datang, saya harus mengantar anak-anak ke kelas sendiri, kalau tidak, saya akan ketinggalan pelajaran pagi dan tidak kembali sore harinya. Orang tua di sini tidak menganggap serius pendidikan, terkadang mereka bahkan menganggap belajar membaca dan menulis adalah kemewahan," ungkap Ibu Thoa.
Ruang belajarnya berupa rumah sederhana dengan meja dan kursi reyot serta papan tulis yang sudah pudar. Di kelas tersebut, guru harus mengajar pada dua tingkat yang berbeda, baik untuk menghibur siswa yang masih asing dengan huruf-huruf tersebut maupun untuk mencoba mengatasi kendala bahasa. Siswa kelas satu kebanyakan adalah orang Mong, yang baru mulai mengenal bahasa umum, banyak dari mereka tidak mengerti apa yang diajarkan guru dan harus meminta bantuan teman-teman mereka untuk menerjemahkan.

Dari perjalanan menabur ilmu hingga cita-cita memberantas buta huruf
Lahir di Hung Yen dan dibesarkan di Dien Bien, guru Thoa bercita-cita menjadi guru untuk "membawa surat ke pegunungan". Pada tahun 2003, ketika Muong Nhe (nama unit administratif lama) baru saja dibentuk dari distrik Muong Te (provinsi Lai Chau lama), jalan-jalan sulit dilalui. Ia dan 25 guru lainnya menjadi sukarelawan untuk "menyeberangi hutan dan sungai" dari komune Cha Cang ke Muong Toong 2 untuk membuka sekolah tersebut.
"Saat itu, kami butuh waktu seminggu untuk berjalan hampir 100 km, kaki kami bengkak, otot-otot kami kaku sekali hingga tak bisa bergerak. Namun, setiap kali kami memikirkan desa-desa yang tidak memiliki sekolah dan tidak ada yang bisa membaca dan menulis, kami bertekad untuk terus berjalan," kata Ibu Thoa.
Perjalanan itu bukan hanya pengorbanan pribadi, tetapi juga kontribusi penting bagi upaya pemberantasan buta huruf di dataran tinggi. Ia mengatakan bahwa di banyak desa pada masa itu, tidak ada yang tahu cara menandatangani. Pengerjaan dokumen dilakukan dengan cap tangan. Anak-anak tidak diizinkan bersekolah. Orang dewasa takut belajar, takut diejek.
Ibu Thoa tidak hanya mengajar siswa, tetapi juga menyelenggarakan kelas literasi malam bersama rekan-rekannya untuk orang tua. Awalnya, hanya sedikit orang yang hadir, tetapi lambat laun, mereka mulai menyadari nilai literasi: mampu membaca rekam medis, menandatangani, memahami dokumen, atau sekadar menulis nama anak-anak mereka.
"Orang-orang kami sangat baik, mereka tidak malas, mereka hanya takut karena belum pernah belajar. Ketika guru memberi saran dan instruksi, mereka sangat tekun. Ada seorang perempuan yang belajar selama beberapa bulan dan berhasil menulis nama suami dan anak-anaknya. Ia sangat senang. Setiap hari ia membawa buku catatannya untuk dipamerkan," kenangnya.

Jaga profesi tetap hidup dengan cinta
Ibu Thoa dan suaminya sama-sama guru di daerah terpencil. Kedua anak mereka terpaksa tinggal bersama kakek-nenek mereka di kota. Suatu ketika, anak sulungnya mengalami kecelakaan dan dirawat di rumah sakit. Ibu Thoa dan suaminya meminta izin pulang untuk menjenguk anak mereka, lalu segera kembali ke sekolah. Rasa sakit karena merindukan anaknya dan jauh dari rumah selalu menghantuinya, terutama di malam-malam musim dingin yang panjang dengan hanya remang-remang cahaya lampu minyak di tengah pegunungan dan hutan yang gersang.
"Terkadang anak saya menangis dan menolak mengikuti saya karena kami sudah lama tidak bertemu. Di malam hari, saya bermimpi anak saya memanggil saya dan saya hanya bisa menangis. Tapi saya tidak bisa meninggalkan tempat ini. Kalau saya pergi, kelasnya harus ditutup. Tidak akan ada lagi yang bisa mengajar anak-anak," kata Ibu Thoa tersedak.
Kecintaannya pada pekerjaannya, kepeduliannya terhadap murid-muridnya, dan tanggung jawabnya dalam upaya pemberantasan buta huruflah yang membuatnya tetap tinggal di desa terpencil ini. Di awal setiap tahun ajaran, orang tua di desa menulis dan menandatangani petisi agar Ibu Thoa tetap tinggal, dengan harapan ia tidak akan dipindahkan ke pekerjaan lain.
Melihat anak-anak duduk dan belajar membaca dan menulis membuat saya merasa lega. Banyak dari mereka awalnya hanya bisa berbicara bahasa Mong dan bahkan tidak bisa memegang pena. Tapi sekarang mereka bisa menulis nama mereka dan membaca nama ibu mereka. Saya pikir, selama saya bisa mengajari mereka membaca dan menulis, sesulit apa pun, itu sepadan.
Literasi adalah pintu yang membuka masa depan.
Dari ruang kelas terpadu di tengah hutan seperti milik Ibu Thoa, anak-anak tidak hanya mendapatkan akses pengetahuan, tetapi upaya pemberantasan buta huruf juga menyebar ke seluruh masyarakat. Dalam beberapa tahun terakhir, berkat kegigihan para guru dan dukungan program pendidikan untuk daerah tertinggal, tingkat literasi di Muong Nhe (lama) telah berangsur-angsur membaik.
Namun, tantangannya masih sangat besar. Medan yang terpencil, adat istiadat dan praktik yang unik, serta kesadaran yang belum merata menyulitkan upaya mempertahankan jumlah siswa dan memperluas kelas literasi. Guru seperti Ibu Thoa memainkan peran yang tak tergantikan sebagai jembatan dan motivator iman bagi masyarakat di daerah perbatasan.
Bagi mereka, mengajar bukan sekadar pekerjaan, melainkan sebuah misi. Sebuah misi yang dibangun di atas pengorbanan, ketekunan, dan cinta kasih tanpa syarat.
Sumber: https://giaoducthoidai.vn/co-giao-vung-bien-va-hanh-trinh-gioo-chu-xoa-mu-giua-dai-ngan-tay-bac-post740781.html







![[Foto] Presiden Luong Cuong menghadiri Peringatan 80 Tahun Hari Adat Angkatan Bersenjata Daerah Militer 3](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/1200x675/vietnam/resource/IMAGE/2025/10/28/1761635584312_ndo_br_1-jpg.webp)























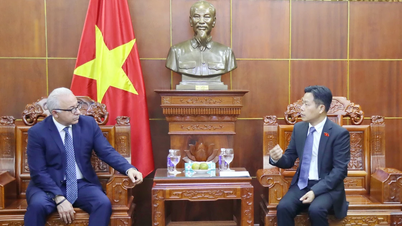


![[Foto] Komite Partai di Badan Pusat Partai merangkum pelaksanaan Resolusi No. 18-NQ/TW dan arahan Kongres Partai](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/1200x675/vietnam/resource/IMAGE/2025/10/27/1761545645968_ndo_br_1-jpg.webp)
![[Foto] Draf dokumen Kongres Partai ke-14 sampai di Kantor Pos Budaya Komune](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/1200x675/vietnam/resource/IMAGE/2025/10/28/1761642182616_du-thao-tai-tinh-hung-yen-4070-5235-jpg.webp)
![[Foto] Kongres Emulasi Patriotik ke-5 Komisi Inspeksi Pusat](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/1200x675/vietnam/resource/IMAGE/2025/10/27/1761566862838_ndo_br_1-1858-jpg.webp)











































































Komentar (0)