Ayah tertawa, "Asap jerami itu baunya enak sekali, Nak. Baunya persis seperti nasi buatan rumah kita." Ibu, di dapur, berkata dengan suara lantang, "Kalau baunya enak, makanlah banyak-banyak, kalau tidak kamu akan mengeluh lapar saat pergi ke ladang besok." Seluruh keluarga tertawa terbahak-bahak. Tawa itu berkilauan seperti sinar matahari, membuat rumah sederhana itu terasa hangat.
Lalu suatu hari, tawa itu hancur berkeping-keping seperti cangkir keramik yang jatuh ke lantai keramik. Sore itu, ketika Han pulang sekolah, pintu terbuka lebar, dan ayahnya ambruk di halaman, tangannya gemetar saat memeluk wanita yang terbaring tak bergerak seperti kayu: "Sayangku! Bangun!" Han bergegas maju, teriakan "Ibu!" tercekat di tenggorokannya. Bayangan atap tiba-tiba memanjang, menelan tangisan anak berusia sepuluh tahun itu.
Setelah pemakaman, ayahnya menjadi pria yang pendiam. Setiap malam, pulang dari pekerjaannya sebagai buruh upahan, ia akan membawa seikat tangkai padi yang lebih besar dari dirinya di pundaknya, langkah kakinya menimbulkan debu dari jalan. Han belajar memasak nasi, menyapu halaman, mencuci padi, dan menjaga api. Tanpa sentuhan ibunya, api di dapur berkobar lemah. Tetapi di rumah kecil di lereng bukit itu, suara ayahnya masih terdengar, menghiburnya: "Belajarlah giat, anakku. Kita mungkin miskin, tetapi jangan sampai kita miskin dalam pengetahuan."

ILUSTRASI: AI
Waktu berlalu, dan Hân tumbuh dewasa, kemeja putihnya ternoda keringat ayah dan anak perempuannya. Di siang hari yang terik, Hân akan memarkir sepedanya di dekat pohon flamboyan di depan gerbang sekolah, membuka tas sekolahnya, dan mengeluarkan nasi yang dibungkus daun pisang oleh ayahnya. Nasi itu, dibumbui dengan kecap ikan dan beberapa helai sawi asin, terasa semanis nasi yang baru dimasak. Di malam hari ketika lampu minyak berkelap-kelip seperti kupu-kupu, ayahnya akan tertidur, sementara Hân dengan tekun menyelesaikan soal-soal matematika, siluet rapi mereka terpantul di dinding seperti dua burung pipit yang berkerumun bersama, saling melindungi dari angin.
Setelah menyelesaikan kelas dua belas, Han mengira semuanya sudah berakhir. Dari mana dia akan mendapatkan uang untuk melanjutkan studinya? Ayahnya berkata, "Kamu bisa bekerja," suaranya lembut dan acuh tak acuh. Tetapi kata-kata di hatinya terus berdebar. Pihak berwenang desa memanggil namanya, tetangga menawarkan kata-kata penyemangat, dan surat penerimaan ke Universitas Keguruan tiba. Ayahnya memegang kertas itu, matanya yang kusam, seperti aliran air di bawah terik matahari siang, tiba-tiba berbinar-binar karena kegembiraan. Dia bahagia, tetapi kekhawatiran melekat padanya seperti gulma: "Jika kamu ingin pergi, pergilah. Aku hanya punya dua tangan." Han memegang tangan ayahnya: "Aku akan pergi, dan kemudian aku akan kembali."
Di provinsi, Han adalah murid yang baik dan menerima beasiswa. Gadis desa itu, dengan rambut yang diikat tinggi, kemeja yang dicuci dengan teliti, dan mata yang selalu cerah seperti air sungai di bawah sinar bulan, menarik banyak pengagum. Tetapi orang yang selalu ada untuk Han ketika dia lelah, ketika tiba-tiba hujan, atau ketika listrik padam di kamar sewaannya… adalah An. An tidak mengatakan sesuatu yang muluk-muluk, dia hanya akan berdiri di bawah atap dan dengan lembut memanggil, "Ayo makan. Kamu pasti lapar." Cinta mereka mekar seperti bibit padi muda yang menantang angin. Mereka berjanji untuk menikah setelah lulus.
Setelah lulus, Han melamar pekerjaan sebagai guru di kampung halamannya. Gaji untuk guru yang baru lulus memang tidak banyak, tetapi para guru di sana tidak mengukur nilai diri mereka berdasarkan uang, melainkan berdasarkan cahaya terang yang mereka pancarkan di mata murid-murid mereka. Setiap sore, Han bersepeda di sepanjang tanggul tanah merah, ao dai-nya (pakaian tradisional Vietnam) berkibar seperti sayap bangau, hatinya terasa ringan saat membayangkan makan malam bersama ayahnya yang menunggunya.
Suatu malam, ayah Hân memanggilnya, suaranya terdengar ragu-ragu:
- Hân… Kamu sudah dewasa sekarang, kamu sudah punya pekerjaan, jadi aku tidak terlalu khawatir. Ini… aku tidak tahu bagaimana menjelaskannya dengan tepat.
"Hanya ada kami berdua, ayah dan anak, di rumah ini. Jika sang ayah tidak memberi tahu anaknya, kepada siapa lagi dia harus memberi tahu?" Han tersenyum, meletakkan teko teh di atas meja.
- Ayah... memiliki perasaan terhadap Linh, putri Tuan Nam dari desa di bawah. Aku sudah lama berencana menikahkan dia, tetapi aku khawatir karena Ayah masih kuliah... Sekarang Ayah sudah mengajar, aku ingin mendengar pendapat Ayah.
Hân terkejut:
- Linh? Dia hanya beberapa tahun lebih tua dariku... dia belum menikah dan punya anak... apakah kau dan dia cocok? Atau... kau hanya merasa kasihan padanya?
Ayahku menyipitkan mata, cahaya memantul dari kerutan di sekitar matanya:
- Jangan berpikir seperti itu, Nak. Saat kau masih sekolah, Linh sering berkunjung, membawakan bubur saat ayahmu sakit. Dalam hidup, baik berjalan lancar atau tidak, tetap harus ada rasa tanggung jawab. Ayahmu sudah tua sekarang, dan kehadiran seseorang yang menemaninya membuatnya merasa tidak terlalu kesepian. Jika kau menyayangi ayahmu, sayangilah dia sepenuhnya, ya?
Hân tetap diam, mendengarkan kicauan serangga di luar pagar. Ketidaksenangannya yang awalnya muncul bercampur dengan rasa bersalah atas tahun-tahun yang telah ayahnya besarkan sendirian. Dia berbicara pelan:
- Aku tidak akan keberatan. Aku hanya berharap kamu memilih seseorang… yang baik dan pengertian.
Pernikahan itu sederhana. Linh pulang ke rumah membawa seikat bunga bougainvillea merah cerah, pipinya merona seperti pipi seseorang. Santapan untuk tiga orang diisi dengan dentingan sendok yang lembut. Linh sering tersenyum, memilih untuk melakukan hal-hal kecil, dari semangkuk kecil saus ikan hingga menjemur kemeja di bawah sinar matahari. Hân perlahan menjadi kurang malu. Melihat ayahnya bahagia, hati sang putri terasa seringan daun.
Kemudian hari pernikahan Hân tiba. Sang pengantin wanita, mengenakan gaun putih, matanya berkaca-kaca, memasang jepit bunga buatan tangan di rambutnya. Ayahnya memeluknya, bahunya sedikit bergetar seperti tertiup angin.
- Saat kau pergi, ingatlah untuk memperlakukan keluarga suamimu seperti keluargamu sendiri. Jangan biarkan siapa pun kekurangan tawa. Saat kau jauh, ingatlah untuk makan dan tidur dengan cukup. Kebahagiaan... harus dipupuk dengan tanganmu sendiri. Ayahmu... tidak bisa selalu berada di sisimu.
Hân tersenyum, air mata hangat mengalir di pipinya. Ayahnya menyeka air mata itu dengan punggung tangannya yang kapalan, aroma asap jerami dari masa lalu tercium kembali.
Suatu pagi Senin, saat Han bersiap-siap untuk kuliah, teleponnya berdering. Suara Linh di ujung telepon terdengar terputus-putus, seolah terbawa angin:
- Han… Ayah…
Ponsel itu terlepas dari tangannya dan jatuh ke lantai. An berlari dari luar dan memeluk istrinya yang telah pingsan: "Aku di sini. Ayo pulang!"
Hân berlutut dan memeluk ayahnya. Wajahnya tenang, seolah-olah dia telah menyelesaikan semua pekerjaannya. Hân berseru:
- Ayah… Mengapa kau pergi begitu tiba-tiba? Dan bagaimana denganku…?
An berperan sebagai istri, berbicara perlahan:
- Tenanglah dan dengarkan aku. Ada sesuatu... yang sudah lama kusembunyikan darimu.
An bercerita bahwa beberapa bulan sebelumnya, Tuan Tuan didiagnosis menderita tumor otak, dan dokter mengatakan bahwa ia tidak punya banyak waktu lagi. Pada saat yang sama, ayah An menderita gagal ginjal parah dan berada di kamar rumah sakit yang sama. Kedua pria lanjut usia itu, yang akan segera menjadi mertua, secara kebetulan bertemu dalam keadaan sakit masing-masing. Setelah mendengar cerita An, Tuan Tuan berkata kepadanya beberapa hari kemudian: "Biarkan aku menyelamatkannya. Aku tidak punya banyak waktu lagi! Aku akan memberikan sebagian diriku… agar putriku bisa tersenyum lagi."
An berkata sambil mengepalkan tangannya:
- Aku tak berani menerimanya. Tapi dokter bilang itu masih mungkin, ayahmu sangat bertekad. Dia menyuruhku untuk tidak memberitahumu. Dia ingin hari pernikahanmu secerah bulir padi yang matang. Dia mempercayakanmu kepadaku… Kumohon cintai dirimu seperti ayahmu mencintaimu. Aku minta maaf karena menepati janji kepada ayahmu dan menyebabkanmu menderita begitu tiba-tiba.
Hân merasa seolah-olah banjir besar sedang melanda dadanya, menghantam jantungnya hingga ia hampir tidak bisa bernapas. Hal-hal aneh yang terjadi pada hari pernikahannya—tatapan ayahnya yang lebih lama dari biasanya, nasihatnya yang lebih panjang—kini menjadi kunci untuk membuka pintu. Ia menundukkan kepala, menangis tak terkendali, diliputi campuran kesedihan, penyesalan, dan rasa syukur.
Dia menoleh ke Linh:
- Tante… Apakah Tante tahu tentang keadaan Ayah? Mengapa… Tante masih menikahinya, padahal dia…
Linh menggenggam tangan Hân, tangannya hangat seperti secangkir teh hijau yang baru saja dituangkan:
"Aku tahu. Tapi aku menikahinya karena cinta dan kesetiaan, bukan karena takut akan kesulitan. Sebelumnya... aku melakukan kesalahan. Dia pergi ketika mengetahui aku hamil. Aku bahkan pergi ke tepi sungai, berniat untuk menceburkan diri. Malam itu, tidak ada bulan, airnya sehitam tinta. Aku dan suamiku lewat, melihat pakaianku berkibar di tepi sungai, dan dia bergegas turun, menarikku ke atas, dan membawaku ke rumah sakit. Aku akan selalu ingat apa yang dia katakan: 'Anak itu tidak bersalah.' Kemudian dia meminta untuk menjadi anak laki-laki ayahnya... agar anak itu tidak merasa malu ketika pergi ke sekolah nanti. Aku bersyukur. Hidup bersamanya, aku merasa tenang. Aku tahu dia sangat mencintai anak kami. Aku di sini untuk merawat anak kami dan keluarga kami."
Kisah Linh bagaikan lampu minyak yang berkedip-kedip, bergoyang sebelum akhirnya stabil. Hân memeluk bibinya, merasa bersalah karena pikiran lamanya lenyap seperti lumpur dalam banjir yang mengamuk. Di ruang tamu, An dengan tenang menata ulang altar dan membawa secangkir air baru. Bayangan ketiganya berkerumun bersama, seperti tiga cabang dari pohon yang sama.
Pemakaman itu sederhana. Orang-orang dari desa-desa sekitar mampir, menyalakan beberapa batang dupa. Seorang lelaki tua berdiri di halaman, membiarkan angin bertiup, dan berkata, setengah kepada yang hidup, setengah kepada yang meninggal: "Dia menjalani hidup yang layak. Sekarang dia telah tiada... dia telah beristirahat dengan tenang."
Hân memegang dupa di samping foto ayahnya. Itu adalah foto yang diambil terburu-buru saat hari kelulusannya – kemeja putih, uban di rambutnya, senyum tipis, dan sekilas pemandangan jalan tanah merah di sudut matanya. Asap dupa bercampur dengan aroma jerami kering dari kenangannya, tiba-tiba memenuhi rumah dengan aroma yang aneh. Hân teringat kata-kata ayahnya dari masa kecilnya: "Asap dari jerami yang terbakar berbau seperti masakan rumahan." Sekarang, asap dari jerami yang terbakar berbau seperti kehangatan manusia.
Pada hari pemakaman ayahnya, matahari tidak terik. Gumpalan awan tipis menggantung di langit, dan angin sepoi-sepoi bertiup, seolah takut mengganggu tidur damai almarhum. Iringan jenazah berjalan dengan kaki berdebu, gumaman nyanyian memenuhi udara, dan suara anak-anak bermain petak umpet di bawah pohon kelapa masih bergema. Di suatu tempat, seekor sapi mengeluarkan jeritan panjang yang melengking, seperti rasa sakit yang tajam di dadanya. Hân meletakkan dupa di atas kuburan dan berbisik:
Ayah, aku akan menjalani hidup yang layak. Aku akan menjaga kehangatan rumah dan tetap tersenyum, seperti yang Ayah perintahkan.
Linh berdiri di sampingnya, tangannya bertumpu di bahu Hân. An mundur sedikit, membiarkan kedua wanita itu bersandar satu sama lain, seperti dua tepian kanal yang memeluk air.
Waktu berlalu. Di pagi hari, Hân pergi ke kelas, suara para siswa yang melafalkan pelajaran mereka bergema seperti kicauan burung. Di sore hari, ia pulang dan memasak, termasuk ikan kakap rebus favorit ayahnya. Di altar, tempat pembakar dupa selalu memiliki bara api yang menyala. Linh sesekali membawa si kecil ke kios bunga bougainvillea, mengajarinya memanggilnya "Kakak Hai." Anak itu akan mengoceh, "Kakak Hai." Panggilan itu seperti kupu-kupu yang hinggap di bahu Hân, membuat hatinya terasa ringan.
Suatu hari, rumah sakit kota mengirimkan surat terima kasih kepada keluarga tersebut, kata-katanya sederhana namun mengharukan: "Berkat sebagian tubuh Tuan Tuan, seorang pria lain telah diberi kesempatan untuk hidup, dan sebuah keluarga masih memiliki pilar dukungan." Han memegang surat itu, merasa seolah tangan ayahnya dengan lembut membelai rambutnya. Dia membawa surat itu ke altar dan berdoa dengan lembut:
- Sekarang aku mengerti, Ayah. Memberi bukanlah kehilangan. Memberi adalah menjaga – menjaga bagian terbaik dari dirimu dalam diri orang lain.
Malam itu, bulan terbit di balik rumpun bambu, bersinar seperti semangkuk susu di halaman. Han menarik kursi bambu ayahnya ke beranda dan duduk mendengarkan suara katak di ladang. An membawakan dua cangkir teh panas. Linh mematikan lampu di dalam rumah, membiarkan bayangan mereka bertiga memanjang di tanah. Angin bertiup dari tepi sungai, membawa aroma jerami dari sawah yang baru dipanen. Asap dupa di altar berputar membentuk garis tipis, seperti sinar matahari yang diletakkan seseorang di bahunya, meskipun malam telah tiba.
Hân mendongak ke langit dan tersenyum. Di suatu tempat, ayahnya mungkin juga tersenyum. Dan aroma jerami yang terbakar – bau masakan rumahan, aroma bahu seorang ayah – akan selamanya melekat di rumah kecil itu, dalam perbuatan baik yang diwariskan, di hati yang tahu bagaimana mencintai satu sama lain seperti ayahnya mencintai.

Source: https://thanhnien.vn/vet-nang-tren-bo-vai-cha-truyen-ngan-du-thi-cua-duong-thi-my-nhan-18525101512380187.htm

































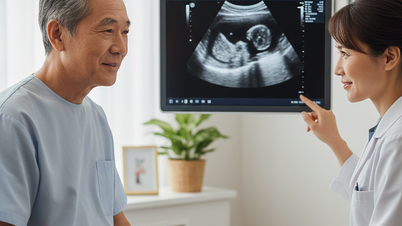





![[Video] Kerajinan pembuatan lukisan rakyat Dong Ho telah dicantumkan oleh UNESCO dalam Daftar Kerajinan yang Membutuhkan Perlindungan Mendesak.](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/402x226/vietnam/resource/IMAGE/2025/12/10/1765350246533_tranh-dong-ho-734-jpg.webp)





































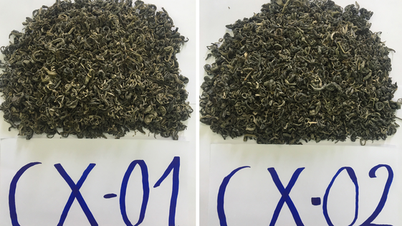






























Komentar (0)