Perahu layar kami berlayar melawan arus selama satu setengah jam, di lanskap yang, di beberapa tempat, tampak seperti pedesaan Mesir, di suatu tempat yang jauh di delta. Di sebelah kiri, bukit pasir putih menutupi laut, dan gemuruh ombak terdengar. Di sebelah kanan, pasir masih ada, terbawa angin dari laut melewati bukit pasir: tidak menumpuk, melainkan tersebar di dataran aluvial dalam bentuk bubuk halus, di mana bercak-bercak mika berkilauan di antara biru pucat.

Di gua-gua Pegunungan Marmer pada tahun 1920-an
Di sana-sini, areal persawahan dibagi menjadi jalur-jalur lebar, hamparan sawah terbentang di kaki lereng bukit yang berdebu, penambahan pasir dicegah dengan irigasi, tanah tandus diberi pupuk, tanaman tumbuh subur di daerah air payau.
Beberapa parit drainase yang dalam mengalirkan air langsung dari sungai, dan ketika tanah terlalu tinggi untuk penggunaan sistem kanal yang rumit, sumur-sumur digali dalam beberapa bagian, serangkaian ember bambu dililitkan di sekitar kerekan sederhana yang dioperasikan oleh satu orang. Terkadang, kerekan ini dioperasikan oleh seekor kerbau, yang langkahnya lambat dan siluetnya yang menonjol di langit yang luas.
Di tepi ladang, sekelompok pekerja sibuk mengeruk parit dan melapisi tepiannya dengan tanah liat. Mereka bertelanjang dada dan berjongkok, kepala mereka ditutupi topi daun palem sebesar payung, dan mereka tak lagi tampak seperti manusia, melainkan seperti bunga liar raksasa yang bercampur dengan rerumputan tinggi dan semak gorse.
Sesekali, di dekat pondok, seorang perempuan akan muncul, menyalakan api unggun atau mengambil air dari kendi. Ia akan mengganti topinya yang besar dengan selendang yang melilit kepalanya: dari kejauhan, dengan jubahnya yang gelap dan longgar memperlihatkan kulitnya yang kecokelatan, kami akan mengira ia adalah perempuan Afrika Utara yang sedang membawa air, meskipun tubuhnya kecil dan kurus.
Perahu kami berada di dalam teluk yang dalam, sekitar seperempat mil dari tiga bukit, yang tertingginya hanya 150 meter. Namun, keterpencilan mereka dan pantulan cahaya membuat mereka tampak jauh lebih besar; "gunung" adalah kata yang hampir terucap dari bibir seseorang ketika melihat balok-balok marmer ini, dengan tepian bergerigi yang aneh, menjulang di antara samudra dan dataran biru laut yang tak berujung di cakrawala.
Selama 45 menit kami mengarungi debu setinggi lutut. Tak ada tumbuhan apa pun kecuali beberapa helai rumput kering dan semak sikas berdaun jarang dan kelabu. Bukit pasir lagi, lalu kami sampai di kaki gunung utama dengan 300 anak tangga yang dipahat di batu, 20 anak tangga pertama terkubur di pasir.
Pendakiannya tidak lama, tetapi sangat melelahkan, di bawah terik matahari siang yang membakar tebing-tebing barat, memicu percikan api di setiap undulasi. Namun, semakin tinggi kami mendaki, semakin sejuk angin laut bertiup, menyegarkan dan menyegarkan, kelembapannya terkumpul di celah-celah terkecil, memungkinkan bunga-bunga dan bunga-bunga dinding bermekaran dalam semua warnanya.
Kaktus-kaktus raksasa melesat bak roket di mana-mana. Semak-semak saling tumpang tindih, akar-akar menjalar, melilit, dan menjalar di antara bebatuan; dahan-dahan saling melilit dan membentuk simpul. Dan tak lama kemudian, di atas kepala kami, kanopi semak-semak berserat yang nyaris tak terlihat, terbentang kanopi anggrek yang sedang mekar penuh, indah, rapuh bagai sayap kupu-kupu ketika angin sepoi-sepoi bertiup, bunga ini mekar lebih awal dan layu dalam sehari.
Jalan setapak yang curam mengarah ke sebuah panggung setengah lingkaran: sebuah pagoda kecil, atau lebih tepatnya tiga ruangan beratap genteng kaca dan atap berukir khas Cina, dibangun di tempat yang tenang ini atas perintah Minh Mang, Kaisar Annam, sekitar 60 tahun yang lalu. Ruangan-ruangan ini, dikelilingi beberapa taman kecil yang terawat rapi, tidak lagi digunakan untuk beribadah, melainkan menjadi tempat pertapaan enam biksu - penjaga gunung suci ini. Mereka tinggal di sana, di tempat yang tenang, melantunkan mantra dan berkebun setiap hari. Sesekali, beberapa orang baik hati membawakan mereka beberapa keranjang tanah untuk merawat kebun sayur dan beberapa makanan lezat seperti nasi dan ikan asin. Sebagai imbalannya, orang-orang ini diizinkan beribadah di aula utama, yang sulit ditemukan oleh peziarah pemula tanpa pemandu.
Kuil yang tak tertandingi ini tidak dibangun atas dasar kesalehan para raja. Alamlah yang menjalankan tugasnya; tak ada sketsa arsitek, tak ada impian penyair yang dapat menandingi mahakarya yang lahir dari bencana geologis ini. (bersambung)
(Nguyen Quang Dieu dikutip dari buku Around Asia: Cochinchina, Central Vietnam , and Bac Ky, diterjemahkan oleh Hoang Thi Hang dan Bui Thi He, AlphaBooks - National Archives Center I dan Dan Tri Publishing House yang diterbitkan pada bulan Juli 2024)
[iklan_2]
Sumber: https://thanhnien.vn/du-ky-viet-nam-du-ngoan-tai-ngu-hanh-son-185241207201602863.htm


![[Foto] Upacara penutupan Kongres ke-18 Komite Partai Hanoi](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/1200x675/vietnam/resource/IMAGE/2025/10/17/1760704850107_ndo_br_1-jpg.webp)








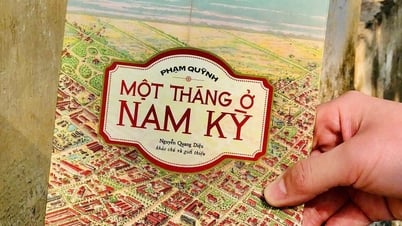

















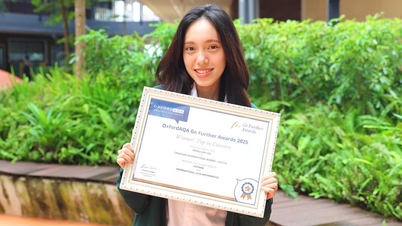





![[Foto] Surat Kabar Nhan Dan meluncurkan “Tanah Air di Hati: Film Konser”](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/1200x675/vietnam/resource/IMAGE/2025/10/16/1760622132545_thiet-ke-chua-co-ten-36-png.webp)










































































Komentar (0)