Rasa kantuk datang tanpa disadarinya, ketika Quang membuka mata, hari sudah hampir sore. Motel di dekat perbatasan tidak ramai, tetapi anehnya sepi. Baru saat itulah Quang ingat bahwa ia perlu memeriksa paspornya untuk dibawa melewati gerbang perbatasan besok, tetapi setelah mencari beberapa kali, ia tetap tidak menemukannya. Mungkin ia lupa membawanya karena ia hanya berencana bepergian dalam negeri. Quang dengan marah melempar ranselnya, menyalakan sebatang rokok, dan pergi keluar, berniat menemui sopir untuk melaporkan masalahnya lalu berganti tujuan.
"Quang, apakah itu kau, Quang?" Suara itu tiba-tiba terasa familiar. Quang menoleh, mustahil, itu Di, itu benar-benar Di. Di bergegas memeluk Quang karena terkejut. Tangan Quang terangkat pelan, lalu tiba-tiba memeluk Di. Itu Di kecil, ia seperti bola kapas yang ringan, tak mampu berkata apa-apa. Quang hanya bisa memeluk dan mengangkat Di, lalu membenamkan wajahnya di bahu Di dan terisak. Butuh waktu lama bagi Quang untuk bisa mendorong Di sedikit menjauh, menatapnya, dan berbicara:
- Kamu baik-baik saja? Kenapa kamu pergi seperti ini? Bagaimana kalau kamu terluka lagi? Bagaimana aku bisa menemukanmu? Kamu sudah pergi berbulan-bulan?
Di tersenyum, menggelengkan kepala Quang pelan. "Katakan pelan-pelan, aku tidak akan bisa menjawabnya tepat waktu," lalu menutup mulutnya dan tertawa lagi. Quang menatap Di dengan heran. Sudah lama Quang tidak melihat senyumnya secerah ini. Di secara ajaib pulih seminggu setelah Quang pergi. Semua orang ingin menghubungi Quang tetapi tidak bisa karena Quang meninggalkan ponselnya, memutus semua kontak dengannya, dan tidak sedang online di akun mana pun. Sebulan kemudian, Di diperbolehkan pulang dari rumah sakit, setelah bisa berjalan normal dan menjalani berbagai tes. Di mengira Quang hanya akan pergi sekitar dua bulan, tetapi setelah menunggu setengah tahun tanpa kabar, alih-alih pergi berlibur ke Dalat seperti yang direncanakan, Di mencoba peruntungannya di tempat yang telah mereka sepakati.
Tadinya aku mau pulang, tapi aku capek hari ini, jadi kutunda. Aku sudah di sini seminggu penuh. Untungnya aku tetap di sini untuk bertemu denganmu, rasanya seperti takdir. Di menyelesaikan ceritanya dan meringkuk di ketiak Quang dengan gembira.
"Oh, apa kau menelepon ke rumah untuk memberi tahuku apakah kau sudah melihatku? Aku khawatir keluargaku akan khawatir." Setelah mengobrol riang sejenak, Quang teringat. Di terdiam sejenak lalu dengan malu-malu berkata:
- Ponselku dicuri, tapi tak apa, aku hanya pergi selama seminggu. - Di membujuk untuk meyakinkan.
- Baiklah, aku akan meneleponmu besok. - Quang mengangguk acuh tak acuh.
Kita bisa kembali besok. Aku tidak punya paspor.
- Aku bawakan untukmu, oke? - Di tersenyum lagi.
- Bagaimana... kau tahu? - Quang terkejut.
"Aku pergi ke rumahmu untuk mencarinya, lalu ingat kamu janji mau keluar di hari ulang tahunku, jadi aku membawanya. Kamu selalu menaruhnya di laci nakas. Kita pergi besok, ya?" Di menatap Quang, memasang wajah memohon seperti anak kecil. Quang selalu melunak menanggapi permintaan Di.
Karena tidak bisa menelepon ke rumah, sinyalnya tampak lemah di dekat perbatasan, Quang mengembalikan telepon kepada pengemudi sambil bersiul, mungkin itu tidak perlu. Quang telah merencanakan perjalanan yang tidak bergantung pada teknologi, hanya bepergian, bertamasya, dan merasakan. Meskipun ia agak khawatir dengan kesehatan Di, ketika melihat senyum cerah Di, Quang menurutinya. Dengan menaiki bus wisata, keduanya memulai perjalanan yang telah ditinggalkan Di.

ILUSTRASI: AI
Siapa yang berani mengatakan naluri itu jelek, siapa yang berani mengatakan naluri itu biadab. Sejak pertama kali bertemu dunia ini, teriakan marah manusia juga merupakan naluri. Saat lapar, tangan yang meronta-ronta, tangisan memilukan hati untuk diberi makan juga merupakan naluri bertahan hidup yang memperebutkan sebagian kehidupan, dengan cepat menentukan di mana sumber kehidupan itu. Saat bibir mungil terbuka untuk mencoba menerima tetesan susu manis yang diwariskan sang ibu, tiada yang lebih berharga daripada naluri bertahan hidup. Naluri itu, yang diwariskan selama ratusan juta tahun, lebih kuat daripada hasrat apa pun. Ia selalu laten dalam tubuh setiap orang, tak pernah hilang, hanya membara, membara dalam bara api merah membara, menanti hari untuk melestarikan hasratnya yang kuat untuk hidup.
Berubah sesuai kondisi sekitar juga bagian dari naluri bertahan hidup, tetapi sejauh mana berubah agar tak kehilangan diri sendiri, tetap menjaga apa yang paling hakiki bagi diri sendiri. Angin berputar-putar dengan pertanyaan-pertanyaan sulit yang selalu hadir dalam diri Di. Hanya manusia, hewan yang paling berevolusi tinggi, yang memberi diri mereka hak untuk mencabut nyawa mereka sendiri tanpa menunggu alam melenyapkannya. Kepala penuh perhitungan, kesedihan yang hanya mereka yang bisa mengerti, hanya mereka yang kesepian di dunia yang luas ini, menyiksa diri mereka sendiri. Sehingga suatu hari ketika semuanya mencekam dengan kesedihan dan kebencian, orang-orang akan memilih jalan mereka sendiri untuk mengakhiri hidup, tak memperhatikan siapa pun dan melawan hukum bertahan hidup yang menjerit di suatu tempat di dalam diri mereka. Tak memberi naluri kesempatan untuk bersuara, untuk berekspresi atau untuk berpegang teguh pada kehidupan yang berkedip-kedip karena pikiran yang menghina itu. Benarkah begitu, Di?
Kata-kata Di mengejutkan Quang, ia selalu merasa takut, lalu merentangkan tangannya untuk melindungi. Sementara Di selalu berjuang, dalam diam, dan terkadang meluapkan kegembiraan, dari mata Di hingga bibirnya atau bibirnya yang mengerucut, semuanya bersinar dengan pancaran kegembiraan yang tak tertahankan. Kegembiraan itu dapat menyebar ke banyak orang, menciptakan harmoni yang tak tertahankan, tetapi bagi Quang, senyum itu tidak nyata. Sama sekali tidak nyata, karena Quang mengerti bahwa senyum itu membawa banyak luka di dalamnya, dan luka-luka itu tak kunjung sembuh, senyum itu selalu berdarah dengan setiap tawa riang bagai untaian kristal hangat dan bening yang membentang tanpa henti dalam cahaya.
***
Dua puluh tahun, usia di mana orang berhak untuk bebas, mencintai, melakukan sesuatu yang besar atau gila untuk menandai tonggak baru dalam kedewasaan mereka. Di juga berusia 20 tahun, juga penuh keyakinan, keyakinan pada dongeng, keyakinan pada keajaiban seperti anak-anak dari jauh yang percaya pada peri dan jin. Namun, Di merayakan ulang tahunnya yang ke-20 dengan berbaring telungkup di ruangan putih bersih, dipenuhi aroma antiseptik yang kuat, sosok-sosok berpakaian putih yang berlalu-lalang, terus-menerus bertukar pandang putus asa tentang penyakit Di. Ia tak mampu membuka mata untuk tersenyum menghibur semua orang, karena kini Di sendiri tak mampu tersenyum pada penyakitnya sendiri.
Quang tak berdaya menyaksikan senyum Di yang semakin menipis bagai selembar kertas, kulitnya semakin transparan seakan-akan setiap saat Di bisa menghilang, bisa menjadi tak terlihat tepat di depan mata Quang. Quang kesakitan saat melihat rasa sakit Di semakin menjadi, rambut cokelat halusnya kini hanya tersisa di sebuah foto yang tergantung di sudut ruangan, dan kini ada Di dengan topi wol menutupi kepalanya seharian. Jarang sekali melihat hari di mana Di mengulurkan tangan untuk menatap Quang, tersenyum dalam diam. Quang hanya bisa duduk dan menyaksikan, menanti dengan putus asa bersama Di sebuah keajaiban yang, di saat-saat teralihkan, dapat mengingat nama Di dan dengan senang hati datang. Penantian itu membunuh Quang. Penantian itu menggerogoti Quang perlahan, dari rambut Di yang semakin rontok hingga tak bersisa, dari rasa sakit yang tiba-tiba membuat wajah cantik Di yang tersenyum kusut, hingga gelengan kepala para dokter.
Quang menyadari dirinya berubah setiap hari, berubah begitu banyak hingga ia hanya bisa berharap untuk menjaga sedikit kehangatan di bibir Di, sedikit ekspresi kehidupan yang panik.
***
Apa yang terjadi di sini? Apa yang dilakukan orang-orang di sini? Apa sebenarnya altar itu? Semua pertanyaan berputar-putar di benak Quang. Wajah-wajah yang menangis menatap Quang dengan penuh simpati, lelucon gila apa ini? Quang ingin menghancurkan segalanya, jeritan Quang pecah, sesuatu yang Quang hindari, bayangan yang selalu mengikuti perjalanan Quang muncul kembali, ini mimpi buruk, ya, ini mimpi buruk, ini akan berlalu dengan cepat, Di akan membangunkan Quang dengan senyum rapuh di bibirnya, semuanya akan terbangun sekarang juga.
***
Apa itu naluri manusia? Ketika dihadapkan pada sesuatu yang melampaui ambang batas emosional, orang akan memilih untuk menghadapinya atau menghindarinya. Di memilih untuk menghadapinya secara langsung. Ia tak bisa lagi memaksakan diri untuk tersenyum, tak bisa lagi menunggu keajaiban untuk memulihkan kesehatannya, dan tahu bahwa ia tak akan mampu bertahan. Suatu hari yang sunyi, Di diam-diam berpesan kepada ibunya untuk menyumbangkan apa pun yang ia bisa untuk dunia kedokteran. Ia ingin mempercayakan dirinya pada masa depan, agar ia bisa menjadi keajaiban berikutnya bagi semua orang. Dan hari ketika Quang bertemu Di, tepat setengah tahun sejak para dokter bergegas menerima kehidupan berikutnya dalam operasi baru.
- Nggak mungkin, Di ikut aku, Di janji ketemu di rumah. Semuanya, jangan bercanda sama aku, kejam banget.
Suara Quang perlahan mengeras, lalu menghilang. Quang ambruk, rasa sakitnya hancur berkeping-keping. Bayangan perjalanan itu terasa hampa, apakah senyum Di terasa hampa? Quang tak tahu apakah ia melarikan diri dari Di atau melarikan diri dari dirinya sendiri, tas berisi foto-foto yang baru saja dicetak di Laos dan dibawa untuk Di terjatuh dan berserakan. Foto-foto itu memperlihatkan Quang tersenyum lebar, tangannya menggenggam seorang gadis berambut panjang yang asing, wajahnya berseri-seri dan ceria seperti gadis berusia 20 tahun yang berseri-seri. Ibu Di menghampiri, memegang foto itu dan menangis. Gadis itulah yang menerima kornea Di, salah satu dari lima orang yang menerima sisa-sisa kehidupan Di...

Source: https://thanhnien.vn/ban-nang-cua-gio-truyen-ngan-du-thi-cua-le-thi-kim-son-185251027210332005.htm


![[Foto] Hue: Di dalam dapur yang menyumbangkan ribuan makanan setiap hari kepada masyarakat di daerah banjir](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/1200x675/vietnam/resource/IMAGE/2025/10/29/1761738508516_bepcomhue-jpg.webp)

![[Foto] Perdana Menteri Pham Minh Chinh memimpin pertemuan untuk membahas solusi mengatasi dampak banjir di provinsi-provinsi tengah.](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/1200x675/vietnam/resource/IMAGE/2025/10/29/1761716305524_dsc-7735-jpg.webp)
![[Foto] Banjir di sisi kanan gerbang, pintu masuk Benteng Hue](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/1200x675/vietnam/resource/IMAGE/2025/10/28/1761660788143_ndo_br_gen-h-z7165069467254-74c71c36d0cb396744b678cec80552f0-2-jpg.webp)












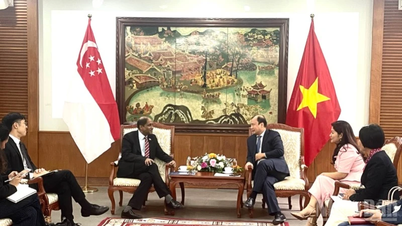































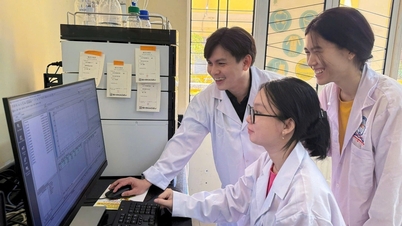



























![[Langsung] Konser Ha Long 2025: "Semangat Warisan - Mencerahkan Masa Depan"](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/402x226/vietnam/resource/IMAGE/2025/10/29/1761743605124_g-anh-sang-am-thanh-hoanh-trang-cua-chuong-trinh-mang-den-trai-nghiem-dang-nho-cho-du-khach-22450328-17617424836781829598445-93-0-733-1024-crop-1761742492749383512980.jpeg)






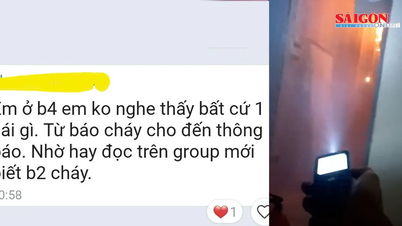





















Komentar (0)