
Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres menyaksikan upacara penyerahan jabatan presiden Majelis Umum ke-79 dari Bapak Philemon Yang kepada Ibu Annalena Baerbock_Foto: VNA
Jabatan Presiden Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa
Terbentuknya Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 1945 menandai titik balik penting dalam sejarah hubungan internasional. Setelah kehancuran dahsyat Perang Dunia II, Perserikatan Bangsa-Bangsa didirikan untuk mencegah risiko perang, menjaga perdamaian dan keamanan internasional, serta mendorong kerja sama dan pembangunan global. Dari enam organ utama yang tercantum dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa adalah badan yang paling komprehensif dan demokratis, di mana semua negara anggota memiliki hak suara yang sama, terlepas dari ukuran atau kekuatan nasional mereka secara keseluruhan.
Tidak seperti Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa - badan yang memusatkan kekuasaan pengambilan keputusan pada lima anggota tetap dan terutama menangani masalah keamanan internasional, Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa beroperasi berdasarkan prinsip kesetaraan kedaulatan, secara komprehensif mempertimbangkan isu-isu di semua bidang. Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa adalah tempat 193 negara anggota bertukar, berkonsultasi, dan mengarahkan solusi untuk masalah global, mulai dari perdamaian, keamanan, perlucutan senjata hingga pembangunan, hak asasi manusia, kemanusiaan, dan lain-lain. Meskipun resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa tidak mengikat secara hukum, resolusi tersebut memiliki makna politik dan simbolis yang mendalam, mencerminkan kehendak dan suara bersama komunitas internasional.
Sebagai kepala Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa, Presiden Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa memegang salah satu posisi kepemimpinan penting dalam sistem Perserikatan Bangsa-Bangsa. Dua dokumen yang terkait dengan posisi ini adalah Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Peraturan Prosedur Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa. Pasal 21 Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa menyatakan bahwa Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa akan memilih Presiden Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk setiap sesi, yang berlangsung kurang lebih satu tahun, dimulai pada bulan September setiap tahun. Fungsi dan tugas khusus Presiden Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa diatur dalam Peraturan Prosedur, khususnya Aturan 30 (pemilihan), Aturan 35 (menyelenggarakan sesi), dan Aturan 55 (merekomendasikan peningkatan efisiensi operasional). Dengan demikian, Presiden Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa bertanggung jawab untuk menjalankan sesi, mengarahkan diskusi, menentukan prioritas, mempromosikan pertukaran antar negara anggota, dan memfasilitasi konsensus. Posisi ini tidak hanya memiliki makna mengkoordinasikan pekerjaan Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa, tetapi juga memiliki nilai politik dan simbolis yang mendalam bagi masyarakat internasional.
Evolusi posisi Presiden Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa dari tahun 1946 hingga sekarang.
Selama 80 tahun terakhir, peran dan kegiatan Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa terus diperkuat dan diperluas, terutama cakupan agendanya yang telah meliputi sebagian besar isu-isu mendesak dan prioritas tinggi dari komunitas internasional. Seiring dengan proses tersebut, posisi Presiden Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa juga telah mengalami perkembangan yang mendalam. Dari sekadar menjalankan fungsi prosedural, Presiden Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa kini telah menjadi faktor berpengaruh dalam sistem tata kelola global, berkontribusi dalam mempromosikan reformasi kelembagaan, mengusulkan inisiatif, dan memandu diskusi tentang isu-isu strategis.
Proses pengembangan peran Presiden Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa dapat diringkas melalui tahapan-tahapan berikut:
1946 - 1950: Pada tahun-tahun awal pembentukannya, Presiden Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa terutama bertanggung jawab untuk memimpin sidang pleno, mengoordinasikan diskusi, dan memastikan kepatuhan terhadap proses dan prosedur. Presiden Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa memiliki wewenang untuk mengendalikan jalannya semua sidang, termasuk hak untuk mengusulkan waktu berbicara, daftar pembicara, menjeda, atau menunda sidang. Namun, cakupan wewenang pada saat itu terbatas pada aspek prosedural, dengan hampir tidak ada dampak signifikan pada proses pembuatan kebijakan dan pengambilan keputusan. Selama periode ini, Presiden Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa tidak memiliki Sekretariat sendiri, memiliki anggaran operasional yang terbatas, dan bergantung pada dukungan Sekretariat Perserikatan Bangsa-Bangsa dan koordinasi negara-negara anggota, terutama negara-negara besar. Oleh karena itu, peran Presiden Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa sebagian besar bersifat seremonial.
Meskipun memiliki wewenang yang terbatas, koordinasi yang terampil, keseimbangan, dan penanganan yang harmonis terhadap isu-isu prosedural dan keanggotaan telah berkontribusi dalam membentuk citra Presiden Majelis Umum sebagai sosok netral, yang menghormati prinsip konsensus dan mempromosikan dialog konstruktif. Presiden Majelis Umum dipilih setiap tahun secara bergilir di antara negara-negara anggota, berdasarkan prinsip rotasi di antara lima kelompok regional. Praktik ini bertujuan untuk memastikan representasi regional dan keseimbangan dalam kepemimpinan Majelis Umum.
Periode 1950 - 1970: Ini adalah periode pergolakan politik besar di dunia , terutama gerakan dekolonisasi dan konfrontasi Timur-Barat selama Perang Dingin, yang menyebabkan kebuntuan dan stagnasi dalam operasi banyak badan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Dalam konteks itu, peran Presiden Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa secara bertahap diperluas dan dibuat lebih substansial, terutama fungsi perantara dan koordinasi untuk menangani konflik dan krisis yang kompleks.
Tonggak penting dalam periode ini adalah Resolusi 377 (V) tahun 1950, yang dikenal sebagai Resolusi “Bersatu untuk Perdamaian”. Berdasarkan resolusi ini, pada tahun 1956, Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa mengadakan sesi khusus darurat pertamanya untuk membahas krisis Terusan Suez. Sesi tersebut mengadopsi seruan untuk gencatan senjata segera dan membentuk Pasukan Darurat Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNEF), pasukan penjaga perdamaian pertama organisasi tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa, dalam keadaan luar biasa, Presiden Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa dapat memainkan peran koordinasi, berkontribusi dalam mempromosikan solusi untuk masalah internasional yang kompleks.
Awal tahun 1960-an menandai titik balik penting ketika gelombang dekolonisasi menyebar, menyebabkan jumlah negara anggota meningkat pesat dari 51 menjadi 114 negara. Sebagai tanggapan terhadap kebutuhan baru situasi tersebut, Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa menyesuaikan struktur organisasinya, meningkatkan jumlah Wakil Presiden Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa, dan membentuk sejumlah komite khusus untuk memenuhi kebutuhan pembahasan dan penanganan isu-isu global. Seiring dengan itu, Presiden Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa diberi tanggung jawab yang lebih besar dalam mengoordinasikan agenda yang semakin kaya dan kompleks, yang mencerminkan beragam kepentingan komunitas anggota, terutama negara-negara yang baru bergabung.
Memasuki tahun 70-an abad ke-20, peran Presiden Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa terkait erat dengan tugas mengoordinasikan diskusi dan mencari konsensus tentang isu-isu penting, seperti membangun tatanan ekonomi internasional baru, perlucutan senjata, dan penghapusan apartheid. Sejak saat itu, Presiden Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa tidak hanya menjalankan jalannya sidang, tetapi juga memegang posisi sebagai jembatan untuk mendorong dialog, mendamaikan kepentingan negara maju dan negara berkembang, dan berkontribusi pada pemeliharaan kerja sama dalam kerangka Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa.
Periode 1986 - 1999: Ini adalah periode yang menandai pergeseran penting dalam peran Presiden Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa, dari lingkup yang sebagian besar bersifat seremonial dan formal menjadi mengemban fungsi administratif substantif, berpartisipasi langsung dalam penanganan krisis dan mengoordinasikan inisiatif untuk mereformasi aparatur organisasi.
Pada tahun 1986, Perserikatan Bangsa-Bangsa menghadapi krisis keuangan yang serius, dengan pemotongan anggaran, banyak kegiatan yang stagnan, dan banyak unit yang menghadapi risiko pengurangan staf besar-besaran. Dalam konteks tersebut, Presiden Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa memainkan peran perantara penting antara berbagai kelompok kepentingan, mengoordinasikan negosiasi anggaran, berkontribusi untuk melindungi tingkat kepegawaian yang penting dan mempertahankan operasional organisasi. Hasil ini meletakkan dasar bagi reformasi lebih lanjut dalam mekanisme anggaran, meningkatkan transparansi keuangan dan meningkatkan efisiensi pengelolaan sumber daya Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam dekade-dekade berikutnya.
Setelah berakhirnya Perang Dingin, Perserikatan Bangsa-Bangsa secara umum dan Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa secara khusus menghadapi kebutuhan akan reformasi yang kuat untuk meningkatkan efisiensi operasional, beradaptasi dengan tatanan dunia multipolar yang muncul, dan pada saat yang sama memenuhi realitas peningkatan jumlah negara anggota yang terus berlanjut. Resolusi No. 45/45 (1990) dan Resolusi No. 48/264 (1994) meletakkan dasar bagi proses "mereformasi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa", dengan fokus pada penyederhanaan agenda, penyederhanaan proses kerja, penguatan koordinasi dengan Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa, peningkatan kualitas diskusi dan efektivitas pengambilan keputusan. Reformasi ini menandai titik balik dalam peran Presiden Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa, menjadi seorang administrator sejati, secara aktif mengoordinasikan agenda, memimpin diskusi, membangun konsensus, dan mempromosikan perbaikan internal. Peningkatan wewenang dan tanggung jawab ini membantu Presiden Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa memiliki suara yang lebih jelas dalam isu-isu global, mewakili kepentingan bersama komunitas internasional, sekaligus berkontribusi untuk membatasi pengaruh kelompok kepentingan individu.
Dalam konteks Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa yang semakin menegaskan peran sentralnya dalam mengoordinasikan diskusi dan memecahkan masalah global, Presiden Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa terus berkontribusi dalam mempromosikan inovasi dalam tata kelola global. Peran ini secara jelas ditunjukkan melalui kepemimpinan dan koordinasi langsung serangkaian konferensi internasional besar seperti Konferensi Dunia tentang Perempuan (1995), Konferensi Milenium (2000)... Poin baru yang penting dari konferensi-konferensi ini adalah perluasan partisipasi organisasi non-pemerintah dalam proses pembuatan kebijakan global, yang secara jelas ditunjukkan dalam agenda dan dokumen yang diadopsi pada konferensi tersebut.
Periode dari tahun 2000 hingga sekarang: Dalam konteks globalisasi yang semakin mendalam, Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa terus mengalami reformasi yang kuat, sementara posisi Presiden Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa diinstitusionalisasi ke arah penguatan peran, wewenang, dan cakupan kegiatannya. Dua resolusi penting Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa, Resolusi No. 60/286 dan Resolusi No. 60/257 (2006), menandai langkah maju baru, ketika untuk pertama kalinya anggaran reguler Perserikatan Bangsa-Bangsa mengalokasikan 5 posisi khusus untuk Kantor Presiden Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa, alih-alih hanya mengandalkan personel yang diperbantukan atau pendanaan sukarela seperti sebelumnya. Regulasi ini membantu Presiden Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa mempertahankan aparat profesional yang stabil dan kemampuan untuk menanggapi isu-isu kompleks sistem multilateral. Presiden Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa didorong untuk secara proaktif mengusulkan dan menyelenggarakan diskusi tematik tentang isu-isu internasional penting; secara berkala melaporkan keuangan dan sumber pendanaan kepada publik; sekaligus memantau kegiatan Komite Prosedur dan lembaga-lembaga terkait. Selain itu, Presiden Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa diberi tanggung jawab penting untuk memimpin negosiasi tentang reformasi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa, mempromosikan proses reformasi komprehensif, dan meningkatkan transparansi dalam kegiatan Perserikatan Bangsa-Bangsa.
Tahun 2016 menandai titik balik penting dalam sejarah Perserikatan Bangsa-Bangsa ketika, berdasarkan wewenang yang diberikan oleh Resolusi 69/321, Presiden Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa, untuk pertama kalinya, mengadakan dialog publik dengan para kandidat Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa. Inisiatif ini menetapkan preseden baru dalam mendemokratisasi dan membuat proses pemilihan posisi kepemimpinan senior dalam sistem Perserikatan Bangsa-Bangsa menjadi transparan. Sesi dialog tersebut menarik sekitar 1,4 juta penonton daring dan menerima lebih dari 2.000 pertanyaan dari negara-negara anggota dan organisasi non-pemerintah. Hasilnya, Sekretaris Jenderal terpilih dengan tingkat konsensus yang tinggi, yang mencerminkan harapan masyarakat internasional akan Perserikatan Bangsa-Bangsa yang modern dan lebih efektif dalam kepemimpinan dan tata kelola.
Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa juga mengadopsi Resolusi 70/305 untuk lebih meningkatkan peraturan tentang transparansi dan mekanisme kontrol dalam operasi internal. Resolusi tersebut menetapkan bahwa Presiden Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa harus mengucapkan sumpah di depan umum sebelum menjabat dan mematuhi Kode Etik yang dikeluarkan oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa; sumbangan sukarela kepada Kantor Presiden Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa harus diungkapkan secara rinci dan tunduk pada pengawasan lembaga audit independen. Penyesuaian ini dipandang sebagai langkah maju dalam meningkatkan disiplin, memastikan transparansi, dan memperkuat kepercayaan masyarakat internasional terhadap tata kelola Perserikatan Bangsa-Bangsa.
Sejak tahun 2020, Presiden Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa terus menegaskan perannya dalam tata kelola dan koordinasi upaya global untuk menanggapi tantangan berlapis dan yang terus muncul. Ketika pandemi COVID-19 merebak, Presiden Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa secara proaktif menggunakan pertemuan daring atau kombinasi pertemuan tatap muka dan daring, memastikan bahwa kegiatan Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa berlangsung terus menerus dan tanpa gangguan. Pada tahun-tahun berikutnya, Presiden Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa terus mengkoordinasikan dan memimpin banyak proses internasional penting, termasuk KTT Masa Depan dan adopsi Dokumen untuk Masa Depan pada September 2024. Dalam konteks persaingan strategis yang semakin sengit antara negara-negara besar, peran mediasi Presiden Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa menjadi semakin penting dalam menjaga dan memperkuat kerja sama multilateral, sekaligus berkontribusi untuk menyelesaikan tren fragmentasi dan perpecahan dalam hubungan internasional.
Sejarah delapan dekade terakhir menunjukkan bahwa, dari posisi awalnya yang murni bersifat seremonial dan prosedural, peran Presiden Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa secara bertahap berkembang menjadi pusat koordinasi, tata kelola, proaktif dalam mengusulkan inisiatif, dan mempromosikan inovasi. Nilai inti dari gelar Presiden Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa terletak pada kemampuan untuk secara adil mewakili 193 negara anggota, membangun konsensus, mempromosikan dialog, dan melindungi prinsip-prinsip bersama dalam lingkungan internasional yang bergejolak.
Perkembangan peran Presiden Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa mencerminkan proses pergerakan dan adaptasi Perserikatan Bangsa-Bangsa. Pada periode ketika dunia menghadapi krisis keamanan dan politik, konflik Timur-Barat, atau tantangan pembangunan sosial-ekonomi, Presiden Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa telah mengambil peran sebagai perantara yang fleksibel, jembatan untuk mendamaikan kepentingan antara berbagai kelompok negara. Jejaknya terlihat jelas melalui koordinasi topik-topik utama, seperti dekolonisasi, pembentukan tatanan ekonomi internasional baru, mempromosikan rekonsiliasi, atau memimpin reformasi aparatur Perserikatan Bangsa-Bangsa. Kemampuan untuk memberikan pengaruh dari posisi Presiden Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa tidak hanya berasal dari otoritas kelembagaan, meskipun ada beberapa keterbatasan, tetapi juga bergantung pada kapasitas diplomatik, netralitas, kemampuan membangun kepercayaan, dan keterampilan untuk mendamaikan kepentingan antara kelompok negara maju dan negara berkembang.
Seiring dengan proses "mereformasi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa" dan mereformasi Perserikatan Bangsa-Bangsa dari akhir abad ke-20 hingga abad ke-21, kekuasaan dan tanggung jawab Presiden Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa terus diperluas secara substansial, mulai dari membangun agenda yang efisien, memimpin dialog pleno, meningkatkan transparansi hingga berpartisipasi dalam mempromosikan reformasi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa, mengoordinasikan negosiasi global, beradaptasi dengan persaingan strategis dan memimpin inisiatif utama, seperti Agenda 2030 untuk Pembangunan Berkelanjutan, Pakta Global tentang Migrasi, Konvensi tentang Kejahatan Siber, KTT Masa Depan, dll.

Anggota Politbiro dan Presiden Luong Cuong bertemu dengan Presiden Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa Annalena Baerbock selama kunjungannya untuk menghadiri Debat Umum Tingkat Tinggi sesi ke-80 Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa. Foto: VNA
Mengemban Jabatan Presiden Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa: Prospek dan Persyaratan
Dalam konteks dunia yang berubah dengan cepat, posisi Presiden Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa semakin strategis, tidak hanya dalam peran koordinasinya, tetapi juga dalam kemampuannya untuk mendorong dialog, mempersempit perbedaan, dan mengkonsolidasikan prinsip-prinsip dasar Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa. Mempertimbangkan untuk mencalonkan diri dan menduduki posisi Presiden Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa merupakan kesempatan untuk menegaskan kapasitas, prestise, dan identitas nasional di arena internasional. Untuk menduduki posisi Presiden Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa, diperlukan banyak landasan dan kondisi yang menguntungkan.
Pertama, diplomasi multilateral merupakan bagian penting dari diplomasi nasional. Pengangkatan posisi Presiden Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa perlu ditempatkan dalam konteks pengembangan kebijakan luar negeri multilateral yang lebih proaktif dan mendalam, bergeser dari pola pikir "partisipasi" ke "partisipasi proaktif, kontribusi aktif, meningkatkan peran negara dalam membangun dan membentuk lembaga multilateral serta tatanan politik dan ekonomi internasional"; berupaya memainkan peran inti, utama, atau mediasi dalam organisasi dan forum multilateral yang memiliki signifikansi internasional.
strategi.
Kedua, memberikan kontribusi yang substansial dan efektif di semua bidang kegiatan pilar Perserikatan Bangsa-Bangsa, yang ditunjukkan melalui partisipasi yang semakin mendalam dan proaktif dalam kegiatan organisasi multilateral terbesar di planet ini; menjunjung tinggi prinsip-prinsip kepatuhan terhadap Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa dan hukum internasional, sambil secara aktif mempromosikan inisiatif tentang perdamaian, pembangunan berkelanjutan, kesetaraan gender, respons terhadap perubahan iklim, dan mempromosikan peran Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) di forum-forum Perserikatan Bangsa-Bangsa. Kontribusi yang substansial dan efektif di semua bidang kegiatan pilar Perserikatan Bangsa-Bangsa juga ditunjukkan dalam banyak kegiatan lain, seperti mengirim pasukan untuk berpartisipasi dalam pasukan penjaga perdamaian di misi-misi di negara-negara dan wilayah di seluruh dunia. Ini merupakan demonstrasi yang jelas tentang komitmen, tanggung jawab, dan semangat kontribusi negara anggota terhadap perdamaian dan keamanan global; pada saat yang sama, menunjukkan peran proaktif dalam mempromosikan dialog dan inisiatif yang sejalan dengan prioritas komunitas internasional dalam konteks baru, seperti kerja sama dalam kecerdasan buatan (AI), pencegahan dan pengendalian penyakit, dan tantangan keamanan non-tradisional lainnya.
Ketiga, pengalaman dan prestise dalam menjalankan tanggung jawab multilateral dalam kerangka Perserikatan Bangsa-Bangsa. Hal ini ditunjukkan melalui pengalaman dan prestise dalam menjalankan tanggung jawab multilateral dalam kerangka Perserikatan Bangsa-Bangsa, seperti anggota tidak tetap Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa, anggota Dewan Hak Asasi Manusia, Dewan Ekonomi dan Sosial (ECOSOC), memegang posisi penting lainnya di Majelis Umum dan badan-badan khusus lainnya dari Perserikatan Bangsa-Bangsa. Pengalaman dan prestise dalam menjalankan tanggung jawab multilateral dalam kerangka Perserikatan Bangsa-Bangsa juga ditunjukkan melalui partisipasi aktif dalam proses pembentukan mekanisme kerja sama, membangun aturan dan standar bersama, seperti membangun kode etik, menyelenggarakan konferensi internasional tingkat tinggi, dan lain sebagainya.
Namun, mengemban tanggung jawab sebagai Presiden Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa juga menghadirkan banyak kesulitan, terutama dalam konteks dunia yang mengalami perubahan mendalam dan luas, dengan banyak faktor yang tidak dapat diprediksi, dan tantangan multidimensi yang sangat memengaruhi kerja sama internasional dan peran Perserikatan Bangsa-Bangsa.
Pertama, konflik dan isu keamanan non-tradisional terus menimbulkan tantangan besar bagi kerja sama multilateral. Persaingan strategis di antara kekuatan-kekuatan besar meningkatkan kompleksitas peran mediasi Perserikatan Bangsa-Bangsa; negara-negara kecil dan menengah berada di bawah tekanan untuk "memilih pihak", sementara munculnya inisiatif multilateral kecil telah sedikit memengaruhi pengaruh global Perserikatan Bangsa-Bangsa, sehingga memerlukan penguatan lebih lanjut kapasitas koordinasi dan pemeliharaan kerja sama multilateral untuk menghindari risiko polarisasi global.
Laporan Risiko Global 2025 dari Forum Ekonomi Dunia memprediksi bahwa cuaca ekstrem akan menjadi risiko utama dalam dekade mendatang. Program Pangan Dunia menyatakan bahwa kelaparan dan kemiskinan memengaruhi sekitar 720 juta orang di seluruh dunia. Serangan siber diperkirakan akan meningkat sebesar 30% antara tahun 2023 dan 2025, sementara perkembangan pesat AI, transformasi digital, dan transformasi hijau menimbulkan tuntutan mendesak untuk kerja sama dalam tata kelola global. Ini adalah faktor yang diperkirakan akan mempersulit agenda Majelis Umum PBB khususnya dan PBB pada umumnya.
Kedua , proses “UN80” yang diprakarsai oleh Sekretaris Jenderal PBB pada Maret 2025, dengan tujuan meningkatkan efisiensi operasional, meninjau fungsi, tugas, dan merestrukturisasi sistem PBB, diharapkan akan berdampak langsung pada kegiatan Majelis Umum PBB. Penyesuaian ini kemungkinan akan berdampak besar pada metode operasional, struktur organisasi, dan mekanisme partisipasi negara-negara anggota, sehingga membentuk kembali peran dan operasi Majelis Umum PBB di masa mendatang.
Dihadapkan pada peluang dan tantangan yang saling terkait, mengikuti pemilihan dan mengemban peran sebagai anggota aktif dan bertanggung jawab dalam lembaga dan posisi internasional penting dalam sistem Perserikatan Bangsa-Bangsa, termasuk posisi Presiden Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa, tidak hanya sejalan dengan kepentingan nasional, tetapi juga berkontribusi untuk mempromosikan integrasi internasional yang mendalam dan komprehensif berdasarkan kebijakan luar negeri yang independen, mandiri, damai, kooperatif, dan berorientasi pembangunan; pada saat yang sama, hal itu menunjukkan posisi dan prestise negara di arena internasional.
Terpilih sebagai Presiden Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa akan membantu negara-negara anggota untuk berpartisipasi lebih dalam dalam proses perencanaan agenda dan pengorganisasian pelaksanaan keputusan Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa, sehingga berkontribusi dalam menyelesaikan isu-isu politik, ekonomi, dan sosial yang penting di dunia dan kawasan. Ini juga merupakan kesempatan untuk memperkuat hubungan dan mengkonsolidasikan relasi antara negara-negara anggota dan Perserikatan Bangsa-Bangsa, sekaligus mempromosikan hubungan bilateral dengan negara-negara anggota. Untuk mengemban tanggung jawab ini, negara-negara anggota perlu mempersiapkan diri dengan cermat dalam hal isi, kapasitas, dan metode koordinasi, terutama dalam konteks perubahan yang tidak dapat diprediksi di dunia dan Perserikatan Bangsa-Bangsa.
----------------------------
* Dr. Hoang Thi Thanh Nga, Pham Binh Anh, Vu Thuy Minh, Nguyen Hong Nhat, Pham Hong Anh, Mai Ngan Ha, Le Thi Minh Thoa
Sumber: https://tapchicongsan.org.vn/web/guest/the-gioi-van-de-su-kien/-/2018/1154702/chu-tich-dai-hoi-dong-lien-hop-quoc--y-nghia%2C-co-hoi%2C-vinh-du-doi-voi-quoc-gia-thanh-vien-dam-nhiem-trong-trach.aspx



























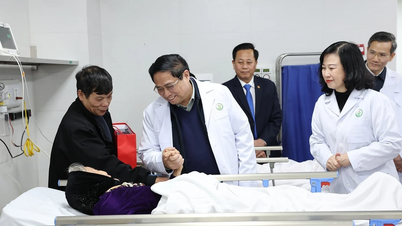










![[Video] Kerajinan pembuatan lukisan rakyat Dong Ho telah dicantumkan oleh UNESCO dalam Daftar Kerajinan yang Membutuhkan Perlindungan Mendesak.](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/402x226/vietnam/resource/IMAGE/2025/12/10/1765350246533_tranh-dong-ho-734-jpg.webp)









































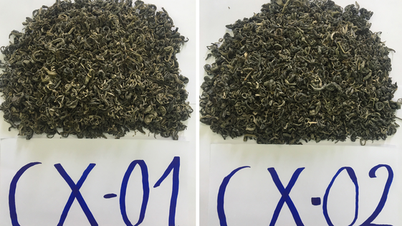






























Komentar (0)