
Isu nilai ujian masuk universitas di Vietnam mencerminkan perjalanan transformasi yang panjang - Ilustrasi oleh AI
Kenangan akan masa ketika "sulit bernapas"
Mari kita kembali ke masa awal tahun 2000-an, ke universitas-universitas bergengsi dengan budaya penilaian yang ketat seperti Arsitektur, Teknik, dan Kedokteran. Di sana, "kelonggaran dalam pemberian nilai" hampir menjadi norma tak tertulis yang dipertahankan selama beberapa generasi.
Bahkan proyek arsitektur yang paling teliti dan dipoles sekalipun hampir tidak dapat melampaui skor 7. Skor 8 sudah merupakan pencapaian yang patut dipuji, sementara skor 9 sangat langka sehingga menjadi legendaris, sering kali "disimpan" oleh para guru sebagai bukti keunggulan bagi generasi mendatang untuk ditiru.
Di balik ketegasan itu terdapat filosofi pendidikan yang jelas: kehidupan nyata jauh lebih menantang. Nilai "sebenarnya" akan membantu siswa menilai kemampuan mereka secara realistis, mengatasi rasa puas diri, dan terus meningkatkan diri. Pada dasarnya, ini adalah pelajaran tentang kerendahan hati dan kemauan untuk belajar.
Namun, filosofi ini bukannya tanpa kekurangan. Hal ini menciptakan paradoks yang menggugah pikiran: transkrip nilai yang "sederhana" tersebut, yang dipenuhi dengan banyak nilai 5 dan 5, menjadi beban bagi siswa ketika memasuki pasar kerja atau mengejar beasiswa untuk belajar di luar negeri.
Di mata banyak pemberi kerja atau universitas internasional – terutama di Eropa, di mana persyaratan IPK minimum sering diberlakukan – nilai-nilai tersebut mudah disalahartikan sebagai keterbatasan kemampuan, tanpa disadari menutup banyak peluang berharga bagi siswa yang berbakat.
Titik balik sistem kredit dan paradoks yang genting.
Titik balik penting terjadi dengan adopsi luas sistem pelatihan berbasis kredit dan skala penilaian 4 poin. Angkatan kami tahun 2009 di Sekolah Arsitektur adalah salah satu yang pertama mengalami transisi ini. Sebuah paradoks muncul: sementara sekolah masih mempertahankan standar penilaian "sulit" pada skala 10 poin, untuk mencapai nilai A (4,0) pada skala 4 poin, mahasiswa harus mencapai minimal 8,5/10.
Konsekuensinya dapat diprediksi. Transkrip nilai kami menjadi sangat "biasa" ketika diurutkan berdasarkan abjad. Bahkan siswa terbaik pun hanya mendapat nilai B (3.0) - artinya cukup untuk lulus, sesuai dengan persyaratan beberapa universitas Amerika (siswa harus mempertahankan IPK minimum 3.0/4.0 untuk lulus).
Kami, para siswa, mendapati diri kami dalam dilema: meskipun telah berusaha sebaik mungkin, nilai kami tidak dapat dibandingkan dengan nilai sekolah lain, bahkan membuat kami dirugikan ketika melamar studi di luar negeri atau pekerjaan di perusahaan multinasional. Para guru pun sama bingungnya, terjebak di antara kebiasaan penilaian lama mereka dan tekanan dari sistem baru.
Era "inflasi poin" dan konsekuensinya yang tak terduga.
Meskipun kenangan akan nilai-nilai "yang tak tertahankan" dari generasi sebelumnya masih membayangi, realitas pendidikan tinggi saat ini mengungkapkan paradoks yang kontras.
Di media, kita sering menjumpai angka-angka yang mencengangkan: persentase mahasiswa yang lulus dengan predikat kehormatan dan penghargaan di banyak universitas besar terus meningkat, bahkan beberapa universitas akan melampaui 80% pada tahun 2025.
Analisis cermat terhadap data peringkat lulusan beberapa tahun terakhir mengungkapkan tren yang menonjol: peningkatan yang berkelanjutan, terkadang dramatis, dalam persentase mahasiswa yang meraih penghargaan akademik tinggi.
Khususnya di lembaga-lembaga pelatihan utama yang berspesialisasi dalam bidang ekonomi , persentase mahasiswa yang lulus dengan nilai sangat baik dan baik tidak hanya tinggi tetapi juga sangat besar, mencakup mayoritas dari total jumlah lulusan yang menerima gelar.
Perbedaan ini mau tidak mau menimbulkan pertanyaan tentang keseragaman standar evaluasi di berbagai bidang studi, dan terlebih lagi, tentang makna sebenarnya dari gelar yang unggul di pasar kerja saat ini.
Akar permasalahannya sama sekali tidak misterius. Penyebabnya terletak pada sistem penilaian itu sendiri. Dengan aturan bahwa seorang siswa hanya perlu mencapai nilai 8,5/10 untuk mendapatkan nilai A – nilai tertinggi – kecenderungan untuk "melonggarkan" kriteria penilaian secara tidak sengaja telah didorong. Akibatnya, kelas dengan 50%, atau bahkan 70-80%, siswa yang mendapatkan nilai A bukanlah hal yang jarang terjadi lagi.
Konsekuensi dari "inflasi nilai" tidak hanya berhenti pada memiliki transkrip yang sempurna. Hal ini merusak fungsi inti dari nilai: membedakan kemampuan sebenarnya. Ketika semua orang dianggap unggul, tidak ada seorang pun yang benar-benar unggul di mata pemberi kerja.
Mereka terpaksa menggali lebih dalam, menggunakan alat penyaringan canggih seperti tes bakat, wawancara perilaku, atau pusat penilaian untuk melakukan tes tambahan, yang menyebabkan peningkatan signifikan dalam biaya dan waktu perekrutan. Oleh karena itu, nilai sebenarnya dari gelar universitas dipertanyakan.
"Kurva Lonceng" - Sebuah keajaiban ataukah obat pahit yang harus ditelan?
Dalam konteks ini, metode penilaian "kurva lonceng" disebutkan sebagai solusi teknis yang layak untuk mengendalikan inflasi. Inti dari kurva lonceng bukanlah perubahan metode pengajaran atau penilaian. Kita juga tidak perlu mereformasi atau mengubah metode penilaian atau evaluasi yang ada; perubahannya terletak pada proses konversi dan pemeringkatan akhir.
Alih-alih ambang batas nilai A tetap yang langsung dikonversi ke nilai huruf A, B, C, D, metode ini memberi peringkat siswa berdasarkan distribusi kemampuan relatif di seluruh kelas. Hanya persentase tertentu (misalnya, 10-15%) yang menerima nilai A, mayoritas akan berada di level B dan C, dan sebagian kecil di level D.
Pendekatan ini, yang diterapkan di banyak universitas internasional seperti Stanford, Harvard, dan bahkan di RMIT Vietnam, membantu memastikan bahwa nilai secara relatif akurat mencerminkan posisi siswa dalam kelompok, sehingga mengendalikan situasi "semua nilai A" atau kelas yang penuh dengan nilai 5 atau nilai 5 yang hanya sekadar lulus mata kuliah.
Manfaatnya jelas: mengembalikan diferensiasi, meningkatkan nilai kualifikasi, dan memberikan tolok ukur yang lebih andal bagi para pemberi kerja.
Namun, ceritanya tidak selalu mulus. Kurva Bell juga memiliki sisi negatif yang tak terbantahkan. Kurva ini dapat menciptakan persaingan yang tidak perlu dan terkadang tidak adil.
Dalam kelas yang penuh dengan siswa-siswa berprestasi (seperti kelas berkualitas tinggi atau kelas untuk siswa berbakat), seorang siswa yang benar-benar mampu, bahkan dengan nilai ujian yang tinggi, mungkin hanya menerima nilai B atau C jika mereka bukan termasuk siswa terbaik di kelas, atau jika banyak siswa lain mencapai nilai yang lebih tinggi. Metode ini juga memiliki keterbatasan, seperti berpotensi menyulitkan siswa berbakat di lingkungan yang penuh dengan individu-individu yang sama berbakatnya; atau ketika kelas memiliki terlalu sedikit siswa.
Jadi, apa solusinya?
Kurva Bell bukanlah solusi ajaib, dan menerapkannya secara kaku hanya akan mengganti satu masalah dengan masalah lain. Solusinya mungkin terletak pada filosofi evaluasi yang lebih seimbang dan fleksibel.
Pertama , fleksibilitas diperlukan dalam penerapannya. Distribusi nilai dalam kurva lonceng tidak boleh berupa angka yang kaku (misalnya, jika ada ujian, hanya 10% siswa yang bisa mendapatkan nilai A, 30% bisa mendapatkan nilai B) untuk setiap mata pelajaran dan setiap kelas; sebaliknya, perlu disesuaikan dan diseimbangkan berdasarkan kekhususan setiap bidang (teknik, seni, bisnis, dll.), ukuran kelas, dan bahkan kualitas mahasiswa yang masuk.
Kedua , dan mungkin yang lebih penting, kita perlu mengubah cara berpikir kita tentang tujuan nilai. Nilai seharusnya bukan tujuan utama, tetapi hanya sebagai sarana umpan balik terhadap proses pembelajaran. Nilai inti pendidikan tinggi terletak pada pengetahuan, keterampilan, dan pemikiran yang diperoleh siswa, bukan pada angka yang bagus di ijazah.
Pada akhirnya, menemukan metode evaluasi yang secara akurat mengakui upaya individu sekaligus memastikan objektivitas, transparansi, dan daya diskriminasi adalah kunci untuk meningkatkan nilai sebenarnya dari gelar universitas Vietnam di era baru. Ini adalah perjalanan yang membutuhkan kolaborasi, tidak hanya dari administrator pendidikan, tetapi juga dari dosen, mahasiswa, dan komunitas bisnis.
Sumber: https://tuoitre.vn/chuyen-diem-so-o-dai-hoc-viet-nam-tu-thoi-ky-kho-tho-den-cau-chuyen-lam-phat-diem-20251010231207251.htm























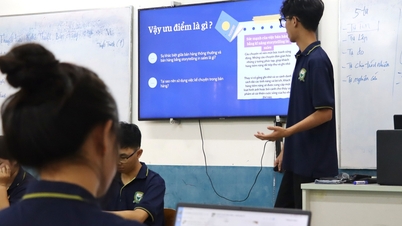








































































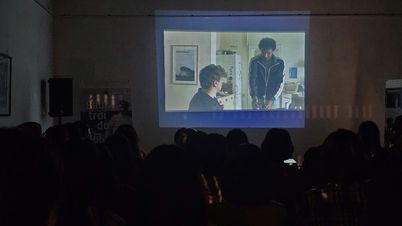














Komentar (0)